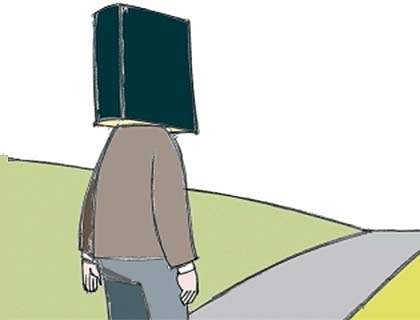
Oleh : Asratillah
Antara tahun 1988 hingga 1993, pernah ada sebuah proyek yang berkenan dengan fundamentalisme, dipimpin oleh E. Marty dan R. Scott Appleby. Proyek tersebut berhasil mengadakan 10 konferensi dan melibatkan 100 ahli dengan latar belakang yang berbeda-beda. Proyek tersebut lalu dituangkan dalam 5 buku yakni, Fundamentalisms Observed (1995), Fundamentalisms and Society: Reclaiming the Science, the Family and Education (1993), Fundamentalisms and the state: Remaking Politics, Economics, and Militance (1993), Accounting for Fundamentalisms: The Dynamic Character of Movements (1994), dan Fundamentalisma Comprehended (1995). Walaupun beberapa hasil dari proyek tersebut telah dikritik dan direvisi tapi ada beberapa kesimpulan yang penting kita ketahui tentang fundamentalisme.
Kesimpulan pertama, Marty dan Appleby menyatakan bahwa fundamentalisme tidak identik dengan agama ataupun negara tertentu. Fundamentalisme bisa lahir dan bertumbuh kembang melalui agama atau negara apapun. Dan perihal yang bisa membuatnya bertumbuh adalah memerangi situasi tanpa Tuhan (Godles) alias budaya sekuler, maka dari itu hukum Tuhan mesti tegak bukan hanya dalam skala pribadi tetapi juga dalam skala negara.
Bagi saya yang jadi problem di sini adalah, siapa yang paling otoritatif dalam menentukan, mana budaya bahkan negara yang tanpa Tuhan (godless) dan mana yang bertuhan ?. Sebut saja Pancasila dalam konteks Indonesia, walaupun di pasal pertama secara eksplisit disebutkan diksi “Tuhan”, tetapi oleh beberapa kelompok dianggap sebagai produk “kafir” atau sekuler. Dengan kata lain fundamenralisme punya tuntutan yang tidak mudah, Tuhan dianggap perlu ikut campur dalam tetek bengek urusan kenegaraan.
Kemudian soal sekularisasi, meminjam pendapat Bassam Tibi dalam Islam and Secularization : Religion and Functional Differentition of the Social System (1980), bahwa tidak sedikit yang salah paham terhadap sekularisasi. Banyak yang menyangka sekularisasi kongruen dengan penafian eksistensi agama, bahkan sekularisasi diartikan sebagai “melawan Tuhan atau agama”. Tibi menegaskan bahwa dalam sekularisasi tidak ada gagasan untuk menghapus agama, merelatifkan agama ataupun menolak peran Yang Ilahi dalam kehidupan keseharian warga negara. Bahkan dalam gagasan sekularisasi tidak sama sekali berniat untuk membenturkan antara “yang ilahi” dengan “yang insani” dan berujung Zero Sum Game, di mana salah satunya mesti kalah dan disingkirkan.
Sekularisasi bagi Tibi dan ini sedikit banyaknya sejalan dengan gagasan Nurcholis Madjid dalam Doktrin, Islam dan Peradaban, bahwa sekularisasi sederhanya adalah menempatkan secara proporsional yang sakral sebagai yang sakral dan yang profan sebagai yang profan, tidak melegitimasi tindakan profan (semisal politik) sebagai sesuatu yang sakral. Bisa dikata bahwa sekularisasi adalah sebuah sikap dalam menyikapi perkembangan dunia yang semakin kompleks dan cepat, yang tidak dapat begitu saja disikapi dengan paradigm God’s rule, dimana segala hal direspon secara formal dan otoritatif-absolut (hakimiyyat order) serta berujung pada penyangkalan terhadap dunia.
Kesimpulan kedua, Marty dan Appleby menyatakan bahwa, fundamentalisme menganggap bahwa interpretasi terhadap sabda Tuhan adalah sesuatu yang terlarang. Wahyu mesti dibaca apa adanya, literal alias harfiah. Namun kalua kita memperhatikan wacana keagamaan yang diproduksi oleh kelompok-kelompok fundamentalis, maka mereka juga sebenarnya mempraktekkan metode tafsir atau interpretasi atas sabda Tuhan versi mereka sendiri. Anggapan bahwa makna sebenarnya dari teks kitab suci sama dengan bunyi harfiah teks tersebut, adalah bentuk pendirian tafsir tersendiri. Sehingga yang fundamentalisme lakukan selanjutnya adalah merebut klaim kebenaran dan klaim keselamatan.
Mungkin fundamentalisme tidak mau pusing dengan asumsi-asumsi dalam studi hermeneutika, bahwa ada rentang waktu yang cukup panjang antara momen mula terbentuknya teks keagamaan, dengan pembaca di abad 21 saat ini. Bahwa ada horizon sosio-kultural yang berbeda secara mencolok, antara audiens awal teks keagamaan dengan audiens teranyar di abad millenial. Belum lagi berlapis-lapis produk tafsir terhadap teks keagamaan yang bisa saja berkelindan dengan kepentingan ekonomi politik di masanya. Fundamentalisme membuat soal teks agama menjadi sesuatu yang terlampau sederhana, dan menolak kemungkinan merembesnya variable-variabel politik dan kebudayaan dalam teks-teks keagamaan.
Padahal Ali Harb dalam At-Ta’wil wa al-Haqiqah (1993), menyebutkan “wahyu adalah firman (kalam) yang tidak kering dan makna yang tidak habis-habisnya, sebagaimana telah dikatakan dan diisyaratkannya. Wahyu sesungguhnya adalah rujukan sumber (referensi), titah, dan teks. Hanya saja wahyu bukan rujukan ototritatif, melainkan juga rujukan signifikansi dan sumber makna. Dengan wahyulah, pemikir berijtihad dan di dalamnya nalar mengembara”. Tapi fundamentalisme justru menginginkan sebaliknya, dengan merujuk pada bunyi harfiah wahyu, nalar diminta untuk berhenti mengembara.
Kesimpulan ketiga, perlunya kita mengoreksi asumsi selama ini bahwa fundamentalisme baik yang berujung kekerasan ataupun tidak, selalu berasosiasi dengan orang-orang miskin dan tidak berpendidikan. Karena sudah banyak kasus terutama di Indonesia bahwa para pelaku bom bunuh diri berlatar belakang keluarga yang berkecukupan. Walaupun ada juga beberapa pihak yang berpendapat bahwa ini bukan hanya soal kemiskinan tetapi juga soal ketidakadilan, baik dalam ranah politik rekognisi maupun politik redistribusi.
Kesimpulan keempat, menyatakan bahwa fundamentalisme tidak selalu mengarahkan aksinya pada tindak kekerasan. Walaupun pada kondisi-kondisi tertentu melakukan tindak kekerasan terutama jika ada kaitannya dengan negara. Tidak bisa dipungkiri senantiasa ada permusuhan antara kelompok fundamentalisme dengan negara, apakah permusuhan dimulai oleh pihak fundamentalisme atau pihak negara, dan inilah yang biasanya yang memicu kekerasan. Konflik diawali dengan negara yang mempersepsikan kelompok fundamentalisme sebagai pengganggu stabilitas, dan sebaliknya kelompok fundamentalisme memandang negara sebagai pihak yang mengacuhkan Tuhan.
Kesimpulan kelima, alih-alih menganggap fundamentalisme sebagai entitas anti perubahan, justru kita mesti melihat fundamentalisme sebagai pihak yang mendukung perubahan, namun mereka memiliki pandangan sendiri soal perubahan. Justifikasi mereka dalam melakukan perubahan adalah karena negara bahkan peradaban saat ini adalah peradaban tanpa Tuhan (godles), dan mesti diubah atau dibersihkan walaupun mesti dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Walaupun nanti gerakan-gerakan politik yang bercorak fundamentalisme nantinya rentan digunakan sebagai “kaki tangan” pihak-pihak tertentu dalam memperebutkan sumberdaya (politik maupun ekonomi) yang semakin langka, tapi mereka memiliki bangunan narasi yang khas yakni narasi oposisi biner anatara “kami yang beriman” dengan “mereka yang kufur” (dan kita masih ingat saat Amerika ingin menyerang Afghanistan dan Irak, membangun model narasi yang sama cuman dengan pilihan diksi yang agak beda, dan ini bisa dijadikan acuan bahwa Amerika sebagai negara juga bercorak fundamentalisme saat itu).
Kemudian kesimpulan keenam, Marty dan Appleby mengusulkan koreksi terhadap anggapan adanya keterpusatan kepemimpinan dalam fundamentalisme. Walaupun para fundamentalis mengikuti seorang pemimpin, namun pemimpin tersebut tidak menjadi pusat segalanya. Jika seorang pemimpin meninggal maka dengan cepat dia akan digantikan oleh sosok baru, bahkan tidak jarang munculnya pemimpin-pemimpin baru dalam jejaring-jejaring baru yang dipicu oleh perbedaan dalam hal landasan teologis maupun metodologi gerakan. Dan kita bisa saksikan sendiri dalam konteks Indonesia, kelompok fundamentalis terbagi dalam berbagai friksi-friksi, begitu pula dengan para aktor teror berbasis agama bergerak dalam bentuk kelompok-kelompok yang semakin kecil.
Namun, bagi saya kita mesti melihat fundamentalisme sebagai salah satu varian dalam mengekspresikan agama, dan senantiasa ada jarak antara paham fundamentalisme dengan tindak kekerasan. Yang perlu kita lakukan adalah membuat jarak antara fundamentalisme dengan kekerasan semakin lebar, disamping ada upaya-upaya yang dilakukan agar adanya perjumpaan-perjumpaan publik di antara warga yang berbeda latar belakang pikiran dan keagamaan, termasuk perjumpaan antara yang beragama secara fundamentalistik dengan yang tidak. Bagaimanapun yang kita tuju adalah suasana, dimana martabat kemanusiaan (human dignity) dijunjung, kita mesti memandang sesama ( baik yang fundamentalis ataupun tidak) bukan sebagai “evil” tapi sebagai “human”.
Di samping itu, kita tidak hanya cukup dengan dialog di antara yang berbeda, kita juga butuh keadilan ekonomi dan politik, terbebas dari kemiskinan dan kelaparan. Karena bisa jadi teror atas nama agama ataupun bukan, sedikit banyaknya diawali oleh teror ketimpangan, teror ketidakadilan, teror represi aparat negara dan teror perampasan hak-hak orang kecil.




















