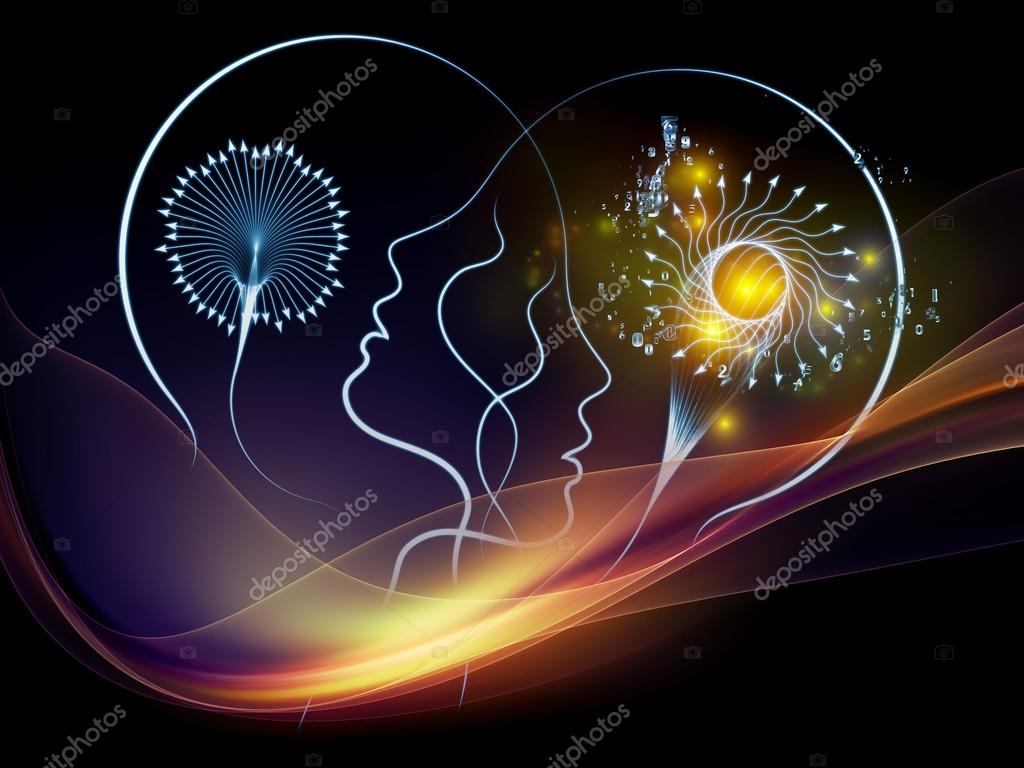
Oleh: Agusliadi Massere*
KHITTAH.CO, – Manusia bisa dipandang dan dinilai secara esensial dan eksistensial. Secara esensial manusia hanya terdiri atas “akal” dan “rasa”. Sedangkan secara eksistensial maka, manusia selain terdiri atas, sebagaimana dua hal yang telah disebutkan sebelumnya, akal dan rasa, juga terdiri/dilengkapi dengan “jasad”. Jadi membahas eksistensi manusia, maka secara tidak langsung juga menyentuh dimensi esensi.
Membahas tema ini, maka memaksa diri penulis dan pembaca untuk sedikit mengarungi belantara filsafat eksistensialisme. Untuk memasuki rimba eksistensialisme maka saya memilih buku Psikologi-Kita & Eksistensialisme: Pengantar Filsafat Barat, Berkenalan dengan Eksistensialisme, Kita dan Kami karya Fuad Hasan, sebagai rujukan utama. Meskipun demikian, saya tidak ingin terlalu jauh ke dalam rimba filsafat tersebut, karena keterbatasan pengetahuan membuat diri ini takut tersesat atau menyesatkan pembaca.
Mendahului yang lainnya, saya terlebih dahulu menyampaikan penegasan Fuad Hasan bahwa “Abad ke-20 ditandai oleh munculnya aliran filsafat yang disebut eksistensialisme. Sebutan ini berlaku untuk suatu rumpun filsafat yang tidak seragam penguraiannya tentang manusia sebagai eksistensi. Walaupun demikian, aliran-aliran tersebut berpangkal tolak dari asas yang sama, yaitu dalam usaha memahami manusia, eksistensi lebih penting ketimbang esensi”.
Penegasan bahwa eksistensi lebih penting ketimbang esensi, saya sepakat dengan Fuad Hasan. Baik dengan menggunakan logika sederhana maupun jika kita merujuk pada cara pandang Islam. Bisa disimpulkan bahwa Islam pun sepakat dengan hal tersebut, sebagaimana penegasan dan kesimpulan Fuad.
Terinspirasi dari kerangka materi-materi LK1 HMI—meskipun saya bukan bagian daripada kader HMI dan sama sekali tidak pernah melewati dinamika apapun di dalamnya—tetapi sempat membaca dan tidak pernah melupakan hal menarik dari buku/modul panduannya itu. Salah satu yang menarik, di dalamnya menjelaskan terkait esensi dan eksistensi manusia.
Secara eksistensial, dipahami bahwa manusia terdiri dari akal, rasa, dan jasad. Akal berfungsi untuk menemukan dan membedakan “benar-salah”. Rasa berfungsi untuk menemukan dan membedakan “baik-buruk”. Jasad mampu membedakan “indah-jelek”. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui “benar-salah” tersebut dan berada dalam ranah akal adalah “logika”. Sedangkan untuk mengetahui “baik-buruk” yang berada dalam ranah rasa adalah “etika”. Dan untuk “indah-jelek” yang berada dalam ranah jasad adalah “estetika”.
Setelah itu, maka kita akan memahami bahwa logika menjadi wilayah kerja “ilmu”. Etika berada dalam wilayah kerja “Iman”. Estetika menjadi wilayah kerja “Amal”. Ilmu, iman, dan amal, itulah yang menjadi pilar Islam. Dari alur pemahaman inilah, saya sepakat dan termasuk dalam substansi ajaran Islam, bahwa pembahasan eksistensi lebih utama ketimbang esensi. Pembahasan eksistensi sudah mencakup secara keseluruhan “diri” manusia.
Dalam kehidupan modern yang salah satunya ditandai dengan kemajuan teknologi, ditemukan fenomena kehidupan, di mana eksistensi manusia digerogoti. Manusia mengalami reduksi dan/atau distorsi nilai-nilai kemanusiaanya. Maka sangat pantaslah, ketika Prof. Syafiq G. Mughni, Ph.D—salah satu jajaran Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah—menegasakan “Persoalan besar yang muncul di tengah-tengah umat manusia sekarang ini adalah krisis spiritual.
Prof. Syafiq (dalam Azaki Khoiruddin, 2015) menambahkan “Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dominasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme ternyata membawa manusia kepada kehidupan modern di mana sekularisme menjadi mentalitas jaman dan karena itu spiritualisme menjadi suatu anatema bagi kehidupan modern”.
Satu pandangan menarik yang pernah saya tangkap dan sepakat terhadapnya, pada saat Kak Alwy (sapaan akrab Alwy Rachman) menjadi narasumber di Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Pandangan menarik itu, saya tidak ingat sepenuhnya tetapi bisa diparafrasekan seperti ini tanpa mengurangi substansi materinya, “Manusia, karena lebih banyak menghabiskan waktunya, menjalin relasi intim dengan mesin (teknologi), maka dimensi psikologis dan/atau kemanusiaannya tergerus. Efek lanjutannya adalah terkikisnya empati/kepedulian”.
Dari analisis dan pengamatan sederhana saja, kita bisa menemukan/melihat, jika pun tidak mampu merasakan, betapa eksistensi manusia telah digerogoti: nalar publik dipenuhi kekacauan, salah satunya hoax terus diproduksi dan direproduksi; empati dan simpati tergerus oleh narsisme, salah satunya tidak jarang sesuatu yang dimaknai “musibah’ menjadi “latar indah” untuk berfoto “selfie ria”. Jasad pun tidak sedikit mengalami ketersiksaan akibat pemenuhan nafsu, tanpa kecuali nafsu konsumtif.
Para filsuf eksistensialis pun, seperti Soren Kierkegaard, Nicolai Berdyaev, Karl Jaspers, Jean Paul Sartre, dan Martin Heidegger, juga merasakan betapa eksistensi manusia, terus mengalami, yang saya sebut saja dengan istilah “digerogoti”. Sebelum mengurai sedikit pandangan para filsuf eksistensialis, saya tegaskan terlebih dahulu bahwa mesin atau teknologi pun salah satu yang menggerogoti eksistensi manusia. Kurang lebih inilah yang ditegaskan pula oleh Jaspers.
Merujuk pada pandangan Heidegger saja, kita akan merasakan betapa manusia melalui sikap dan perilakunya, tidak lagi mencerminkan eksistensi yang sebenarnya. Hari ini manusia terkesan rakus, sehingga, khususnya untuk konteks kehidupan Indonesia keadilan sosial terasa masih terasa jauh. Rumus matematika sederhananya, 90% kekayaan/sumber daya alam Indonesia hanya dikuasai oleh 10% orang/rakyat/populasi Indonesia. Dan sebaliknya 90% orang/rakyat/populasi Indonesia, hanya menguasai sumber daya alam Indonesia. Angka persentase ini, bukan data yang tepat sesuai data statistik yang formal, tetapi kurang lebih mendekati. Ini tentunya menggambarkan ketimpangan dan ketidakadilan. Selain itu, kita bisa saksikan bersama, hari ini manusia tanpa kecuali yang mengaku pemeluk agama, terkesan anti dialog.
Padahal menurut Heidegger, dan saya sepakat begitupun pembaca pasti ada yang sepakat, “…manusia pada keseluruhannya adalah eksistensi yang terus-menerus terjalin dalam dialog. Artinya, manusia senantiasa terlibat dalam dialog dengan manusia lainnya, dirinya sendiri, atau dengan Tuhannya”.
Adalah Heidegger pun menambahkan “Sesungguhnya, manusia harus berbagi dunia dengan sesama manusia maka rumus itu dilanjutkan dengan menambahkan bahwa dunia manusia dihayati sebagai dunia bersama”. Jadi, saya memahami dari Heidegger bahwa idealnya manusia itu tidak rakus, tidak mendominasi secara berlebihan kekayaan dunia ini, dan mengabaikan serta membiarkan manusia lainnya mengalami penderitaan yang amat dalam akibat kemiskinan.
Adalah Kierkegaard, meskipun pandangannya terkesan sangat dipengaruhi oleh dirinya sendiri, sehingga sangat pesimistis, bisa disimpulkan secara substansial menegaskan, terkait kebebasan manusia dalam memilih, yang terkadang bermuara pada ketakukatan dan kecematan. Singkatnya, Kierkegaard pun sampai pada kesimpulan, atas ketakutan dan kecematan dari pilihan-pilihan tersebut bahwa “Manusia tidak punya pilihan lain kecuali berpaling pada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kepastian”.
Dalam pandangan Berdyaev, yang juga seorang filsuf eksistensialis, berdasarkan pemahman saya terhadapnya bahwa, komunisme dan kapitalisme pun itu “menggerogoti” eksistensi manusia. Singkatnya atau kesimpulan yang bisa ditarik dari Berdyaev, bahwa keduanya merenggut kemerdekaan manusia.
Berdyaev pun sampai pada kesimpulan “Satu-satunya hubungan yang tidak meniadakan kemerdekaan manusia untuk tampil dengan kesejatian pribadinya (personal authenticity) ialah hubungan dengan Tuhan. Bagi Berdyaev—sebagaimana hal ini telah ditegaskan dalam buku karyanya Dream and Reality—menegaskan “Dalam kehidupan bersama Tuhan itulah terwujud kebebasan”. Tentunya nalar pembaca tidak boleh mengimajinasikan “makna hidup bersama Tuhan” di sini sama dengan pemahaman lazim, ketika kita hidup bersama dengan seseorang.
Adalah Jasper, sebagai filsuf eksistensialis pun memiliki pandangan yang menarik, “Tuhan sebagai sumber imperatif yang justru mengukuhkan penghayatan kebebasan eksistensi manusia. Kebebasan adalah manusiawi, tetapi kebebasan itu bukan tanpa batas. Pada kebebasan itu selaku melekat berbagai imperatif….Tuhan yang diyakini sebagai sumber imperatif pun harus dipadnang sebagai pengukuh kebebasan”.
Dan yang sangat menarik dari Jasper, “Semakin dalam manusia menghayati kebebasan niscaya dia makin berkeyakinan tentang keberadaan Tuhan”.
Dari berbagai pandangan filsuf eksistensialis Barat pun, sampai pada kesamaan kesimpulan, yang saya sebutkan saja “kesadaran ilahiah”. Kesadaran akan adanya Allah sebagai sumber kekuatan menghadapi kehidupan. Atau minimal Allah bisa menjadi “titik” kembali paling aman ketika manusia terkungkung atau terperosok dalam ketakutan dan kecemasan yang amat akut.
Bagi umat Islam—dan memang konteks tulisan ini fokus utamanya adalah bagi umat Islam—yang sedang “mencelupkan” diri dalam kenikmatan bulan Ramadan, sangatlah tepat bahwa dalam atau melalui bulan Ramadan ini menjadi wahana ataupun sarana mengokohkan eksistensi manusia, yang terus digerogoti oleh kemajuan-kemajuan yang ada. Karena para filsuf eksistensialis pun, yang disebutkan di atas, semuanya menjadikan Tuhan sebagai sandaran, sumber, jalan kembali, yang utama untuk menjaga eksistensi manusia.
Bulan Ramadan, saya menyimpulkan demikian, karena semua memahami (dalam hal ini, terutama umat Islam) bahwa relasi kedekatan dengan Allah melalui beberapa ibadah utama selama Ramadhan, sangat intens, dan “intim” dilakukan. Bagi yang sedang berpuasa khususnya di bulan Ramadan ini, bisa dipastikan ingatannya senantiasa tertuju kepada Allah (yang para filusf di atas menyebut Tuhan, dan saya sendiri terkadang merasa berat menyebut selain kata “Allah”). Sebab jika yang melaksanakan puasa lupa akan kehadiran dan/atau pengawasan Allah, maka berpotensi atau berpeluang besar akan membatalkan puasanya. Belum lagi sejumlah ibadah-ibadah lainnya, yang sangat maksimal dilakukan selama bulan Ramadan ini.
Apalagi beberapa pandangan filus eksistensialis di atas, memiliki relevansi dengan pandangan Islam. Seperti terkait kebiasaan berdialog, Islam pun mengharapkan bahkan dalam hal perbedaan pandangan agama, untuk membangun dialog dalam rangka menemukan titik temu, karena Islam menganut aksioma “perbedaan adalah rahmat”.
Islam pun, termasuk ini tercermin dari substansi atau secara hakiki dari ibadah puasa, melarang manusia untuk rakus dan mengendalikan diri dari nafsu dunia. Islam mengajarkan zakat, sedekah, infaq, dan melarang menumpuk harta. Selain itu dalam hal kebebasan, jika kita atau umat di luar Islam mau jujur mengakui, maka ajaran kebebasan melalui kalimat tauhid adalah di atas dari segala ajaran kebebasan tersebut.
Bahkan oleh Ary Ginanjar Agustian “kalimat tauhid adalah deklerasi kemerdekaan yang melampaui apa pun yang ada di dunia, termasuk deklarasi Hak Asasi Manusia yang ada di Barat.
*Mantan Ketua PD. Pemuda Muhammadiyah Bantaeng. Komisioner KPU Kabupaten Bantaeng Periode 2018-2023.




















