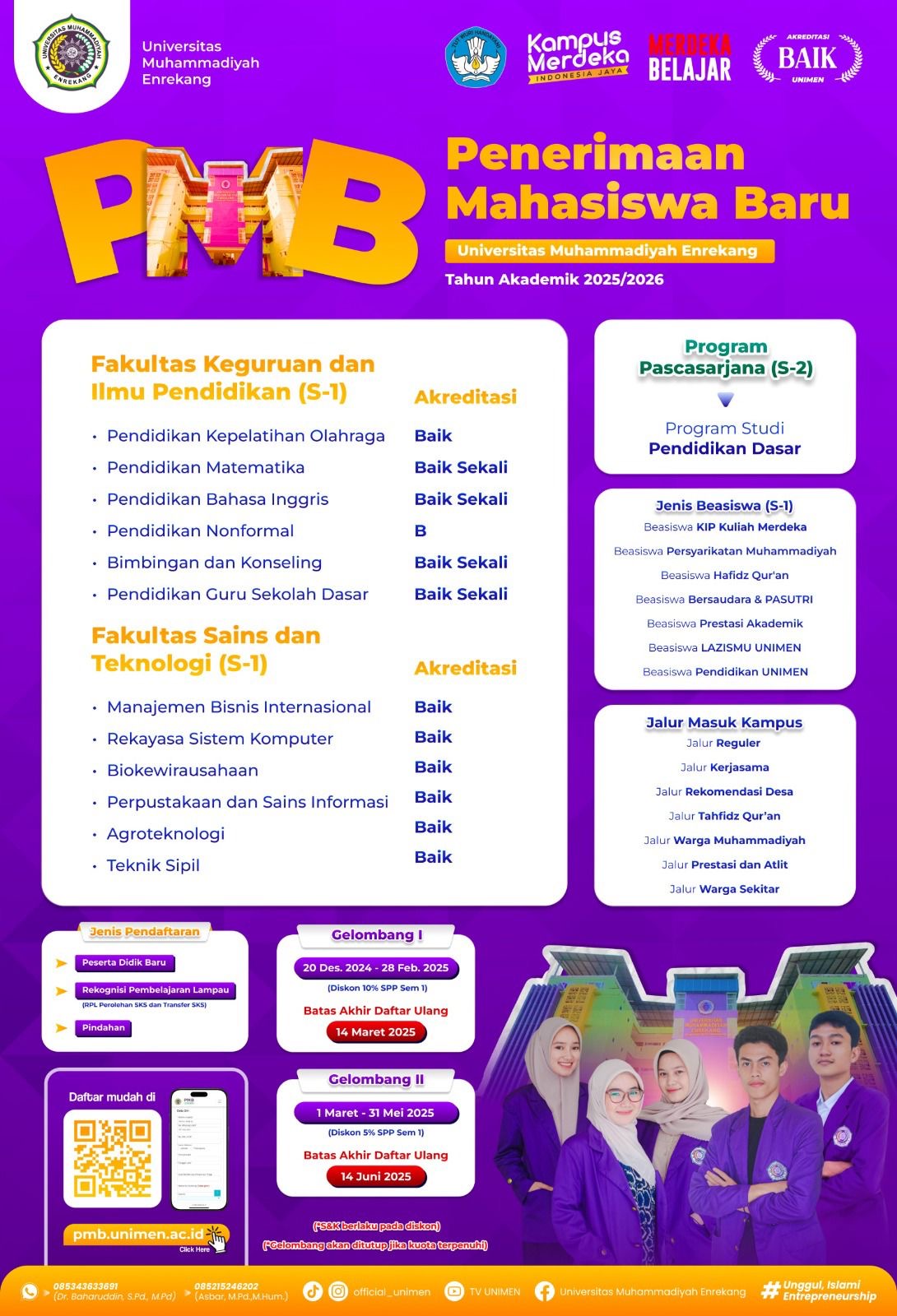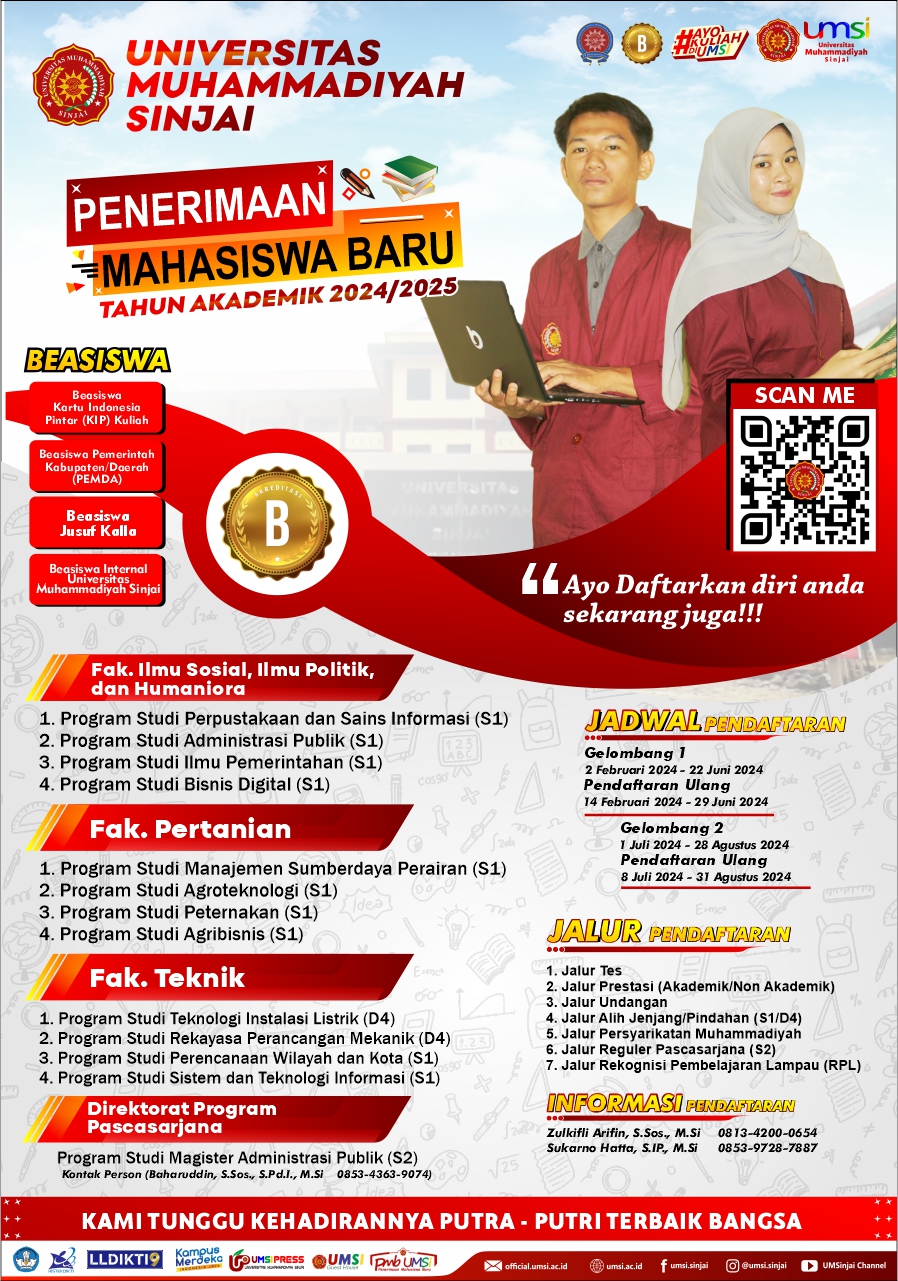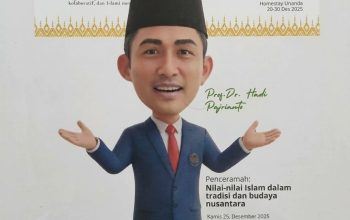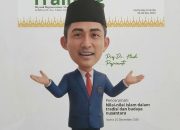Oleh: Agusliadi Massere*
KHITTAH. CO – Jauh sebelum memahami gaya diplomasi M. Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI ke-10 mendampingi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden dan Wakil Presiden RI ke-12 mendampingin Bapak Joko Widodo, saya mendapatkan pembelajaran dan didikan terbaik dan berharga dari almarhum Bapak saya sendiri, yang akrab disapa oleh masyarakat di kampung, Massere, sering pula disapa dengan “Iye” atau “Iye Massere”. Iye adalah panggilan yang sama dengan Bapak atau Abi.
Sekadar tambahan pengetahuan, ternyata setelah saya membaca buku karya Fadmi Sustiwi, Din Syamsuddin dari Sumbawa untuk Dunia, saya mendapatkan, bahwa panggilan “Iye” juga adalah panggilan kesayangan Pak Prof. Din Syamsuddin di rumahnya. Penasaran dengan panggilan “iye” yang sama dalam keluarga kami, saya pun chat pribadi via WhatsApp Pak Prof. Din untuk menanyakan latar belakang panggilan kesayangannya tersebut. Ternyata, salah satu jawaban beliau menegaskan bahwa leluhurnya berasal dari Kabupaten Gowa.
Salah satu pembelajaran dan didikan yang tidak pernah saya lupakan adalah dari suatu peristiwa yang bisa kita sebut dengan “Kisah sebungkus kacang goreng”. Saya masih mengingat dengan baik peristiwa atau kejadian tersebut, meskipun pada saat itu mungkin umur saya kurang lebih enam tahunan.
Pada saat itu, saya berdua dengan almarhum Bapak saya menuju Makassar dengan menggunakan mobil bus penumpang untuk tujuan menjemput uang pembayaran hasil penjualan satu paket sound-system yang dijemput oleh pembeli satu bulan sebelumnya. Artinya pada saat itu, tidak langsung dibayar, sehingga setelah sampai batas waktu perjanjian, kami ke Makassar untuk menagih. Modal yang dimiliki Bapak saya hanya sekadar sewa mobil ke Makassar, tidak lebih dari itu.
Sebagaimana biasanya, pada saat itu tahun delapan puluhan, semua bus penumpang yang menuju Makassar bisa dipastikan akan singgah di warung makan satu-satunya (jika tidak salah pada saat itu)—sekarang pun, saya masih menghafal dengan baik lokasinya tersebut. Pada saat itu, tentu saja semua sopir dan penumpang turun untuk makan atau sekadar beli makanan ringan atau minuman. Saya dan Bapak, pada saat itu tidak turun dari mobil karena memang kami tidak memiliki uang lebih selain untuk sewa mobil sebatas biaya sampai ke Makassar.
Beberapa menit kemudian, seorang penumpang kembali naik ke mobil bus yang kami tumpangi, mungkin mengamati kondisi kami dan termasuk kondisi psikologis kami, apa lagi saya yang masih anak kecil pada saat itu, maka dia pun menyodorkan sebungkus kacang goreng. Bapak saya secara spontan menyampaikan “Iye, terima kasih tawwa, sudahmi makan dan sudah kenyang juga.” Mendengar penyampaian Bapak saya ke orang tersebut, saya pun menolak tidak mengambil sebungkus kacang goreng tersebut, meskipun dalam hati kecil ini, saya sangat suka dan ingin sekali menerima pemberian orang tersebut, apa lagi disodorkan beberapa kali.
Kejadian serupa meskipun bukan hanya seperti kisah sebungkus kacang goreng tersebut, saya sering mendapatkan penyataan Bapak saya yang kurang lebih sama dengan kejadian di mobil tersebut. Saya pun selalu mengikuti harapan tersiratnya untuk tidak mudah meminta dan menerima sesuatu dari orang lain.
Ada banyak model didikan yang saya dapatkan dari almarhum Bapak saya, termasuk ada nilai-nilai yang relevan dengan nilai dan ajaran fundamental dari pandangan keagamaan Muhammadiyah, meskipun Bapak saya bukan kader dan pengurus Muhammadiyah, dan termasuk pemahaman dan praktik keagamaannya masih tergopoh-gopoh. Nanti, kurang lebih sepuluh tahun terakhir pada akhir hidupnya barulah dirinya sedikit semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan salat dan berpuasa.
Dari kisah sebungkus kacang goreng tersebut di atas, tentunya dalam konteks ajaran agama Islam itu terkesan relevan dengan penegasan “Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah”. Ternyata seiring perjalanan waktu dengan geliat, pergumulan, dan dialektika pengetahuan dan intelektualitas, saya pun menemukan banyak pembelajaran dan keteladanan yang pada intinya menegaskan prinsip “Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah”. Meskipun, dalam realitas kehidupan pun banyak sosok yang menunjukkan dan menampakkan dirinya mempraktikkan antitesa dari hal tersebut. Sering berada dalam posisi “Tangan di bawah” bahkan dalam makna yang lebih luas dengan varian yang sangat beragam.
Yang menarik ternyata ada satu tokoh nasional—di Indonesia. Bahkan, mungkin bisa disimpulkan satu-satunya tokoh nasional, yang dalam kancah diplomasi dunia, dirinya senantiasa merefleksikan dan mengkristalisasikan gaya diplomasinya dari prinsip “Tangan di atas”. Tokoh nasional yang dimaksud tentu saja, tidak ada yang lain, adalah Bapak M. Jusuf Kalla yang berdarah Bugis-Makassar.
Dalam buku Tangan di Atas: Kumpulan Pidato dalam Rangka 76 Tahun M. Jusuf Kalla yang dieditori oleh Husain Abdullah, dan kawan-kawan, kita bisa menemukan dengan jelas gaya diplomasi yang dimaksud. Jika kebanyakan tokoh nasional atau pejabat negara ke luar negeri cenderung terkesan meminta kepada kepala negara yang didatanginya, justru sebaliknya jika Pak JK mengunjungi suatu negara, maka dirinya menawarkan apa yang bisa dibantukan dari Indonesia.
Ada peristiwa menggelitik yang pernah dirasakan oleh Pak JK bersama rombongannya ketika berkunjung ke negara tertentu, kemudian mereka memasuki kios dan toko. Ternyata, pelayan tokoh mengira mereka orang Malaysia, sama sekali tidak ada dalam pikiran pelayan toko/kios tersebut sebagai orang Indonesia. Ini adalah efek lanjutan dari prinsip yang tidak relevan dengan ajaran agama tersebut, karena kesannya selama ini kita lebih cenderung menerapkan prinsip “Tangan di bawah”.
Menurut Pak JK, kenapa kita selalu dikira orang Malaysia ketika berada di luar negari? Jawabannya “Malaysia lebih dikenal di dunia ini, Ekonominya lebih besar dan mereka juga lebih banyak tangan di atas, sementara kita banyak di bawah”. Ini penegasan Pak JK.
Kita katanya, ketika kedatangan tamu dari negara lain, maka selain pertanyaan “Dia mau apa?”, kita juga bertanya pada diri sendiri “Kita dapat apa kira-kira dari dia?” Selalu langsung berpikir dapat apa dari dia.
Pengalaman menarik dari Pak JK ketika agak tersinggung dengan Wakil Presiden Amerika Serikat, Dick Cheney. Ketika itu Cheney baru terpilih berpasangan dengan Barack Obama. Pak Jk menemui Cheney selaku wakil presiden. Menurutnya, “Begitu saya duduk, dia langsung bicara dengan sedikit angkuh, Dia angkat kakinya, kemudian langsung berkata Mr. Vice President, biasanya negara-negara seperti Anda datang selalu minta bantuan, apa yang bisa saya bantu?”
Pak JK yang tersinggung mengangkat juga kakinya, dan dalam perbincangannya itu pun memberikan jawaban tegas “Oh, tidak. saya tidak pernah datang untuk meminta bantuan. Saya datang ke sini justru untuk membantu Anda. Anda sedang krisis, Indonesia tidak. Jadi sekarang saya bisa bantu Anda apa?” Maka pada saat itu Wakil Presiden Amerika Serikat pun kaget mendengarkan jawaban dan tanggapan balik dari Pak JK yang tegas tersebut.
Gaya Diplomasi Pak JK yang kurang lebih seperti ini—dengan prinsip “Tangan di atas”—di berbagai negara, sehingga Pak JK sangat disegani oleh pimpinan negara-negara lain. Sama halnya ketika ada hal genting relasinya dengan China dan Taiwan. Kesannya China marah karena mengakomodir harapan Taiwan, bahkan beberapa negara lain menolak juga harapan Taiwan karena takut China marah, malah Pak JK lebih marah lagi kepada China. Panjang ceritanya ini yang bisa ditemukan dalam buku tersebut. Singkatnya, setelah Pak JK melakukan semua itu justru ketika dia ke Beijing, dirinya disambut dengan Barisan Kehormatan yang paling megah, belum pernah ada wakil presiden disambut semegah itu di Beijing.
Pak JK pun sukses mendamaikan beberapa perseteruan sampai dijuluki Bapak Perdamaian Dunia, itu karena gaya diplomasinya yang sering mengkristalisasikan prinsip “Tangan di atas”. Tidak mau menjadi pengemis, penjilat, peminta-minta, dan lembek di mata pimpinan negara di dunia. Justru dirinya senantiasa mengedepankan pikiran, apa yang bisa saya bantu untuk negara lain.
Prinsip “Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah” sebenarnya bukan hanya dalam makna sempit memberi-diterima dan meminta-menerima dalam hal barang atau finansial. Terinspirasi dari gagasan Arvan Pradiansyah yang menegaskan posisi manusia, yaitu “dependen”, “independen”, “interdependen”, terakhir “dependen, tetapi kepada Allah”, kemudian untuk bergeser dari posisi satu ke posisi lain, itu harus memiliki kemampuan mulai dari intrapersonal relation (hubungan ke dalam diri sendiri), interpersonal relation (hubungan ke orang lain), dan God relation (hubungan kepada Allah), maka prinsip tersebut harus terkristalisasi melalui sikap dan tindakan dalam lingkup sosial, politik, bahkan dunia birokrasi, dan institusi tertentu.
Sebagai contoh dalam dunia birokrasi, apa lagi yang beririsan dengan politik dalam kontestasi politik, maka seorang bawahan itu tidak boleh terjebak dalam makna bawahan-atasan yang kaku, sehingga kesannya memiliki loyalitas buta terhadap pimpinan. Jika kita memahami prinsip interdependen (saling tergantung) maka relasi bawahan-atasan adalah relasi birokrasi yang dibingkai dengan aturan yang jelas, sumpah dan janji jabatan, serta kode etik. Jadi jika loyalitas yang dituntut menciderai aturan dan kode etik yang ada, sejatinya tidak ada loyalitas sekali pun kepada pimpinan. Loyalitas terhadap pimpinan hanya ada ketika itu relasinya atau dalam bingkai yang sesuai aturan dan kode etik yang mengikat .
Pemahaman dan kesadaran ini, tentu akan menyelamatkan diri kita dari karakter yang bisa dimaknai karakter penjilat dan bahkan berpotensi selanjutnya menjadi karakter bunglon dan kutu loncat. Selalu mencari aman dengan menghalalkan berbagai cara, melabrak etika dan berbagai aturan dan moralitas yang ada.
Mengapa makna interdependen tersebut hanya pada relasi simbiosis mutualisme yang bermoral dan beretika karena kita pun akan melangkah pada posisi berikutnya, posisi puncak yaitu dependen tetapi hanya kepada Allah, modalnya dengan God relation. Di posisi puncak ini, di dalamnya harus terpancar ketulusan, keikhlasan, dan tidak mempertuhankan kepentingan semu, jabatan, harta, dan uang.
Dalam satu peristiwa, mungkin itu efek lanjutan yang ditanamkan oleh orang tua saya dan berbagai nilai dan ajaran lainnya, sehingga saya pernah menegaskan dalam wujud nyata “Tidak ada loyalitas terhadap pimpinan ketika itu bertentangan dengan aturan dan kode etik yang ada”. Padahal pada saat itu, berbagai narasi yang mengancam dan menakutkan dialamatkan ke diri saya. Tetapi saya pun menegaskan siap menerima segala risiko, apa pun yang terjadi.
Jadi dari ini semua, dan beberapa kejadian berikutnya, saya mendapatkan penguatan pemahaman dan kesadaran, bahwa karakter penjilat (suka menjilat) sebagai penjabaran lain dan antitesa dari prinsip “Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah” itu justru buruk pada diri sendiri karena membelenggu diri dari kebebasan dan kemerdekaan untuk menjaga prinsip ideal dan mulia dari dalam diri sendiri. Marilah kita mengkristalisasikan dalam makna yang lebih luas dari prinsip “Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah” dan Pak JK adalah teladan terbaik.
Yang paling utama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, saya memahami dan menyadari, semoga sahabat pembaca pun demikian, bahwa hanya dengan mengkristalisasi prinsip “Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah” dalam makna luas dan berbagai varian atau bentuk kita pun bisa mewujudkan Trisakti Soekarno: Berdaulat secara politik, berdikari dari ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Jika sebaliknya, prinsip “Tangan di bawah” dominan maka kita sulit mewujudkan Trisakti Soekarno.
*Pemilik Pustaka “Cahaya Inspirasi”, Wakil Ketua MPI PD. Muhammadyah Bantaeng, dan Pegiat Literasi Digital & Kebangsaan.