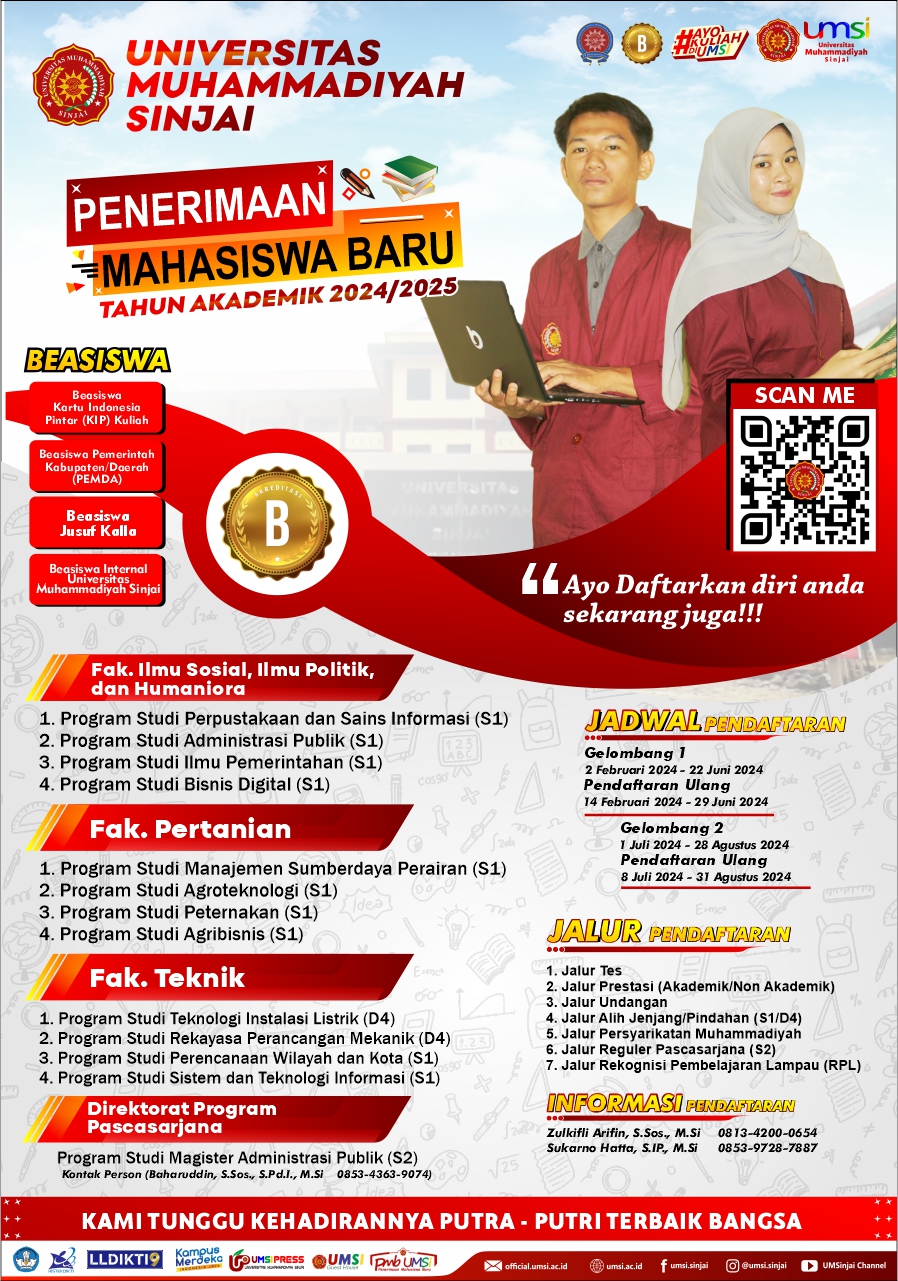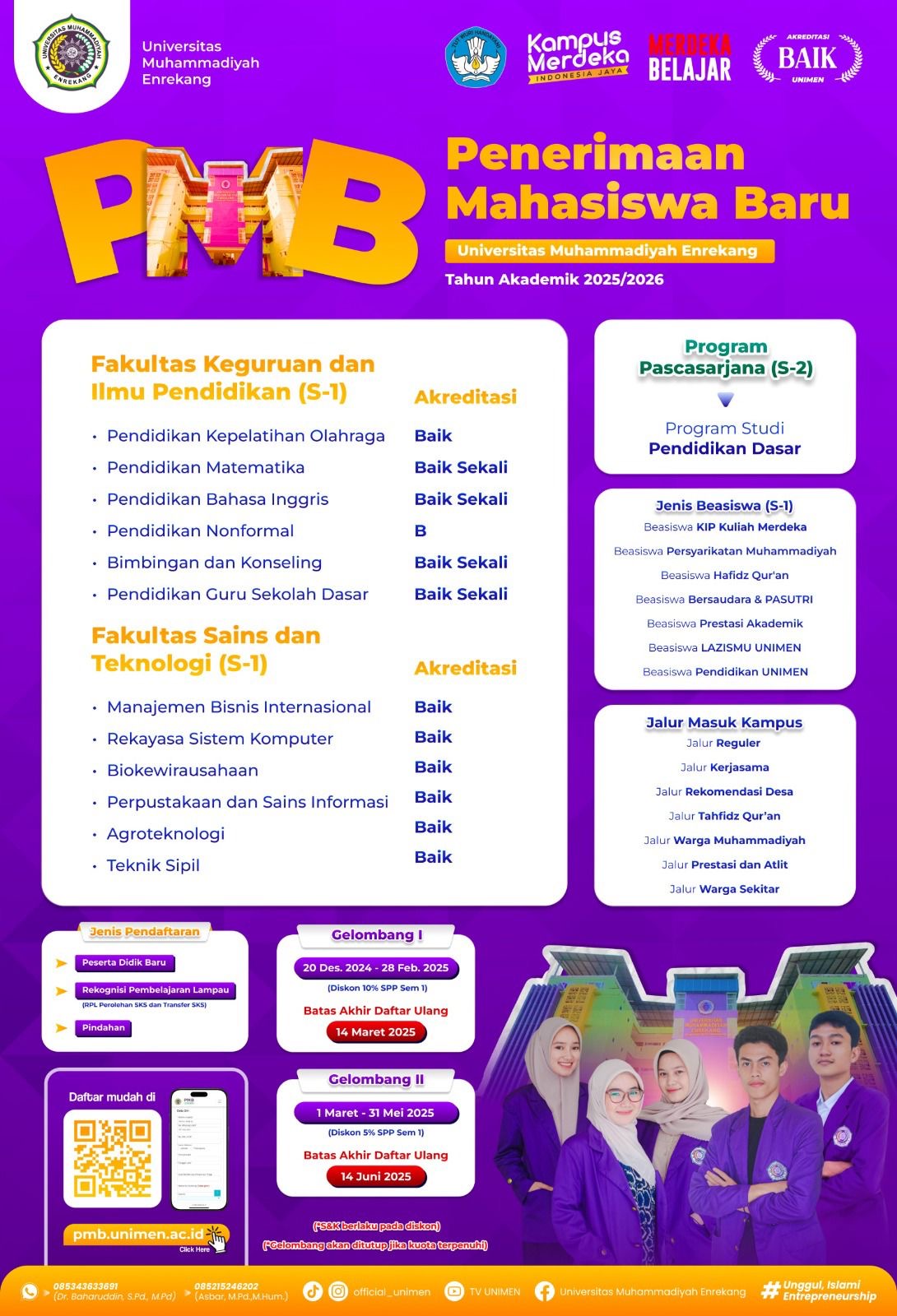Oleh: Agusliadi Massere*
KHITTAH. CO – Sekolah sebagai pilar strategis pembangunan peradaban—di dalamnya termasuk bangsa dan negara—membutuhkan porsi perhatian yang sangat besar. Bukan hanya dimensi fisik, material, dan infrastrukturnya semata. Namun, dimensi jiwa, nilai, makna, psikis, mental, dan spiritualitas, sejatinya sangat diprioritaskan terlebih dahulu.
Lagu kebangsaan Indonesia Raya telah menegaskan “Bangunlah jiwanya bangunlah badannnya”. Jadi mendahulukan jiwa kemudian diikuti oleh badan, raga, fisik, dan infrastrukturnya. Ini pun sebenarnya jika dicermati secara mendalam dari jiwa ke badan (dan tidak boleh terbalik atau sebaliknya), itu adalah mekanisme pembentukan karakter, di mana karakter positif adalah modal yang sangat penting bagi bangsa dan negara, dan sekolahlah wadah terbaik untuk pembentukannya.
Di sekolah bisa berlangsung ta’lim sebagai pembentukan kecerdasan intelektual berbasis ilmu pengetahuan dan sains sebagai syarat utama suatu peradaban memancarkan pengaruh bagi peradaban lainnya. Di sekolah pula bisa berlangsung ta’dib sebagai wadah pembentukan jiwa, psikis, mental, dan spiritualitas, yang sangat dibutuhkan di jantung peradaban agar bisa menjadi fondasi kokoh untuk terus bertahan, eksis, dan berkarya. Termasuk sekolah adalah wadah terbaik berlangsungnya tarbiyah untuk membentuk anak didik menjadi insan kamil dengan menggali dan membentuk segala potensi kemanusiaan yang terbaik dalam diri.
Sekolah dan aktor yang terlibat di dalamnya harus mampu untuk senantiasa menumbuhkan dan merawat gagasan sebagai salah satu langkah maju dan modal besar untuk suatu ikhtiar masa depan yang strategis dan berkemajuan. Mengapa? Prof. Hilman Latief pernah menegaskan yang bisa diparafrasekan seperti ini, “Gagasanlah yang menjadi realitas sesungguhnya jika menggunakan cara berpikir ‘neo-platonistik’. Tidak sedikit lembaga atau organisasi mengalami kemandekan dan kemunduran karena etos dan gagasan para penggeraknya sudah ‘habis’ tenggelam dalam rutinitas kegiatan praktis dan taktis dan jauh dari hal substantif”.
Hal senada diungkapkan oleh Prof. Najib Burhani, “Namun, karena beberapa alasan, seperti bila kita selalu terjebak pada tataran praktis dan tidak mau berada pada tataran diskursif atau wacana, maka alih-alih kita bisa menciptakan dunia yang semarak, alam yang indah, manusia yang penuh inovasi dan kreasi, justru sebaliknya kita bisa terjebak pada paham pembangunanisme yang mengukur segala hal dengan materi”.
Menciptakan perubahan dan kemajuan harus mampu atau dibutuhkan kemampuan berpikir jauh ke depan dan itu diawali dengan sesuatu yang berbasis gagasan. Rhenald Kasali menegaskan satu di antara tiga modal perubahan adalah ”To see” melihat impian, tujuan, dan harapan ideal yang terletak jauh di masa depan melalui alam mental atau melihat secara batin, bukan melalui mata kepala.
Atas dasar pandangan di atas, maka sekolah harus mampu membumikan kecerdasan bangsa. Namun, kecerdasan bangsa yang dimaksud harus berbasis iman, takwa, dan akhlak mulia.
Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah rumusan dan cita-cita mulia para pendiri bangsa, yang hari ini tentunya adalah salah satu tujuan mulia negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa muaranya bukan hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual dan tenaga terampil yang siap pakai untuk mengisi dunia usaha dan industri dalam kancah persaingan regional, nasional, dan global.
Kita harus mampu berpikir dan melampaui dari itu, kita jangan hanya berorientasi pada capaian, output, dan outcome yang penanda dan petandanya hanya dalam hal material, fisik, dan infrastruktur. Kita harus mengingat dan berhati-hati, sebagaimana diingatkan oleh Prof. Najib di atas, jangan sampai kita terjebak pada “segalanya diukur dengan materi”.
Saya khawatir, jika orientasi kita selalu pada hal material, maka ke depan kita terjebak pada karakter keserakahan dan ketidakjujuran”. Membaca buku Educating for Character: Mendidik untuk Membentuk Karakter (2012) karya Thomas Lickona, saya menemukan dua karakter buruk yang seharusnya itu menjadi pekerjaan rumah atau PR terutama oleh sekolah agar tidak terbentuk dalam diri anak didik. Yaitu, karakter keserakahan dan ketidakjujuran.
Ketika kita memiliki impian mewujudkan bangsa dan negara yang maju, berdaulat, makmur, aman, serta mengedepankan welas asih, nilai-nilai kemanusiaan, dan keadilan sosial, maka kata kuncinya adalah di dalam diri para penyelenggara negara, pemimpin, dan/atau wakil rakyat harus terpatri, terbentuk, dan membumi cahaya keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
Jika kita ingin jujur mengakui, bahwa berbagai problem kebangsaan yang terjadi hari ini, korupsi, politik uang yang menjadi bom waktu, penyimpangan, berbagai pelanggaran etik, dan pengkhiatan terhadap sumpah/janji jabatan sendiri, itu adalah wujud nyata hilangnya atau tidak membuminya cahaya keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Seakan ketiganya ini hanya untuk pembentuk kesalehan pribadi menuju surga dalam makna kebahagiaan di akhirat semata.
Padahal, jika hanya dilihat secara sempit dan sekilas, untuk sumber daya manusia bangsa dan negara kita, Indonesia, itu telah cukup. Hanya saja, saya curiga yang kita maknai sebagai “kecerdasan bangsa” belum sesuai dengan esensi kemanusiaan dan termasuk jauh dari konstitusi negara kita sendiri. Dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kita bisa memahami penegasan poin dan basis nilai utama yang wajib dilakukan pemerintah dalam sistem pendidikan nasionalnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
Sekolah memiliki potensi besar sebagai wadah pembentukan karakter, sehingga sekolah dan berbagai stakeholder yang ada di dalamnya harus mampu menerjemahkan dan membumikan nilai dan makna substansial dari Pasal 31 ayat (3) tersebut, diiringi dengan niat tulus, komitmen kuat, dan dibingkai dengan semangat untuk membentuk karakter unggul anak didik yang dipersiapkan menjadi aktor penggerak dan perubahan di masa yang akan datang.
Pendidik maupun anak didik, sejak dini harus mampu meletakkan impian masa depan yang akan memberikan perubahan dan kemajuan baik dirinya maupun bangsa dan negaranya. Pendidik dan anak didik tidak boleh larut dalam kebiasaan untuk memikirkan atau pikirannya hanya untuk kebahagiaan hari ini saja. Meskipun itu positif, tetapi tidak boleh hanya itu, perlu ada keseimbangan antara hari ini dan hari esok.
Usia sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, itu adalah golden age (masa keemasan) atau terbaik utuk membentuk karakter anak didik yang kokoh dan berimplikasi besar dan strategis bagi masa depan, baik untuk diri anak didik sendiri terutama bagi bangsa dan negara.
Cara sederhana yang bisa kita lakukan adalah fokus pada upaya pembentukan kebiasaan positif yang mencerminkan, memancarkan, dan membumikan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Ini harus satu paket, tidak boleh hanya fokus pada satu hal saja. Anak didik atau siswa, tidak hanya fokus untuk meningkatkan kecerdasan intelektualnya. Namun, di antara proses belajar-mengajar harus tercermin, terpancar, dan membumi nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia tersebut.
Anak didik tidak hanya fokus diajari tentang disiplin datang ke sekolah tepat waktu, pakaian yang rapi, begitu pun ukuran dan model rambutnya. Anak didik harus mampu dibiasakan—sebagai upaya pembentukan karakternya untuk mengedepankan welas asih di antara sesama siswa, agar ini bisa melumpuhkan bibit yang berpotensi menyuburkan keserakahan.
Anak didik harus ditanamkan sejak dini dalam dirinya untuk tidak mengejar angka rapor dan ijazah semata yang bersifat material. Namun, mengutamakan ilmu pengetahuan dan keberkahan dalam prosesnya. Anak didik pun perlu dilatih untuk mengedepankan nilai-nilai kejujuran dalam belajar dan proses penyelesaian segala tugas-tugasnya. Jangan ada ruang untuk tumbuhnya budaya nyontek ketika ada ujian yang mengabaikan kejujuran proses di dalamnya. Minimal dua hal ini, itu mengandung upaya pembumian nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
Agar semakin membumikan nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, maka rukun iman, rukun Islam, spirit ihsan, dan nilai-nilai Pancasila jangan sekadar sebagai bahan hafalan. Nilai-nilai dan makna yang terkandung di dalamnya harus senantiasa diinternalisasi ke dalam diri anak didik.
Rukun iman, beberapa contoh saja, iman kepada Allah, bukan hanya mengajarkan anak didik untuk percaya adanya Allah, tetapi tentu harus ditanamkan, minimal, bahwa Allah itu Maha Melihat, Maha Adil, dan Maha Kuasa, agar dengan penanaman dan pemahaman keyakinan ini, setiap anak didik akan melewati proses belajar mengajarnya termasuk dalam penyelesaian tugasnya secara jujur dan hanya mengharapkan rida Allah.
Iman kepada malaikat, bukan hanya anak didik diajari untuk menghafal nama-nama dan tugas para malaikat, tetapi diberikan pemahaman mendalam untuk membentuk karakternya seperti apa malaikat dalam menjalankan perintah Allah. Intinya integritas dan profesionalitas malaikat patut menjadi pemantik nilai dan pembentuk karakter anak didik.
Rukun Islam pun, sejatinya dibahas di hadapan anak didik bukan hanya dimensi fikih semata, atau tentang rukun-rukun ibadah saja. Muaranya bukan hanya untuk surga di akhirat. Rukun Islam sesungguhnya mengandung mekanisme pembentukan karakter. Salat itu bisa membentuk banyak karakter positif, produktif, dan konstruktif bagi anak didik. Puasa membentuk karakter berupa “Pengendalian diri” dan “kepedulian” yang kokoh. Agama bukan hanya tiket masuk surga semata.
Zakat untuk membangun kolaborasi, menguatkan kohesivitas sosial, dan persatuan Indonesia. Begitu pun spirit ihsan, sejatinya membentuk karakter agar anak didik bukan hanya melaksanakan salat dengan baik secara tulus dan ikhlas semata-mata hanya kepada Allah, tetapi akan senantiasa pula memberikan yang terbaik dan memantapkan niat yang tulus untuk mempersembahkan hal positif, produktif, konstruktif, fungsional, dan kontributif, serta berorientasi dunia-akhirat dalam bingkai rida Allah. Ihsan pun adalah basis teologis dari akhlak mulia.
Jadi harapan besarnya jangan konsepsi dan implementasi dari upaya “Mencerdaskan kehidupan bangsa” dipahami secara sempit seperti hanya berorientasi pada bangunan intelektualitas generasi muda, kemampuan public speaking dan/atau komunikasi verbal, dan pemenuhan skill yang dibutuhkan dunia usaha dan industri semata. Namun, yang paling utama dalam segala upaya mencerdaskan kehidupan bangsa—ini pun sangat konstitusional—adalah meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
Jika ketiga nilai dan pilar ini dijadikan fondasi atau basis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dipastikan hal paradoks berupa sikap dan tindakan yang jauh dari ketiganya tersebut, terutama perilaku dalam tata kelola negara, dipastikan tidak akan terjadi atau minimal tidak seburuk kondisi hari ini.
Tata kelola bangsa dan negara hari ini yang masih menyisakan banyak PR dan kondisi buruk, negatif, dan destruktif terutama yang dilakoni oleh para elit negara, sejatinya menjadi bahan refleksi mendalam dan titik balik untuk secara serius memikirkan peran dan fungsi jangka panjang sekolah dalam membangun karakter generasi muda sebagai calon penerima tongkat estafet kepemimpinan dan aktor penentu kemajuan bangsa dan negara pada masa yang akan datang.
*Pemilik Pustaka “Cahaya Inspirasi”, Wakil Ketua MPI PD. Muhammadiyah Bantaeng, dan Redaktur Opini Khittah.co