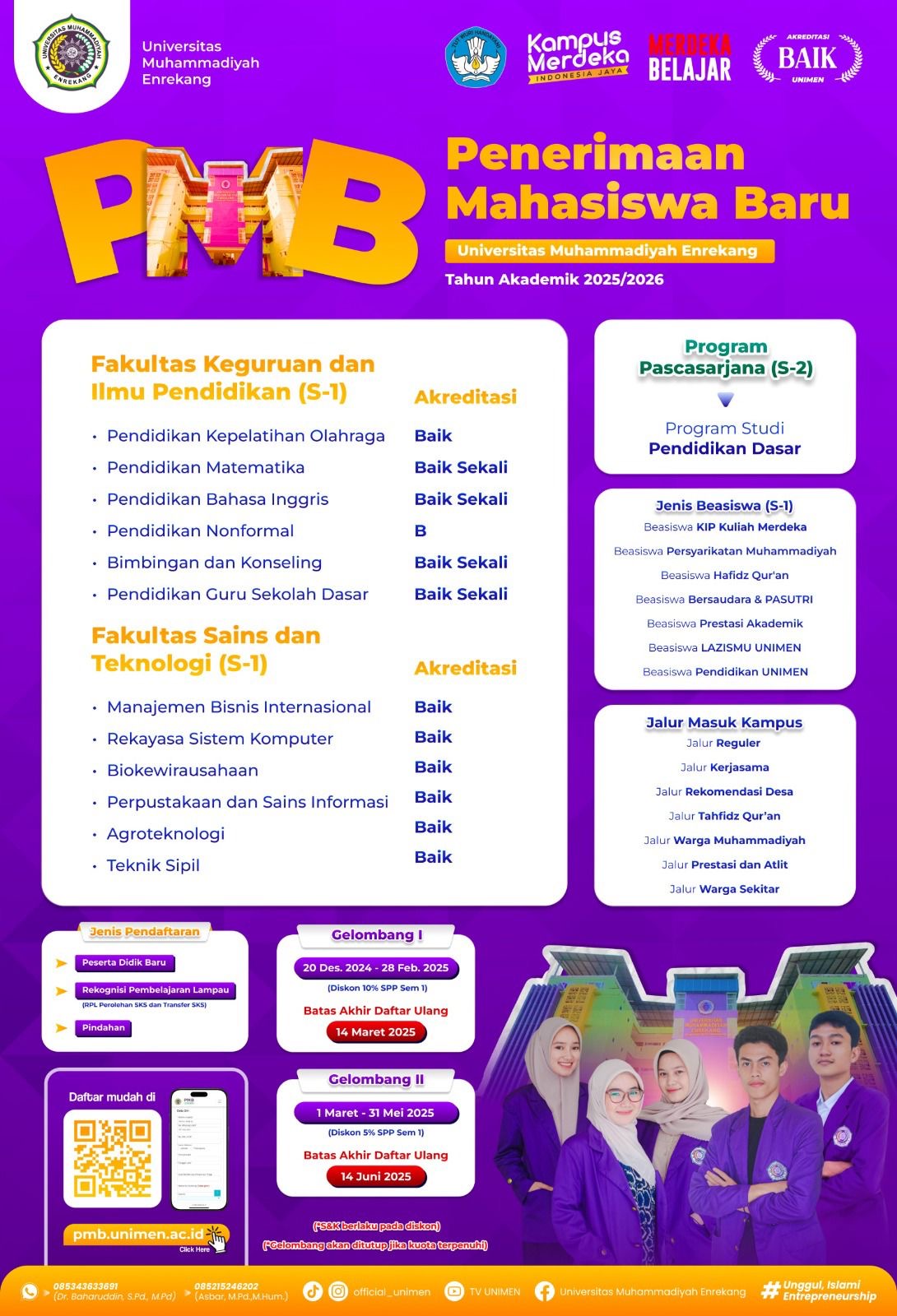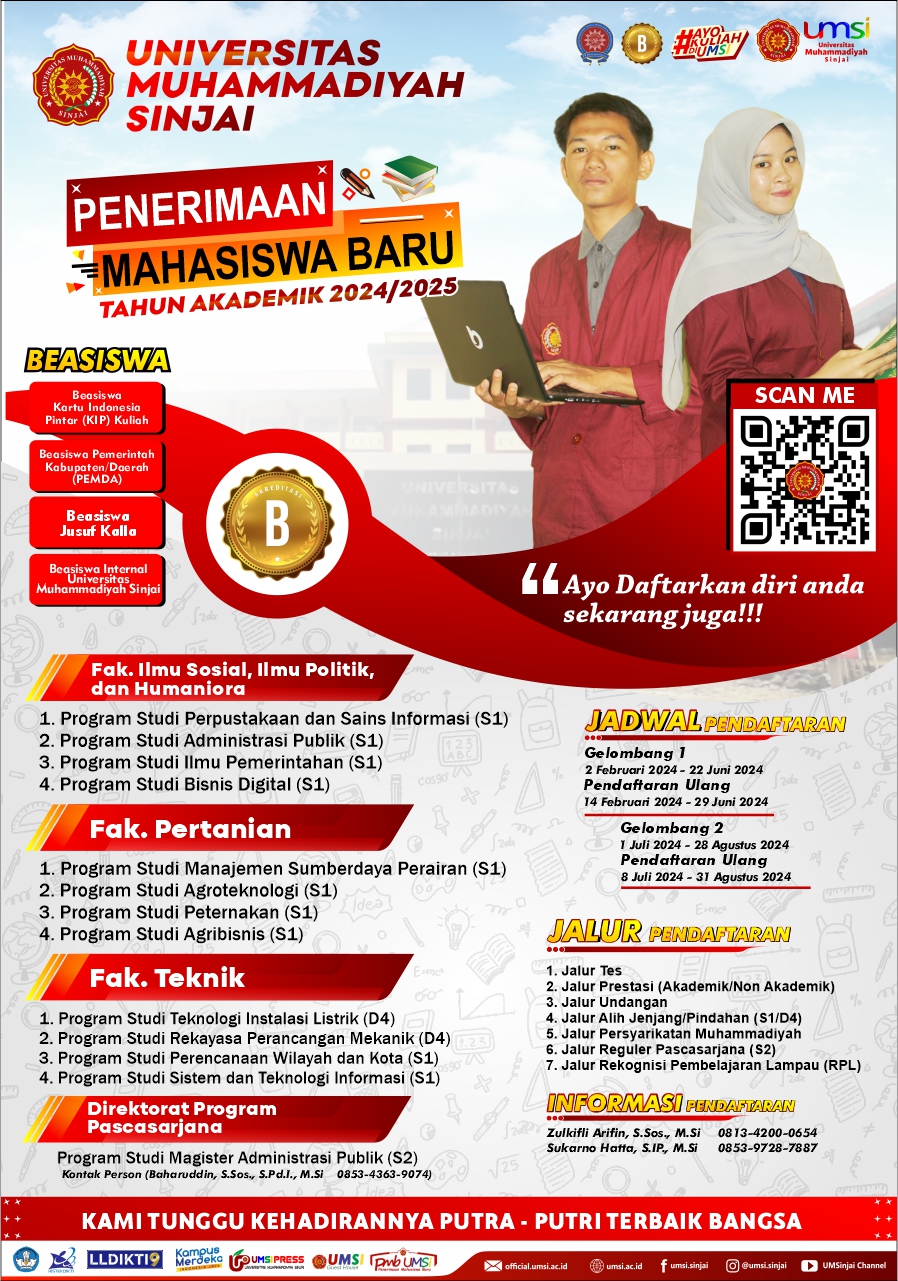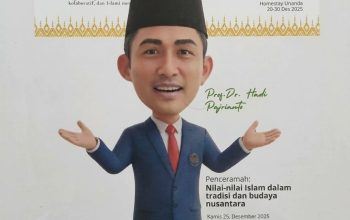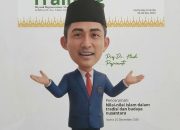Oleh: Mukhaer Pakkanna (Wakil Ketua MEBP PP Muhammadiyah)
KHITTAH. CO – Medio Februari 2025, unjuk rasa mahasiswa marak digelar di beberapa kota dan dijuluki demonstrasi “#IndonesiaGelap”. Unjuk rasa itu dipicu respons atas pelbagai kebijakan kontroversial Presiden hingga makin maraknya kasus megakorupsi yang tersingkap.
Implikasinya, dalam bidang ekonomi, merujuk riset Ciptadana Sekuritas Asia (4/3), IHSG anjlok 21 persen dari puncaknya September 2024 dan investor asing mencatatkan arus dana keluar Rp30 triliun hanya dalam waktu lebih sebulan serta saat bersamaan kurs rupiah makin lunglai mendekati Rp17.000 per US$. Lebih kacau lagi, tidak dinyana, terompet perang tarif dari Presiden USA, Donald Trump, ditiup bertalu-talu sejak awal April 2025.
Masalahnya, apakah kasus-kasus #IndonesiaGelap ini akan berlangsung lama? Sulitkah Indonesia keluar dan mengamputasi pelbagai jeratan masalah itu, yang kelihatannya, spiral masalahnya acap kali direproduksi secara berulang-ulang dengan pelaku yang berbeda?
Dalam kegamangan seperti itu, teringat sosiolog kenamaan asal Norwegia, Johan Galtung dalam karyanya: “Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization” (Oslo, 1996). Kendati buku ini mengulas tentang konflik, perdamaian dan peradaban global, ada satu Bab yang membahas tentang ekonomi dan peradaban, yang bisa menjadi inspirasi untuk mengeluarkan Indonesia dari kegelapan itu.
Galtung menyebut, ada enam aliran pemikiran dan kebijakan ekonomi yang disimbolkannya warna-warni. Sejatinya, dalam teori warna, warna primer hanya Merah, Biru dan Hijau. Maka, biru adalah lambang ekonomi kapitalis yang berintikan pasar dan modal. Kemudian, merah mewakili ekonomi sosialis, bertumpu pada negara dan kekuasaan. Sedangkan hijau mewakili ekonomi Dunia Ketiga, sedang berkembang (developingcountries). Selanjutnya, ketiga aliran lain merupakan ekonomi campuran (mixedeconomy).
Akan tetapi, pengertian “campuran” menurut Galtung, yakni pertama, campuran antara Biru, Mera,h dan Hijau, yang menjadi Merah Muda atau Merah Jambu (Pink). Representasi aliran Merah Muda ini adalah negara-negara Eropa Barat minus Inggris, terutama negara-negara Nordic, yaitu negara-negara yang mengikuti konsep negara kesejahteraan (welfarestate).
Sedangkan “campuran kedua“ antara warna Biru dan Merah menghasilkan warna Kuning yang diwakili oleh negara-negara Timur Jauh, khususnya Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura, yang menggabungkan secara tegas unsur-unsur pasar dan negara, modal, dan kekuasaan.
Aliran pemikiran lain yang disebutnya, “campuran ketiga“ antara Hijau, Merah Muda dan Kuning yang dinilai sebagai kombinasi yang ideal, karena tidak langsung mencampur warna Biru dan Merah. Aliran ini masih merupakan “angan-angan”, belum ada representasinya.
Lantas, apakah “#IndonesiaGelap” memungkinkan kembali terang atau bercahaya? Apakah “campuran ketiga” yang belum ada presedennya secara global, bisa mewujudkan aliran “angan-angan” yang dikonseptualisasikan oleh Galtung, dan menjadi cahaya di Indonesia?
Bagi Indonesia, sudah cukup lama memiliki raison d’etre (dasar keberadaan) dalam menyusun kebijakan ekonomi. Ekonomi Pancasila, seperti gagasan yang dilontarkan Emil Salim (1967) dan Mubyarto (1987) atau Ekonomi Konstitusi, yang diulas Jimly Asshiddiqie (2010), mungkin sesuai harapan Galtung, campuran Hijau, Merah Muda, dan Kuning.
Ekonomi Pancasila, intinya adalah demokrasi ekonomi. Berarti partisipasi ekonomi rakyat. Inti ekonomi rakyat, didasarkan pada ”kebersamaan” (mutualendeavour) dan “kekeluargaan” (brotherhood). Mengutip Mubyarto (1987), Pancasila secara utuh maupun sendiri-sendiri mengandung 5 asas. Semua substansi sila Pancasila yaitu (1) etika, (2) kemanusiaan, (3) nasionalisme, (4) kerakyatan/demokrasi, dan (5) keadilan sosial, harus dipertimbangkan dalam model ekonomi yang disusun. Kalau sila pertama dan kedua adalah dasarnya, sedangkan sila ketiga dan keempat sebagai caranya, maka sila kelima Pancasila adalah tujuan dari ekonomi Pancasila.
Bung Hatta (1981) menyebutkan, untuk tegaknya raison d’etre itu, diperlukan sejumlah nilai instrumental. Pertama, kerjasama ekonomi dengan penekanan kepada koperasi, kedua, peran negara dan demokrasi ekonomi. Negara harus berperan aktif dalam kehidupan perekonomian. Arah, tujuan, dan strategi pembangunan harus diarahkan terciptanya pemenuhan kebutuhan pokok, jaminan sosial, peningkatan daya beli rakyat, pembangunan infrastruktur perhubungan dan transmigrasi, penataan pertanahan, lingkungan, ekspor dan impor agar tujuan dan cita-cita sosial bangsa dan rakyat Indonesia dapat diwujudkan.
Habis Gelap, Terbitlah Terang
Konsep ideal Galtung dan mimpi Bung Hatta, untuk mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Setidaknya, perlu diurai pelbagai kekusutan masalah ekonomi bangsa. Pertama, terkait pada hulu kebijakan ekonomi politik. Teringat kembali pada Bung Hatta (1981), demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sejati. Selain demokrasi politik, harus ada pula demokrasi ekonomi, yang memakai dasar, segala penghasilan yang menguasai kependudukan orang banyak, harus berlaku di bawah tanggungan orang banyak juga.
Karena itu, untuk mengurangi campur tangan pemilik modal raksasa (oligarki ekonomi) ke oligarki politik, perbaikan di tingkat hulu, terutama di partai politik (Parpol). Bagaimanapun, Parpol adalah salah satu pilar demokrasi, kawah candradimuka melahirkan pemimpin politik, dan katalis pembangunan. Jika sistem politik bekerja bermutu, maka akan melahirkan pemimpin yang kapabel dan berintegritas. Jika di tingkat hulunya sarat biaya politik tinggi, maka pemimipin politik yang terpilih justru tersandera beban konsesi atau barter ekonomi-politik.
Tumbuhnya praktik oligarki berkorelasi dalam ekosistem politik yang tidak demokratis. Merujuk riset Damanhuri (2023), pada era Refomasi, prosedur dan mekanisme demokrasi politik berjalan, tetapi oligarki ekonomi yang mengendalikan politik. Dampaknya ketimpangan dan segregasi ekonomi makin buruk.
Kedua, mengamputasi penyakit entropi ekonomi. Adanya ekonomi biaya tinggi, masih besarnya pungutan resmi/tidak resmi, korupsi makin mengganas dan masif, kebocoran anggaran negara, ekonomi rente, dan seterusnya, merupakan bagian entropi itu. Maka, entropi ekonomi telah berdampak pada sulitnya perekonomian Indonesia keluar dalam middleincome trap.
Situasi ini terkonfirmasi, ekonomi Indonesia sulit naik ke status negara dengan pendapatan tinggi. Selain itu, juga berdampak pada naiknya angka Incremental Capital OutputRatio (ICOR). Angka ICOR Indonesia masih bertengger tinggi mendekati 7 persen, sementara rerata negara Asean hanya 3,5 persen. Tingginya angka ini mengrim pesan, masih rendahnya produktivitas, rendahnya daya saing, inefisiensi, dan banyaknya biaya siluman menerpedo mesin birokrasi ekonomi.
Ketiga, reorientasi kebijakan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Hingga detik ini, ekonomi Indonesia masih ditopang oleh usaha ekstraktif berbasis sumberdaya alam, bukan ditopang oleh pengetahuan dan teknologi. Ini mengindikasikan, ekonomi Indonesia lebih ditopang otot ketimbang otak (Basri, 2023). Hal ini relevan jika melihat kontribusi Total Factor Productivity (TFP) dalam perekonomian yang rendah dibandingkan banyak negara lain.
TFP yang menjadi indikator ini dipakai untuk mencerminkan tingkat produktivitas suatu negara dan kemajuan teknologi. Jika dilihat sejak 2010, makin terlihat TFP Indonesia terus terjun bebas. Jadi, penggunaan otot semakin dominan. Dengan demikian, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2000-2020 rata-rata 71 persen ditopang modal yang berbasis non-IT. Sumbangan dari tenaga kerja mencapai 45 persen, sedangkan sumbangan modal yang berbasis IT hanya 4 persen, Sementara itu, kontribusi TFP terhadap pertumbuhan justru minus 19 persen.
Indonesia termasuk sedikit negara di kawasan yang sumbangan TFP ke dalam pertumbuhan ekonominya paling rendah, selain Myanmar, Brunei Darussalam, dan Fiji. Beberapa negara lain di kawasan, Thailand misalnya, sumbangan modal non-IT relatif rendah, sedangkan kontribusi dari TFP sebesar 19 persen. Semakin banyak pakai komponen otak (TFP), semakin kencang pertumbuhan ekonomi, semakin banyak pakai otot perkembangannya akan melambat terus.
Rendahnya TFP juga sejalan dengan gejala deindustrialisasi di Indonesia yang ditunjukkan dengan menurunnya kontribusi manufaktur terhadap PDB. Gejala deindustrialisasi ini juga terlihat dari rendahnya kontribusi ekspor manufaktur terhadap total ekspor. Maka, ketiga kekusutan masalah ekonomi Indonesia (#IndonesiaGelap), bisa menjadi IndonesiaTerang, jika kekusutan masalah itu diamputasi dengan kepemimpinan yang kuat dan tidak bimbang. (27/4/25)