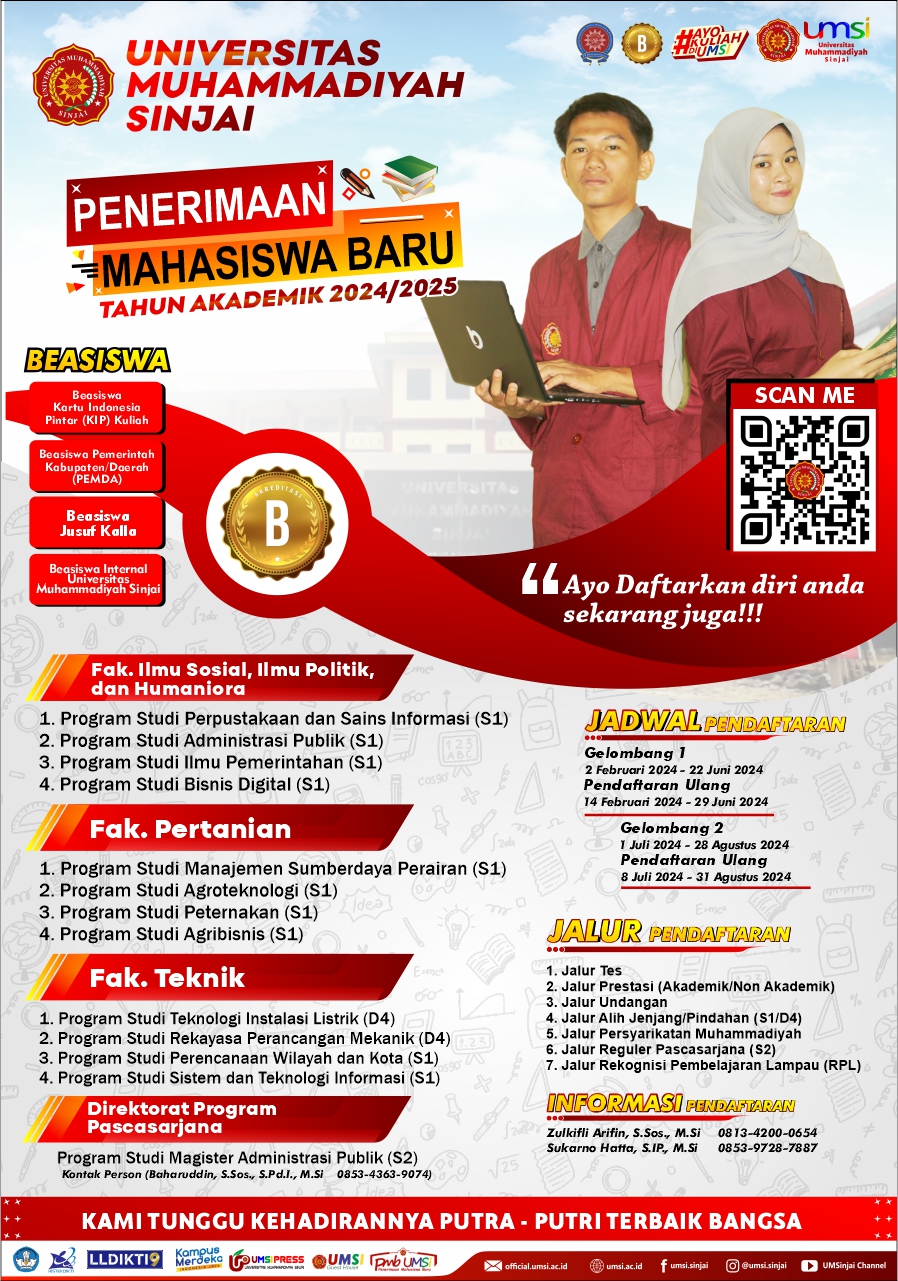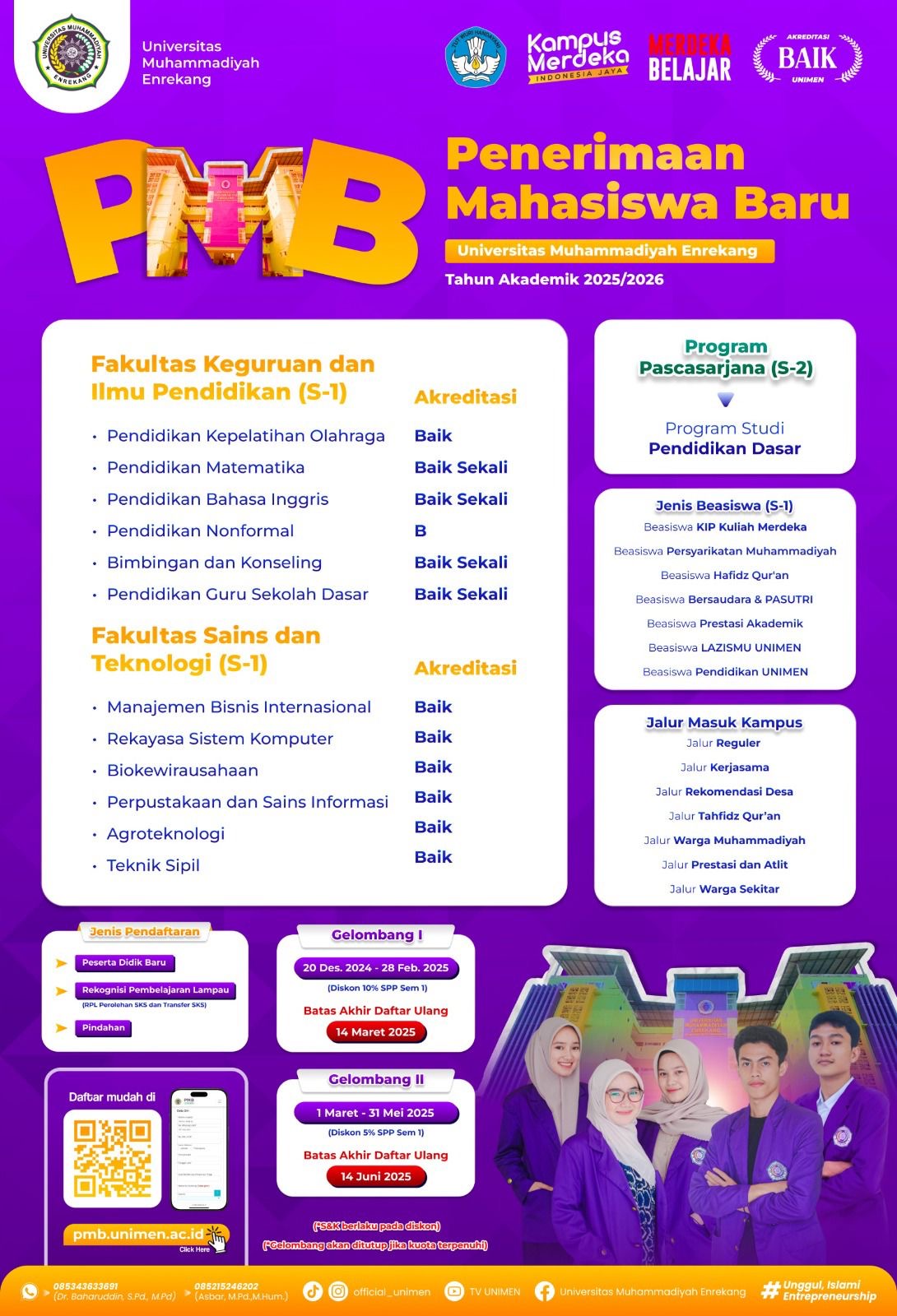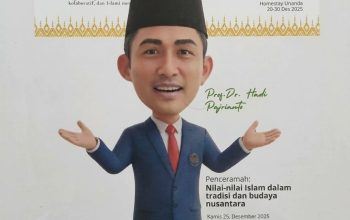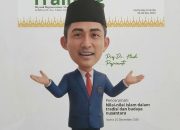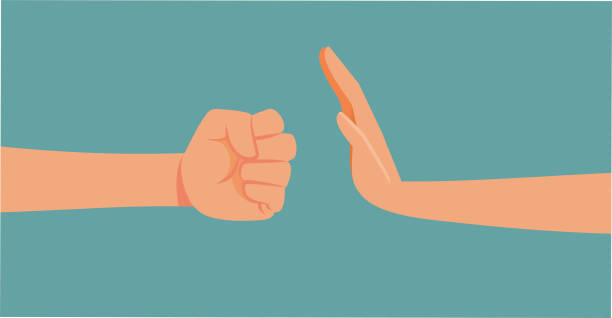
Oleh: Juwandariah Jubir
KHITTAH. CO – Tiga tahun sejak Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan pada 2022, harapan besar untuk menekan angka kekerasan seksual di Indonesia. Namun, memasuki tahun 2025, data justru menunjukkan tren peningkatan. Ironisnya, di tengah gencarnya kampanye dan sosialisasi, perilaku yang seharusnya dikategorikan sebagai pelecehan masih sering dianggap “biasa” atau “candaan”.
Perilaku seperti siulan, komentar bernada seksual, sentuhan tanpa izin, hingga pesan pribadi yang melewati batas, kerap dinilai sepele. Padahal, semua itu dapat meninggalkan trauma mendalam bagi korban. Normalisasi ini, tanpa disadari memberi ruang aman bagi pelaku untuk terus melakukan tindakan serupa, bahkan di lingkungan yang seharusnya menjadi ruang aman seperti sekolah, kantor, atau rumah ibadah, bahkan organisasi tertentu.
Bagi sebagian korban, berbicara tentang pelecehan yang dialami bukan perkara mudah. Rasa kaget saat kejadian, ketakutan akan stigma sosial, hingga kekhawatiran tidak dipercaya, menjadi penghalang besar. Terlebih ketika pelaku adalah sosok yang memiliki posisi berpengaruh atau hubungan dekat. Tentu beban psikologi korban semakin berat.
Fenomena “Cuma bercanda” adalah bentuk pembelaan terhadap pelaku, sekaligus budaya yang menormalisasi kekerasan seksual. Dalam banyak hal pelecehan tidak selalu berbentuk fisik. Pelecehan verbal atau digital dapat sama merusaknya.
Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) per Juli 2025 tercatat 15.615 kasus kekerasan, dengan kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan tertinggi yaitu sebanyak 6.999 kasus. Bentuk pelecehan terbanyak meliputi pelecehan fisik, verbal, dan kekerasan seksual berbasis digital. Namun, angka 15.615 ini bisa saja masih jauh lebih besar dikarenakan banyak kasus yang belum dilaporkan akibat rasa takut, tekanan sosial, dan budaya patriarki yang masih mengakar kuat.
Peningkatan ini seharusnya menjadi perhatian setiap pihak, dan diperlukan upaya nyata. Bukan malah menjadi pelaku dengan dalil yang tak beralasan.
Lebih dari 70 persen pelaku adalah orang yang dikenal korban, rekan kerja, atasan, guru, teman dekat, bahkan anggota keluarga. Fakta ini menegaskan bahwa masalah utama bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga budaya dan cara pandang masyarakat terhadap kekerasan seksual. UU TPKS yang diharapkan menjadi tonggak perubahan masih menghadapi tantangan besar dalam implementasi. Banyak korban tidak memahami prosedur pelaporan, sementara aparat penegak hukum belum sepenuhnya peka terhadap kerentanan korban.
Budaya yang menganggap “hal kecil” seperti komentar fisik atau chat menggoda sebagai sesuatu yang wajar, sebenarnya membuka pintu pada bentuk pelecehan yang lebih berat. ketika pelaku merasa aman, ia bisa melangkah lebih jauh.
Seperti halnya kasus pelecehan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas pada tahun 2024 silam, kita tentu tidak menyoroti dia dengan keterbatasannya, tapi fokusnya adalah kekerasan seksual yang dilakukan dan tentu perilakunya. Menurut psikologi forensik Reza Indragiri, normalisasi pelecehan seksual adalah bentuk kekerasan simbolik. “ketika masyarakat menganggap tindakan itu biasa, korban kehilangan dukungan sosial, sementara pelaku merasa dilindungi oleh norma yang keliru”.
Efeknya bukan hanya pada korban, tetapi juga pada generasi berikutnya. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan di mana pelecehan dianggap wajar, cenderung melihat perilakunya itu sebagai bagian normal dari interaksi sosial.
Perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) dan media sosial justru memperluas ruang terjadinya kekerasan seksual berbasis digital. Pengiriman gambar atau video bernuansa seksual tanpa persetujuan, penyebaran konten intim, hingga pemerasan berbasis gambar (sextortion) semakin marak. Banyak korban mengaku ragu melapor karena merasa kejadian di dunia maya tidak akan dianggap serius. Padahal, dampak psikologisnya nyata: stres berat, depresi, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup.
Melawan normalisasi kekerasan seksual tidak cukup hanya dengan hukum. Butuh perubahan cara pandang masyarakat. Edukasi sejak dini tentang batasan tubuh, persetujuan (consent), dan perilaku yang pantas harus menjadi bagian dari kurikulum dan percakapan sehari-hari.
Media juga memegang peran penting. Pemberitaan yang sensasional tanpa empati bisa melukai korban kedua kalinya (secondary victimization). Sebaliknya, pemberitaan yang tepat dapat membangun kesadaran publik dan mendorong perubahan.
Setiap korban berhak mendapatkan dukungan, bukan keraguan. Menganggap remeh pelecehan adalah bentuk pengkhianatan terhadap korban. Tindakan kecil seperti membela korban di ruang publik, melaporkan pelaku, atau sekadar mendengarkan cerita korban dengan empati, dapat menjadi langkah besar melawan budaya normalisasi.
Diam berarti membiarkan. Normalisasi kekerasan seksual hanya akan berhenti ketika kita semua berani mengatakan: ini salah, dan tidak akan dibiarkan.
Kasus demi kasus yang terungkap hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan, ada ribuan cerita yang tak pernah terdengar. Selama perilaku pelecehan, sekecil apa pun, masih dianggap lumrah, maka perjuangan melawan kekerasan seksual akan selalu tertinggal selangkah.
Maka, pertanyaannya kembali pada kita semua: Apakah kita masih akan menganggap normalisasi kekerasan seksual sebagai sesuatu yang wajar?