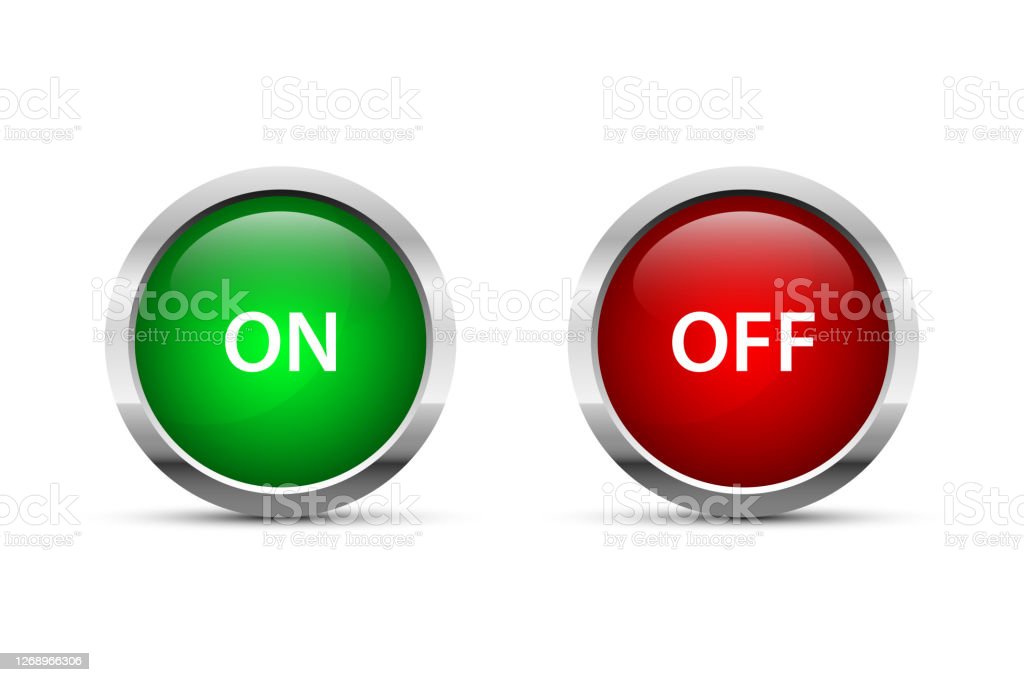
Oleh: Agusliadi Massere*
KHITTAH.CO, – Secara psikologis, ibadah puasa, ibadah dan/atau amalan lainnya yang dilaksanakan selama 29/30 hari dalam bulan Ramadan, idealnya membentuk suatu habits atau bahkan sejenis habitus ala perspektif Pierre Bourdieu. Artinya, nilai, fungsi dan makna yang melekat pada sejumlah ibadah atau amalan itu (tanpa kecuali puasa) mengalami sejenis internalisasi eksterior (nilai-nilainya itu terserap ke dalam diri/jiwa) umat Islam (yang berpuasa) dan selanjutnya memberikan pengaruh dan terwujud dalam sebuah praksis. Praksis ini sebagai proses eksternalisasi interior (implementasi nilai dalam realitas kehidupan), dalam bahasa diskursus agama Islam mungkin tidak keliru jika disebut dengan “takwa”, “ketakwaan” dan “spiritualitas ihsan”.
Pemahaman di atas penting menjadi starting point (titik berangkat) untuk memahami secara rasional, bukan semata berada dalam ranah keyakinan, bahwa betul dan idealnya bulan Ramadan itu mampu mengaktivasi nalar ketuhanan dan kemanusiaan. Kedua nalar ini menjadi penting karena sesuai dengan esensi dan eksistensi manusia, sebagai makhluk individual, fisik-biologis, dan sekaligus sebagai makhluk spiritual.
Sebelum lebih jauh, saya menguraikan perihal bulan Ramadan, dan aktivasi nalar ketuhanan dan kemanusiaan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu suatu hal yang menarik dari Denny JA dan sekaligus bisa saja ada pembaca yang kaget dan mungkin tidak percaya. Hal menarik dari Denny JA adalah data dan/atau hasil riset yang diungkap dalam bukunya yang berjudul 11 Fakta Era Google Bergesernya Pemahaman Agama Dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama. Untuk memudahkan apa yang dimaksud dengan Era Google, Denny JA dalam bukunya itu menegaskan—bisa pula disebut—“Revolusi Industri 4.0”.
Data yang menarik itu adalah sebagai berikut: Pertama, pada posisi Top 10 negara yang warga negaranya paling bahagia, mayorintas warganya menganggap agama tak lagi penting. Kedua, pada posisi top 10 negara yang pemerintahannya paling bersih korupsi, mayoritas warga negaranya menganggap agama tak lagi penting. Dan ketiga, posisi top 10 negara yang warga negaranya paling sejahtera, mayoritas menganggap agama tak lagi penting.
Ketiga data di atas, khususnya bagi umat beragama tanpa kecuali yang fanatik terhadap agamanya, lebih khusus lagi umat Islam pasti kaget dan mungkin tidak percaya. Namun data yang diungkap oleh Denny JA di atas adalah hasil riset oleh lembaga yang kredibilitasnya tidak diragukan apalagi setelah saya membaca, bagaimana metodologi pengambilan datanya sangat komprehensif tanpa tendensi yang sengaja menyudutkan agama. Jika pembaca tertarik ingin membaca lebih mendalam dan ingin mengetahui nama negara-negara yang masuk “Top 10 Negara” dari buku Denny JA tersebut, bisa meminta ke saya untuk dikirimkan buku versi pdfnya, melalui nomor WhatsApp 085243081654.
Awalnya saya juga kaget dan tidak percaya, tetapi setelah membaca buku tersebut, metodologi pengambilan datanya sangat akurat dan terpercaya. Lalu setelah itu, saya sangat prihatin karena Indonesia tidak masuk dalam daftar “Top 10 Negara” paling bahagia, paling bersih dari korupsi, dan paling sejahtera.
Dan yang sangat menyedihkan, Indonesia yang sangat dikenal sebagai negara religious—meskipun tidak ada satu agama pun yang dijadikan sebagai agama resmi negara—apalagi mayoritas penduduknya adalah umat Islam, seakan memperkuat kebenaran data hasil riset tersebut. Menjadi fenomena konfirmatif bahwa betul—dengan logika terbalik—karena Indonesia menganggap agama sangat penting, sehingga (mungkin) itu yang menjadi faktor sehingga tidak bisa menjadi negara yang paling bahagia, paling bersih dari korupsi, dan paling sejahtera.
Saya pun merenung, sambil membaca argumentasi yang menjadi alasan berdasarkan posisinya masing-masing, ternyata jika mencermati fenomena yang selama ini terjadi, sangat rasional dan bagi saya tepat sekali Indonesia sedang mengalami apa yang diungkap dalam buku itu, sehingga wajar jika Indonesia tidak masuk dalam “Top 10 Negara” paling bahagia, bersih dari korupsi, dan paling sejahtera.
Jika seperti itu, lalu apa fungsi, nilai dan makna ibadah-ibadah, termasuk puasa yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Apa arti tulisan-tulisan saya, selama 28 hari (setiap hari) yang saya produksi sebelum tulisan ini, termasuk 30 tulisan yang saya produksi setiap hari pada bulan Ramadan tahun lalu (1442 H), ketika semua hasil perenungan, yang diperkuat dengan landasan kajian ilmiah, yang pada substansinya, tulisan-tulisan tersebut berupaya meyakinkan pembaca khususnya umat Islam tentang pentingnya agama, keimanan, puasa, dan berbagai ibadah lainnya yang masuk dalam determinan dari agama itu sendiri, baik dalam dimensi transendensi maupun dimensi profane-imanen. Hasil riset di atas seakan telah membantah semuanya, dan penegasan risetnya, agama tidak penting.
Ataukah agama hanya sebagai pseudo religious (terkesan hanya sebagai pelarian ketika sedang galau) atau religion tainment (hanya sebagai alat untuk mencapai kepentingan-kepentingan duniawi semata). Dua istilah menarik dan menggelitik ini, dan termasuk tidak diharapkan terjadi, pertama kali saya baca dari tulisan artikel Kak Hadi (panggilan akrab saya ke Hadi Saputra). Istilah ini pun, dipinjam dari seorang aktivis NU, yang saya sudah lupa namanya, tetapi jika tidak salah ingat, dalam tulisan Kak Hadi tersebut, nama itu disebut dengan jelas.
Saya pribadi, meskipun telah membaca buku Denny JA itu, tetap merasa yakin bahwa agama dengan berbagai determinannya yang ideal, itu tetap penting. Keyakinan saya bukan bersifat doktiner dan dogmatisme, tetapi tetap berpijak pada hasil perenungan, pembacaan dan pemahaman termasuk dari referensi yang bisa diyakini sebagai sesuatu yang rasional dan bisa dibuktikan keilmiahannya.
Untuk membuktikan keyakinan saya, bahwa agama tetap penting khususnya dalam konteks tulisan ini terkait bagaimana bulan Ramadan mampu mengaktivasi nalar ketuhanan dan nalar kemanusiaan sebagai sesuatu yang urgen, signifikan dan memiliki impilikasi besar dalam kehidupan, pertama saya tetap bertolak pada buku Denny JA itu sendiri.
Era google pun pada dasarnya jika kita ingin mengindentikkannya pada sesuatu, maka itu identik dengan informasi dan dinamika kehidupan yang mengitari atau mendominasi. Karena informasi dan dinamika kehidupan ini mengitari dan mendominasi maka dipandang memengaruhi cara pandang tanpa kecuali dalam memahami agama. Memengaruhi cara pandang sebagaimana dalam tulisan ini identik dengan istilah atau diksi “mengaktivasi nalar”.
Jika era google dipandang sebagaimana arguemntasi di atas, maka sesungguhnya bulan Ramadan pun yang dilaksanakan selama 29/30 hari dalam setiap tahunnya, itu bahkan bukan sekadar informasi dan dinamika, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang mengandung nilai, makna, fungsi, dan sakralitas (kewajiban) yang sesungguhnya sangat kompatibel dengan chip yang telah ditanamkan atau built-in dalam diri manusia. Manusia dalam dirinya telah ditiupkan roh oleh Allah yang telah melalui komitmen ilahiah. Selain itu dalam awal penciptaannya telah dibekali pengetahuan tentang segala sesuatu dalam rangka mendukung fungsi kekhalifahannya. Berarti secara logis, berangkat dari cara pandang buku itu sendiri, dalam reinterpretasi saya akan lebih dahsyat lagi dalam memengaruhi cara pandang. Yang dalam istilah ini, saya menyebutnya bulan Ramadan mengaktivasi nalar ketuhanan dan nalar kemanusiaan.
Selain itu, dalam buku 11 Fakta Era Google Bergesernya Pemahaman Agama Dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama. Denny JA pun mengajukan pertanyaan kritis dan dijawabnya pun dengan jawaban yang sangat rasional dan kita bisa memahami bahwa agama tetap penting, tetapi dengan persyaratan. Denny JA mengajukan pertanyaan, “Lalu burukkah pengaruh agama di ruang publik berdasarkan data di atas?. Denny memberikan jawaban tegas bahwa “Itu tergantung dari bagaimana agama ditafsirkan”.
Adalah Denny JA menegaskan kembali bahwa “Yang buruk itu adalah tafsir agama yang “main hakim sendiri,” membenarkan elemen kekerasan, dan menyebar sentimen permusuhan. Tapi agama seperti yang dikembangkan Jalaluddin Rumi, itu justru membawa kedalaman. Salah satu renungan Jalaludin Rumi “Agamaku adalah cinta. Setiap hati itu rumah suciku.”
Ketika hasil riset itu dilengkapi dengan alasan yang mempertegaskan tiga kunci terkait yang membuat negara yang masuk “Top 10 Negara” yang paling bahagia meskipun di satu sisi menganggap agama itu tidak penting, ternyata tiga kuncinya adalah sebagai berikut: social trust, freedom to make life choice, dan social support. Ternyata Denny JA pun menegaskan “Jika agama yang dominan dipeluk ditafsir dengan spirit Rumi, justru spirit agama itu tak hanya memperkuat social trust dan freedom to make life choice. Ia juga membawa kita pada kebahagiaan otentik.*
Dalam buku Denny JA yang lain pun, Spirituality of Happiness (2019), dijelaskan bahwa para ahli neuroscience telah menemukan dalam otak apa yang disebut dengan “hormon bahagia” (happy hormones). Denny JA menegaskan “Itu adalah Dopamine, Serotonin, Oxytocine, dan Endorphine. Ini hormon yang jika tumbuh, dan dihidupkan mampu mengaktivasi hormon bahagia. Dan bagi saya salah satu cara untuk menghidupkan horman bahagia tersebut adalah ketika mampu melakukan mekanisme pemaknaan hidup, dan itu lebih banyak dalam ranah kecerdasan spiritualitas yang bisa ditunjang dengan pemahaman agama yang baik. Jadi intinya agama tetap penting.
Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sebelum memasuki pembahasan terkait nalar ketuhanan dan kemanusiaan tersebut adalah. Dalam buku Denny JA, saya mendapatkan satu kesimpulan yang membuat suatu negara masuk dalam “Top 10 Negara” yang paling bersih dari korupsi, tetapi warga negaranya menganggap agama itu tidak penting, alasannya karena menurutnya yang bisa mengendalikan korupsi adalah manajemen modern. Namun bagi saya tidak cukup dengan manajemen modern, karena ini pun memerlukan humanware (pengendalian dari manusia yang menjalankannya). Sedangkan mekanisme pengendalian terbaik bisa lahir dari dalam diri manusia adalah ketika dia memiliki kesadaran terhadap nilai, kewajiban, dan larangan yang diajarkan dari agamanya. Seperti puasa dalam bulan Ramadan sesungguhnya mengandung mekanisme pengendalian diri yang sangat ampuh.
Lalu, bagaimana bulan Ramadan mampu mengaktivasi nalar ketuhanan dan kemanusiaan. Nalar dalam pandangan saya adalah sesuatu yang memengaruhi doing (apa yang dilakukan), relation (bagaimana berinteraksi), meaning (bagaimana memaknai), thinking (bagaimana dan apa yang dipikirkan), dan being (bagaimana cara menjadi).
Bulan Ramadan, khususnya untuk ibadah puasa, dalam pandangan saya itu mampu mengaktivasi nalar ketuhanan, karena yang mampu bertahan untuk menjalankan puasa sesuai dengan tuntunan yang sebenarnya, bukan hanya sekadar menahan haus, lapar dan nafsu seks, adalah orang yang senantiasa fokus dan menyadarikan kehadiran Allah atau dirinya sedang diawasi Allah. Jadi dengan berpuasa di bula Ramadan, berarti hal ini sebagai sesuatu yang bisa dimaknai aktivitas atau ibadah akan mampu mengaktivasi nalar ketuhanan. Ketuhanan di sini, memiliki makna bahwa menarik atau menangkap percikan sifat-sifat Tuhan, yang bagi diri saya lebih senang menyebut Allah.
Dengan teraktivasinya nalar ketuhanan ini, maka itu akan memengaruhi doing, relation, meaning, thinking, dan being kita untuk tetap berada dalam rel atau garis orbit yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan jika ini yang dikedepakan saya yakin, kita pun tetap menganggap agama penting bahkan paling utama dan sebagai core value untuk menjadi diri, suatu bangsa negara untuk menjadi paling bahagia, paling bersih dari korupsi, dan paling sejahtera.
Begitu pun dengan berpuasa saja, sebenarnya jika kita resapi itu akan mengaktivasi nalar kemanusiaan, minimal akan memantik rasa empati. Dan ini sangat terbukti dalam realitas kehidupan, bagaimana suasana, spirit dan semangat berbagi pada bulan Ramadan dibanding 11 bulan lainnya. Jadi dengan berpuasa pada bulan Ramadan maka aktivasi nalar kemanusiaannya semakin baik, semakin di-refresh dan di-upgrade.
Lalu bagaimana fenomena yang ada, ketika semua itu belum berbanding lurus, atau belum berkorelasi positif dalam sikap dan perilaku baik secara personal, bangsa, dan negara, yang termasuk—dalam data hasil riset tersebut di atas—seakan Indonesia sulit membantah ketika dirinya tidak dimasukkan dalam “Top 10 Negara”, sebenarnya saya senantiasa akan menegaskan bahwa bukan karena agamanya, tetapi lebih pada personal pemeluk agamanya dalam menafsirkan, memahami, dan mengamalkan ajaran agama. Apakah niatnya benar-benar tulus atau seperti apa, itu urusan hati masing-masing dan hanya Allah yang bisa mengetahui secara tepat.
Apalagi dalam agama Islam pun tetap dipertegas bahwa ada orang, sebagai contoh saja, orang berpuasa tetapi yang didapatkan hanya hanya haus dan lapar, tidak mampu mencapai apa yang menjadi tujuan utama puasa sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 183, yaitu agar “bertakwa”. Dan ini adalah sebagai puncak prestasi spiritual.
*Mantan Ketua PD. Pemuda Muhammadiyah Bantaeng. Komisioner KPU Kabupaten Bantaeng Periode 2018-2023.






















