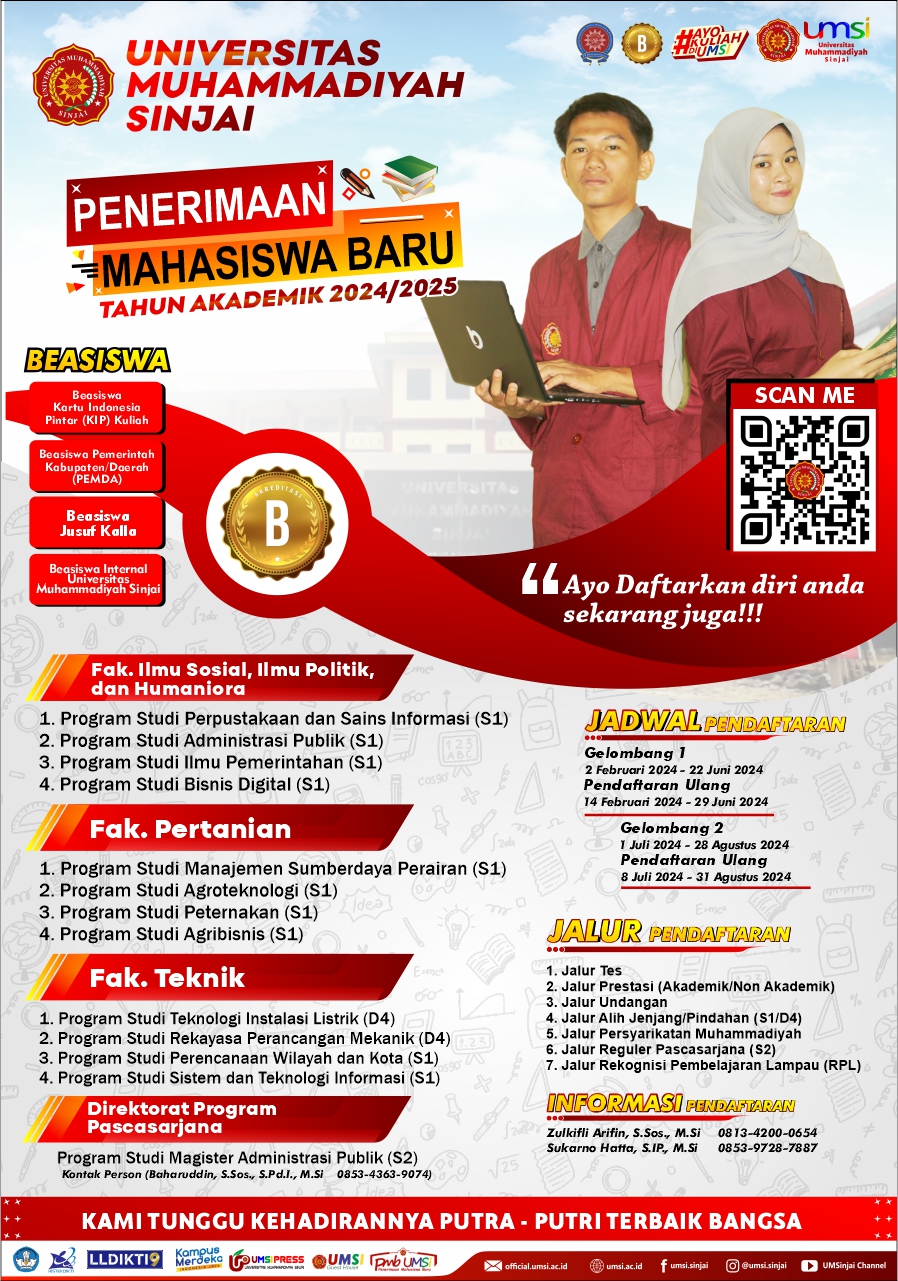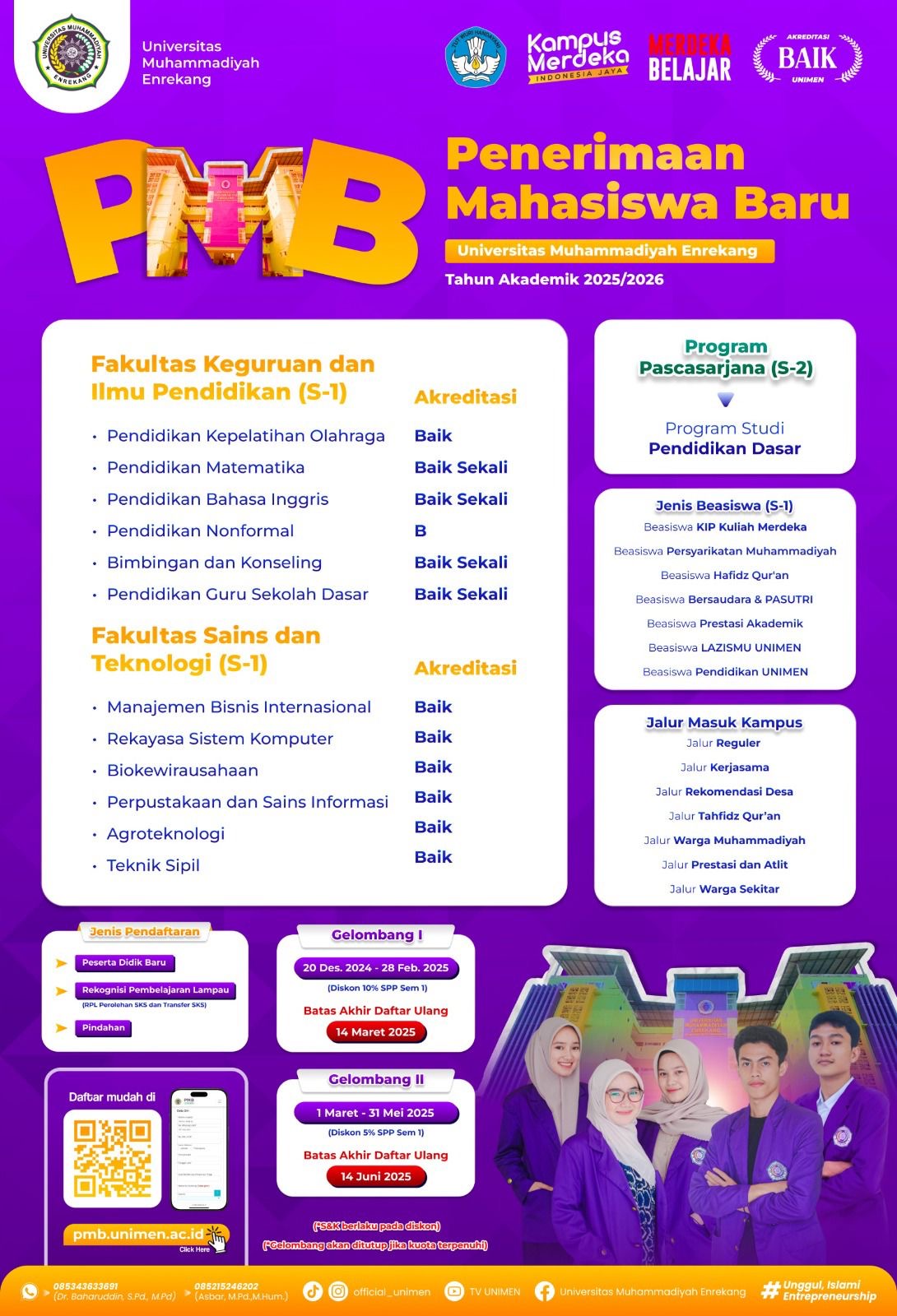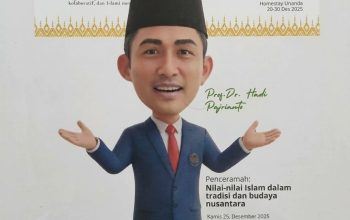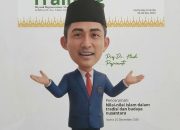Oleh: Multazam Ahmad (Founder Mata Project Indonesia)
KHITTAH. CO – Dalam sejarah panjang bangsa-bangsa, ekspresi pemuda sering kali menjadi isyarat awal perubahan. Revolusi-revolusi besar dunia hampir selalu diawali oleh gejolak pemikiran yang lahir dari ruang-ruang intelektual dan simbol-simbol kebudayaan populer. Di Prancis abad ke-18, pamflet dan karikatur mengguncang aristokrasi. Di Indonesia, pidato-pidato pemuda 1928 dan selebaran-selebaran pergerakan nasional.
Menjadi nyala awal kemerdekaan. Hari ini, di zaman digital, meme menjadi salah satu bentuk baru dari selebaran-selebaran lama itu. Peristiwa yang melibatkan seorang mahasiswi dari Institut Teknologi Bandung karena mengunggah meme tentang Presiden Prabowo dan mantan presiden Jokowi mengundang perdebatan publik yang lebih luas daripada sekadar soal konten digital. Ia menyentuh jantung persoalan relasi negara dan warga, bahasa simbolik generasi muda, serta batas antara ekspresi dan represi dalam masyarakat demokratis.
Dari sudut pandang teori komunikasi politik, khususnya yang berpijak pada gagasan Jurgen Habermas tentang ruang publik, ekspresi semacam meme merupakan bentuk partisipasi simbolik dalam diskursus publik. Ia bukan sekadar lelucon visual, tetapi bisa menjadi kritik sosial, protes diam, atau bahkan tanda dari keinginan untuk didengar. Dalam pandangan Manuel Castells, era digital telah menciptakan “networked individualism”, di mana individu bukan hanya penerima informasi, melainkan juga penghasil narasi.
Namun, ketika simbol-simbol baru ini dibalas dengan tindakan represif, negara berisiko kehilangan kepekaan terhadap semangat zaman. Represi terhadap ekspresi simbolik hanya akan memperlebar jarak antara negara dan generasi muda. Kita pernah belajar dari tragedi Malari 1974 dan gerakan mahasiswa 1998: ketika negara terlalu kaku membaca sinyal zaman, maka sejarah bergerak tanpa koordinasi, kadang penuh luka.
Menggeser Peran: Dari Oposisi Menuju Ko-Konstruksi
Saya percaya bahwa masa depan demokrasi tidak bisa hanya bertumpu pada dikotomi “penguasa dan oposisi”. Demokrasi yang sehat meniscayakan kehadiran warga negara aktif yang mampu bertransformasi dari pengkritik menjadi penyusun agenda. Kritik memang penting—ia adalah alat kontrol. Namun, di balik kritik, harus ada imajinasi baru tentang masa depan.
Dalam konteks inilah saya meyakini bahwa generasi muda hari ini tidak cukup hanya memproduksi wacana, tetapi harus juga merumuskan jalan aksi. Kita perlu menciptakan generasi yang bukan hanya “protes”, tetapi juga “prototipe”—yakni mampu menyusun rancangan, kebijakan, dan tindakan yang nyata.
Indonesia tengah berada pada era demografik yang unik: bonus usia produktif di satu sisi, dan disrupsi teknologi di sisi lain. Tantangan-tantangan baru seperti AI, ekonomi gig, perubahan iklim, hingga krisis tenaga kerja global menuntut kehadiran anak muda bukan hanya sebagai aktivis kampus, tetapi sebagai aktor pembangunan yang melintasi batas-batas negara.
Sebagai founder dari Mata Project Indonesia, saya melihat sendiri betapa besar potensi anak-anak muda Indonesia. Di pelosok dan di kota, mereka punya ide-ide segar, energi yang melimpah, dan keberanian untuk menjelajah dunia baru. Namun, potensi ini sering terhambat oleh tiga hal: kurangnya akses, kaburnya arah, dan minimnya afirmasi dari sistem.
Orientasi pendidikan tinggi kita selama ini lebih sering menjadikan kampus sebagai panggung kontestasi gagasan, tetapi tidak membekalinya dengan perangkat untuk menghadapi kompleksitas dunia nyata. Mahasiswa diajari berpikir kritis, tapi tidak cukup dipandu untuk bertindak kolaboratif. Ini mengingatkan pada kritik Antonio Gramsci terhadap “intelektual tradisional” yang terlalu tenggelam dalam dunia gagasan, tanpa bersentuhan langsung dengan praksis sosial.
Kita membutuhkan jembatan yang menghubungkan dunia pemikiran dan dunia tindakan. Dan jembatan itu bisa berupa media baru, platform dialog, hingga kebijakan afirmatif negara untuk melibatkan anak muda secara nyata dalam proses pembangunan. Media komunikasi publik dan ruang-ruang partisipatif digital harus menjadi arena baru pembentukan warga negara aktif.
Bangsa Tidak Menunggu Amarah, Tetapi Arah
Ada sebuah pepatah lama yang berbunyi, “Bangsa besar bukan yang tidak pernah marah, tetapi yang mampu mengubah amarah menjadi arah.” Kritik adalah awal, tetapi bukan tujuan. Jika Soekarno memulai dari tulisan-tulisan “Indonesia Menggugat”, maka ia menutup hidupnya dengan mewariskan Trisakti: berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kritiknya menjadi gagasan, gagasannya menjadi gerakan, gerakannya menjadi negara.
Kita, generasi hari ini, harus melanjutkan tradisi itu. Dari meme ke misi, dari keresahan ke gerakan, dari ruang digital ke ruang kebijakan. Inilah saatnya generasi muda hadir bukan hanya sebagai bayangan perubahan, tetapi sebagai terang dari masa depan.