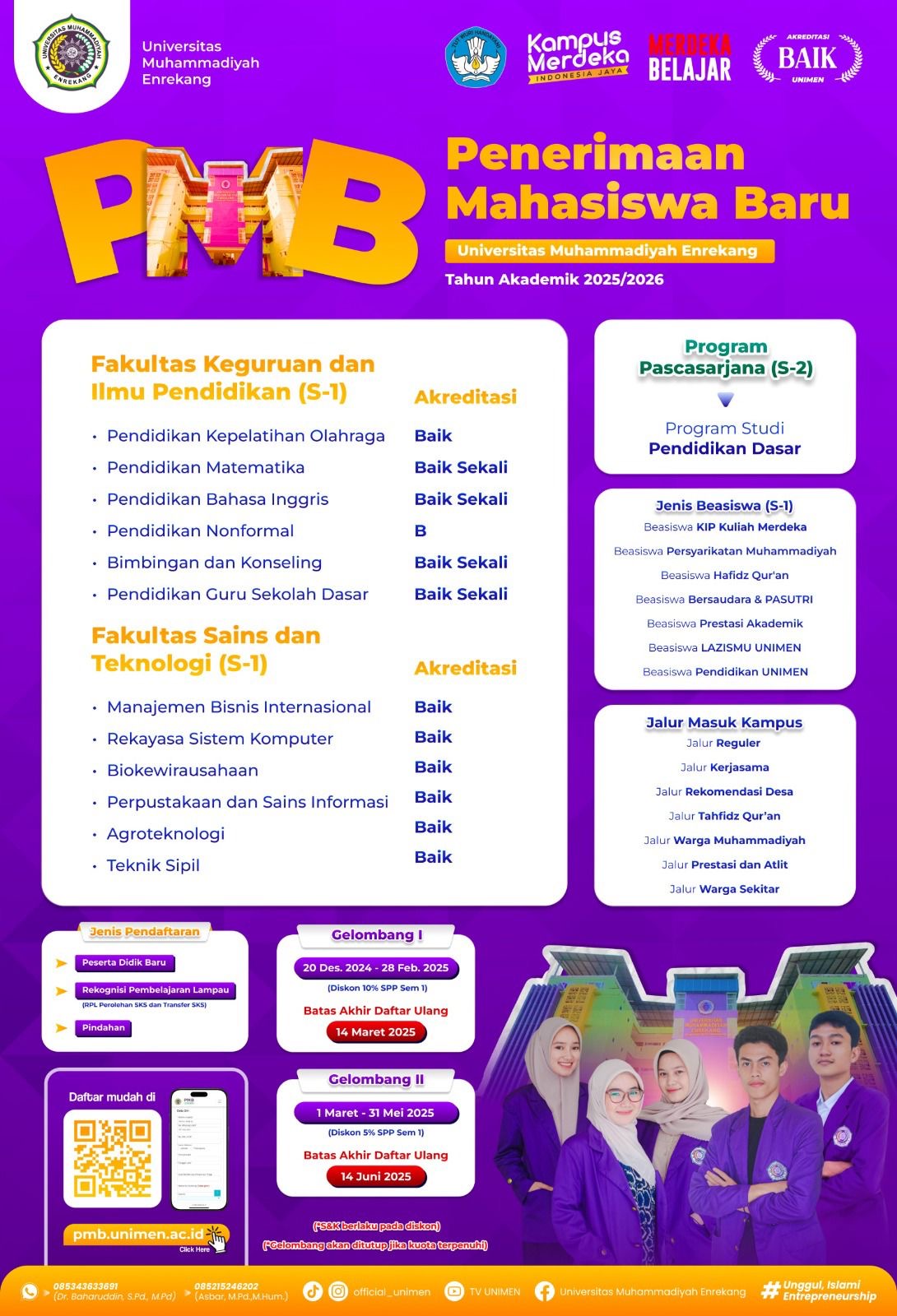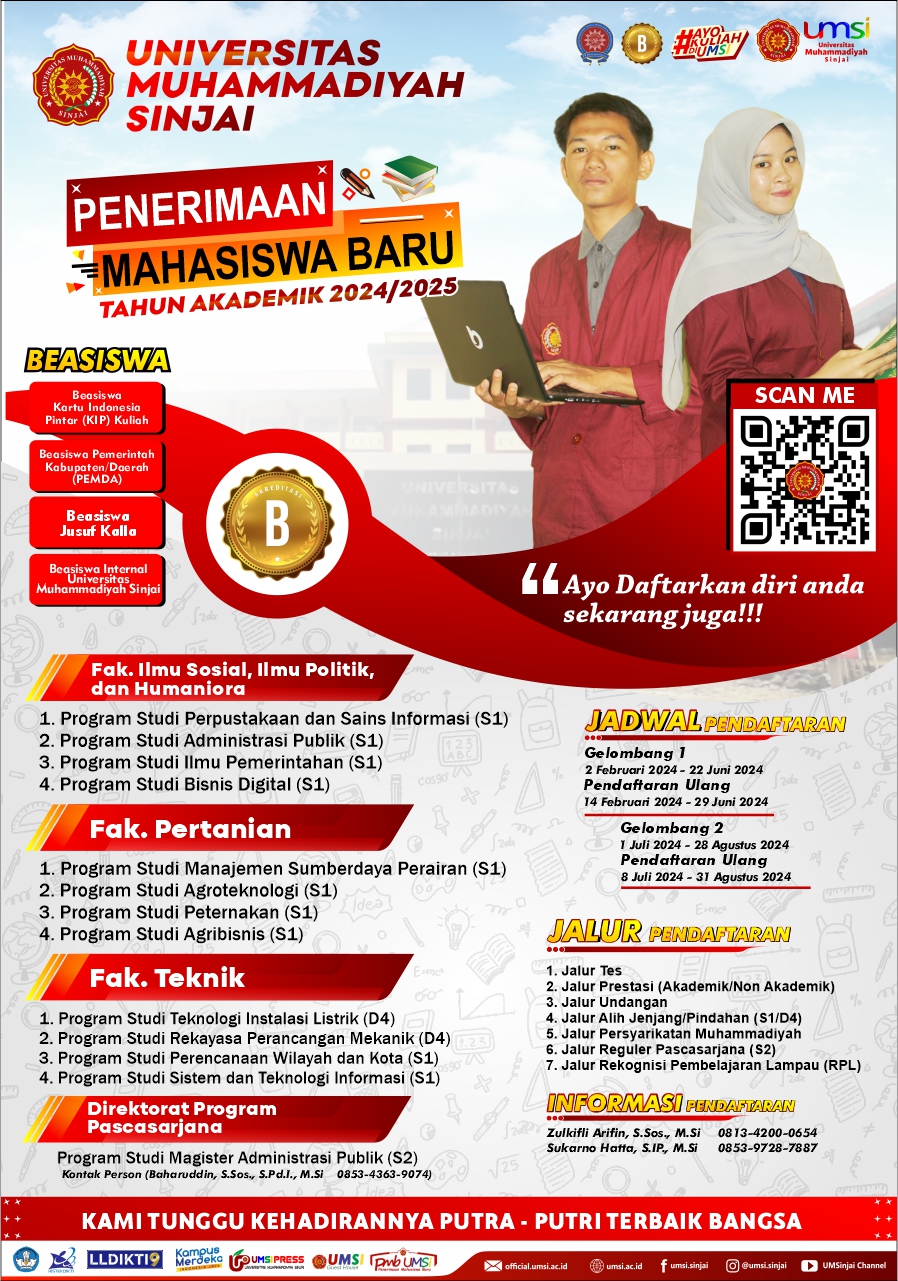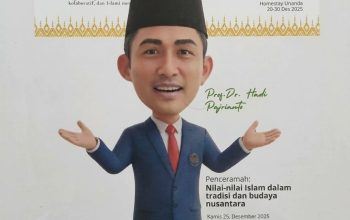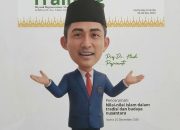Oleh: Agusliadi Massere*
KHITTAH. CO – Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di alinea keempat salah satu tujuan negara adalah “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Minimal bagi saya—mungkin ada sahabat pembaca lainnya yang setuju—bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, tidak hanya melalui pendidikan formal. Sejatinya segala dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki irisan, pengaruh, dampak, dan/atau berimplikasi positif atau negatif terhadapnya.
Kita semua pasti berharap agar segala dinamika kebangsaan dan kenegaraan itu berimplikasi positif terhadap (salah satu) tujuan mulia yang telah dirumuskan oleh Bapak/Ibu Para Pendiri Bangsa: “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Jika, kita memiliki komitmen kuat dengan tujuan mulia ini, maka semestinya segala sikap dan tindakan, tanpa kecuali pola komunikasi yang kita tampakkan khususnya di ruang publik, mendapatkan porsi perhatian yang serius dan besar terbingkai dengan pemahaman dan kesadaran tinggi atas nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Apa lagi bagi sosok yang telah dipandang sebagai figur publik oleh seseorang atau sekelompok orang, dan lingkup yang lebih luas oleh masyarakat pada umumnya, pasti memiliki posisi penting. Seorang figur publik akan dijadikan patron oleh seseorang dan/atau masyarakat. Figur publik memiliki followers (para pengikut). Segala sikap, tindakan, bahkan pola komunikasinya menjadi rujukan bagi orang lain khususnya para followers-nya.
Sedangkan yang dimaknai sebagai figur publik, bisa seorang pejabat negara, pejabat publik, pemimpin, pimpinan institusi atau organisasi kemasyarakatan, keagamaan, dan kepemudaan tertentu. Figur publik juga, itu bisa diduduki oleh para artis tertentu, dan ini yang banyak. Di era digital hari ini, bahkan para influencer dan content creator (kreator konten) ada yang sudah menjadi sebagai figur publik. Para dai dan mubalig tertentu ada pula yang sudah dipandang sebagai figur publik oleh sekelompok orang bahkan masyarakat.
Yang harus pula dipahami, bahwa pelekatan identitas dan atribusi figur publik bagi seseorang bukanlah sesuatu yang berstatus statis dan pasif. Melainkan bersifat dinamis dan aktif dalam makna memancarkan pengaruh, baik berefek secara psikologis bagi orang lain, maupun dalam pengaruh kekuatan pesan dan kesan dari informasi yang disampaikannya. Hal ini disebabkan, selain karena figur publik—sebagaimana telah ditegaskan di atas—memiliki follower (pengikut) dan perhatian orang tertuju kepadanya, juga melekat tanggung jawab moral dan sosial dalam kehidupannya.
Ketika, mereka mungkin dengan karakternya yang kharismatik, follower-nya yang sudah banyak, ketokohan, dan jabatan publiknya sehingga oleh seseorang, sekelompok orang dan/atau masyarakat luas, sosok itu dinilai sebagai figur publik, maka sejatinya mereka itu semakin menambah wawasannya, meningkatkan pemahaman dan kesadarannya, bahwa dirinya sudah memiliki tanggung jawab sosial dan moral yang besar, salah satunya, dan terutama relasinya atas tujuan mulia itu “Mencerdaskan kehidupan bangsa”. Apa lagi urusan “Mencerdaskan kehidupan bangsa” harus dipandang sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya negara.
Sederhananya dan ini penting, dia atau mereka para figur publik itu harus menjadi—meminjam istilah Yudi Latif, sebagaimana judul bukunya—sumber “Mata Air Keteladanan”. Jadi, sekali lagi segala sikap, tindakan, dan pola komunikasinya harus mampu memancarkan keteladanan.
Membaca buku Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan (2014) karya Yudi Latif, saya mendapatkan pemahaman dan kesadaran mendalam betapa pentingnya keteladanan itu. Sebagaimana yang terungkap pula dalam buku tersebut, kita sedang mengalami krisis keteladanan. Bahkan, di dalamnya terungkap harapan besar agar kita mampu mentransmisikan keteladanan itu—yang mungkin hari ini sedang masih posisi “gagal” untuk dilakukan secara masif.
Kaitannya dengan keteladanan untuk konteks kehidupan hari ini ada hubungannya bagi seseorang yang telah melekat pada dirinya sebagai figur publik. Keterkaitan berikutnya adalah dengan sikap, tindakan, dan tanpa kecuali pola komunikasinya. Pola komunikasi, tentu saja di dalamnya merefleksikan sikap dan tindakan itu sendiri. Oleh karena itu, tidak keliru jika melalui tulisan ini, saya fokus ingin menyorot Etika Komunikasi Figur Publik, tentu di dalamnya ini termasuk pola komunikasi.
Apa lagi jika merujuk pada pandangan Jalaluddin Rakhmat (Kang Jalal), komunikasi menyentuh segala aspek kehidupan. Bahkan, 70% waktu bangun kita digunakan untuk berkomunikasi. Yang paling menarik dan penting dari Kang Jalal, bahwa “Komunikasi menentukan kualitas hidup kita”. Kesimpulan Kang Jalal ini, minimal bagi saya itu relevan apa yang menjadi harapan dan telah terungkap di atas hubungannya dengan salah tujuan mulia para pendiri bangsa: “Mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Komunikasi pun tidak hanya dilakukan secara verbal, juga secara nonverbal. Komunikasi yang mengandung pesan dan kesan, kini di era digital hari ini, jangkauan dan pengaruhnya semakin luas dan mendalam. Bahkan, tidak sedikit mengandung hal paradoks dan mudah dipahami oleh para komunikan (penerima pesan).
Akhir-akhir ini—mungkin setahun terakhir, bisa lebih, bisa juga kurang atau beberapa bulan yang lalu, termasuk dalam bulan Ramadan ini—kita menyaksikan adanya oknum pejabat, begitu pun dai atau mubalig yang pola komunikasi publiknya itu tidak sesuai harapan sebagai figur publik. Kurang mencerminkan—untuk tidak mengatakan “tidak mencerminkan”—sebagai sosok pejabat dan dai yang semestinya sikap, tindakan, dan pola komunikasinya mencerminkan keteladanan yang akan bermuara pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Terkesan bukan hanya pola komunikasinya yang rendah, tetapi sama sekali merusak pula etika komunikasi dengan kata lain niretika. Komunikasinya tidak mencerminkan empati atas kehidupan orang lain. Yang berposisi sebagai pejabat komunikasinya tidak mengandung empati bagi rakyat atau masyarakat. Selain tidak mengandung empati, sering kali pola komunikasinya pun seakan melupakan posisi dirinya selaku pejabat yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang sesuai dengan persoalan yang sedang disorotinya. Begitu pun jika dia adalah dai atau mubalig, tidak menyadari bahwa dirinya sedang mendakwahkan nilai kebenaran dan kebaikan.
Menjaga etika komunikasi, memang harus dibingkai—bukan hanya dengan kecerdasan intelektual—kecerdasan emosional dan spiritual menjadi penting. Kecerdasan emosional ini bukan hanya dalam wujud lemah lembut, atau intonasi suara lemah dan lambat, ini adalah makna yang sangat sempit. Tetapi, kita harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Seorang figur publik apa lagi yang berperan sebagai pejabat publik, perasaan dan harapan masyarakat itu sangat penting untuk diperhatikan dalam pola komunikasinya. Asertif sebagai sesuatu yang sangat penting dalam komunikasi yang berbasis pada kecerdasan emosional sangat penting di dalamnya.
Apa yang saya maknai sebagai etika komunikasi dan komunikasi bukan hanya dalam bentuk verbal, melainkan termasuk nonverbal, maka cara kita—jika kita adalah figur publik yang sedang berada di ruang publik—tertawa dan/atau sedang menertawai sesuatu harus pula terukur dengan baik, dalam perhatian serius, bukan hanya dibingkai dengan kecerdasan intelektual, tetapi harus dibingkai pula dengan kecerdasan emosional dan spiritual.
Sama halnya ketika, sebagai contoh saja, saya selaku penulis sebagai orang suku Makassar kemudian berbicara di ruang publik atau forum tertentu yang dihadiri oleh orang-orang Makassar sendiri, maka kata “iye” meskipun sama maknanya dengan kata “iya”—apa lagi dalam perspektif kecerdasan intelektual atau sesuai ejaan baku kata “iya” itu lebih tepat—tetapi posisi “iye” jauh lebih tinggi, lebih sopan, dan lebih memuliakan. Kemuliaan dan keutamaan kata “iye” dalam konteks bugis Makassar itu lebih penting ditinjau dari perspektif kecerdasan emosional dan spiritual.
Dalam bulan Ramadan ini, ada satu kejadian yakni pengiriman “Kepala babi” ke kantor Tempo dan publik pada umumnya memaknainya sebagai teror yang berpotensi mengancam kebebasan pers. Idealnya pejabat negara yang merespon kejadian tersebut—meskipun mungkin dengan bercanda, jika memperhatikan pola dan etika komunikasi—tidak boleh mengatakan “Dimasak saja”. Bahasa ini, jika itu pun kesannya bercanda, itu tidak etis dalam pola komunikasi seorang pejabat negara, karena sesungguhnya (minimal) itu terkait dengan posisi dirinya yang semestinya harus memahami bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, termasuk kebebasan pers sebagai bagian dari pilar demokrasi.
Saya sering membaca di media sosial tetapi sumbernya bisa dinilai otoritatif dan kredibel, masih sering kali ada oknum pejabat yang tidak menyadari posisinya sehingga pilihan-pilihan diksi dalam komunikasi publiknya mencerminkan niretika. Tidak mampu memancarkan rasa empati justru sebaliknya berpotensi besar menyakiti perasaan masyarakat atau rakyat.
Tulisan ini muara utamanya adalah pada harapan, jika kita merasa sebagai figur publik maka kita sesungguhnya memiliki tanggung jawab sosial dan moral yang besar. Oleh karena itu pola komunikasi kita harus memancarkan etika, empati atau kepedulian, asertif, dan keteladanan. Kita pun harus selalu memiliki komitmen, bahwa segala sikap, tindakan, dan pola komunikasi yang ditampakkan harus berimplikasi positif pada upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Figur publik memang idealnya, harus memiliki sensitivitas kepekaan perasaan atas perasaan, kebudayaan, dan kearifan orang lain atau suatu daerah.
Jadi, tulisan ini memang sedang tidak diniatkan untuk menjelaskan teori etika komunikasi secara detail dan runut, hanya menyentuh beberapa poin penting yang dipandang sangat penting relasinya posisi seorang figur publik. Sahabat pembaca pun bisa membaca tulisan saya yang lain dan relevan, Figur Publik, Sensitivitas, dan Tanggung Jawab Sosial.
*Pemilik Pustaka “Cahaya Inspirasi”, Wakil Ketua MPI PD. Muhammadiyah Bantaeng, dan Pegiat Literasi Digital & Kebangsaan.