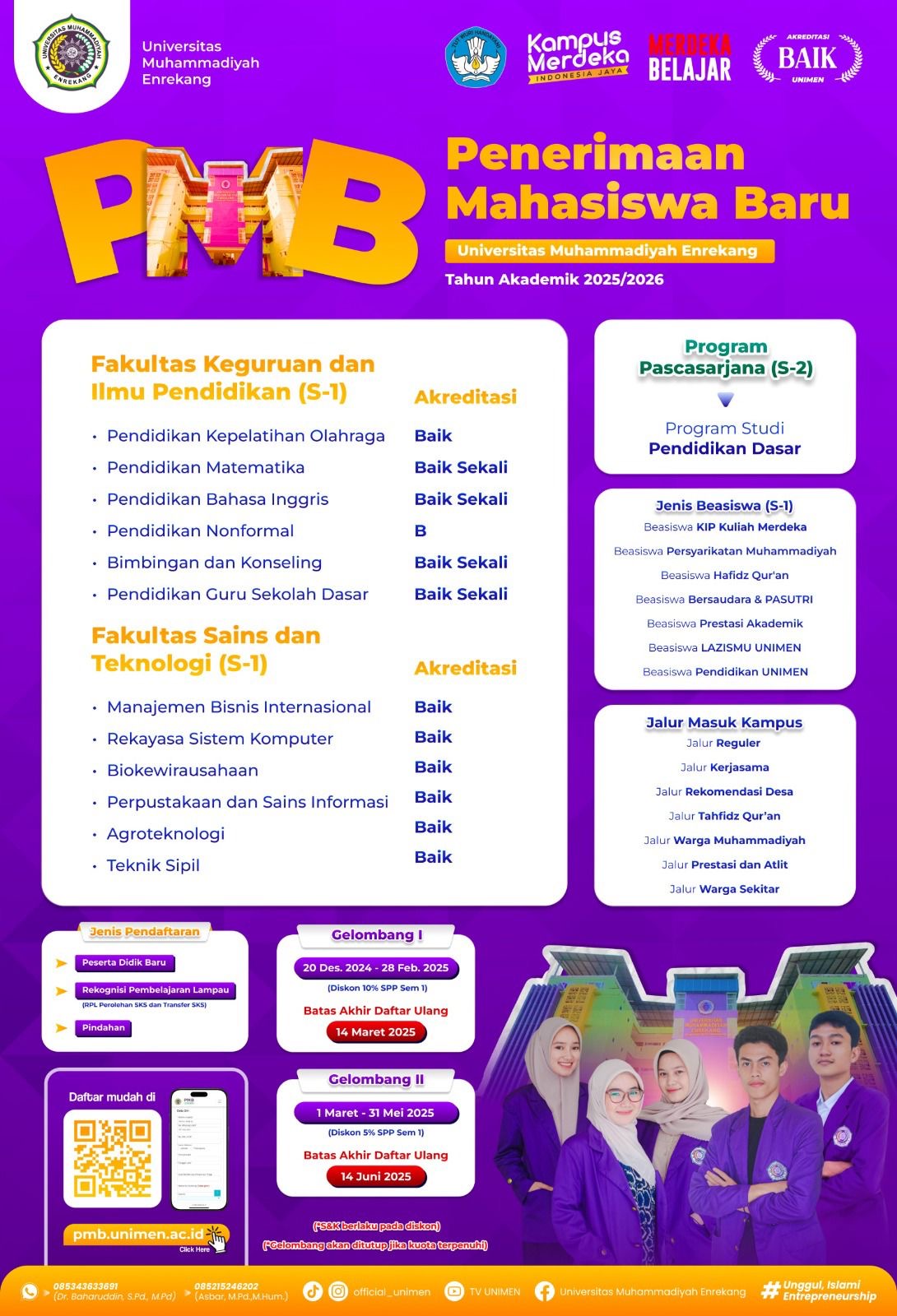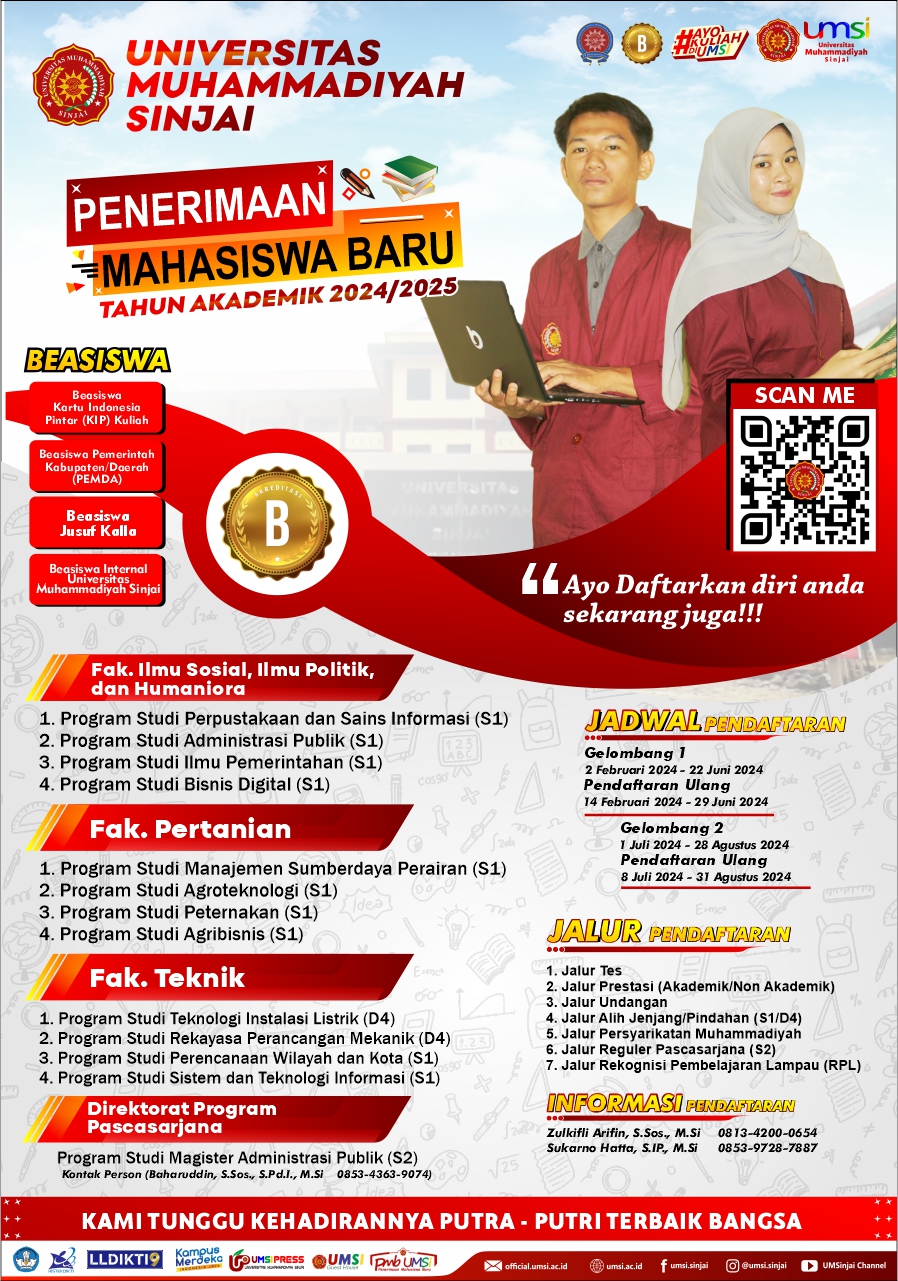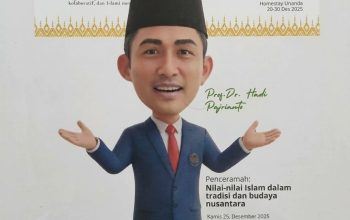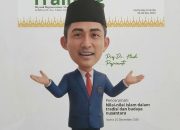Oleh: Agusliadi Massere*
KHITTAH. CO – Pada mulanya, manusia menaklukkan ruang dan waktu dengan kekuatan fisik-alamiah. Kita pernah mendengar cerita orang tua dan/atau kakek kita bahwa dirinya pernah menempuh perjalanan dengan jarak yang cukup jauh, misal Bantaeng-Makassar, hanya dengan berjalan kaki. Yang kaya, mungkin sudah menggunakan kuda. Belum ada kendaraan lain, ini adalah era praindustri.
Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, akhirnya ruang dan waktu ditaklukkan oleh kekuatan mekanik mesin. Bantaeng-Makassar, sebagai contoh, tidak lagi ditempuh dengan berjalan kaki atau menggunakan kuda. Sudah tersedia kendaraan seperti mobil, lintas pulau pun sudah ada kapal dan pesawat. Inilah yang disebut era industri.
Hari ini, sambil berbaring di kamar atau lagi asyik menyantap sarapan pagi, kita bisa melihat suasana kota Jakarta dan kemajuan bangsa-bangsa dan negara lain hanya dengan bermodal perangkat digital yang ada dalam genggaman. Bahkan, kita bisa melakukan transaksi jual beli, begitu pun mengikuti meeting dengan kolega bisnis lintas pulau atau provinsi dan lintas negara pun tanpa perlu ke mana-mana, cukup duduk manis di ruang tamu atau meja kerja yang tersedia di rumah. Hal ini terjadi, karena kini ruang dan waktu ditaklukkan oleh kekuatan elektromagnetik. Inilah yang disebut era digital. Yasraf Amir Piliang menyebutnya era pascaindustri.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah menimbulkan ledakan dahsyat sehingga lahir revolusi teknologi yang kini disebut dengan era digital. Ini adalah suatu keniscayaan yang arusnya tidak bisa dibendung, kita hanya bisa beradaptasi agar potensi kemanusiaan dahsyat yang ada dalam diri setiap manusia tidak tergerus atau terbawa arus negatif-destruktifnya.
Jika direnungkan, semua orang akan memahami bahwa era digital dengan teknologi digitalnya itu mengandung dua aspek yang paradoks. Satu sisi mengandung aspek positif-konstruktif, di mana secara umum teknologi menjanjikan, menjamin, dan menggaransi kemudahan-kemudaan serta efektivitas dan efesiensi dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas yang dihadapi. Sisi lainnnya, dan ini pun nyata, bahkan telah menimbulkan banyak korban, mengandung aspek negatif-destruktif. Aspek kedua ini, bahkan ada yang menggerus dimensi kemanusiaan dan/atau potensi dahsyat manusia yang dianugerahkan Allah Swt. sejak awal kelahirannya.
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak serta merta memberikan kemampuan kepada setiap orang untuk membaca dan merasakan dampak negatif dan destruktif yang ada. Apa lagi kita sering cepat terpesona dan larut di balik kenikmatan, kesenangan, dan kemudahan yang ada. Tanpa melakukan perenungan dan pendalaman dari setiap kemajuan yang ada atau yang sedang kita lakukan atau mengikutinya.
Akhirnya yang terjadi, diri kita seperti kisah dalam cerita katak yang binasa karena terlambat menyadari realitas sekitarnya atau tidak mengetahui bahwa air yang ditempati dirinya terjatuh ke dalamnya adalah air yang ada dalam panci yang akan direbus atau dimasak di kompor yang apinya sudah menyala. Katak mati karena terlambat menyadari keadaan atau realitasnya.
Tentu saja, kita tidak ingin mengalami hal seperti kisah katak dalam cerita itu. Meskipun dalam konteks kehidupan manusia makna “mati” dalam kisah katak tersebut bukanlah dalam makna “meninggal dunia” di mana ruh terpisah dari jasad. Tetapi, bisa saja yang mati adalah semangat belajar, kemampuan berpikir terutama berpikir kritis, kepedulian mati, kasih sayang redup, dan berbagai dimensi psikoligis dan kemanusiaan semakin terkikis dan tumpul akibat keintiman dalam interaksi dengan perangkat digital.
Dalam kondisi, keadaan, realitas, dan fenomena seperti inilah, penegasan dan pesan dahsyat Rhenald Kasali (2019) menemukan ruang urgensi dan relevansinya. Saya membaca buku Disruption, Rhenald Kasali menegaskan hari ini tidak cukup dengan “motivasi”. Tentu saja maksudnya bahwa untuk kesuksesan dan perubahan tidak cukup dengan hanya bermodalkan “motivasi”.
Kata “tidak cukup” bukan berarti bahwa tidak penting atau tidak berguna. Saya meyakini, motivasi masih akan selalu sangat penting dan berguna, terutama—jika kita memahami pandangan Bobby Deporter & Mike Hernacki, penulis buku Quantum Learning—“Bisa membangkitkan kedahsyatan fungsi otak”.
Menurut Rhenald, hari ini dibutuhkan pula kemampuan membaca dua hal: Where we are (Di mana kita) dan Where we are going to (Mau ke mana kita). Saya sangat memahami dari buku Disruption tersebut bahwa penegasan Rhenald jika harus dijawab, jawabannya bukanlah semata terkait letak geografis dan menunjukkan ruang terbatas. Jawaban “di mana” di sini penekanannya sangat luas, bahkan dalam pandangan saya, ini harus melingkupi jawaban filosofis, ideologis, psikologis, sosiologis, antropologis, dan teologis.
Jawaban teknologisnya pun, jika ada, tidak boleh murni bersifat teknis, mekanik, dan elektromagnetik. Mengapa? Sebagaimana yang diungkap oleh Prof. Mujiburrahman, Rektor UIN Antasari Banjarmasin, “Jika ditinjau secara ilmiah, selain teknologi, para pembuat aplikasi itu menerapkan psikologi dan antropologi untuk mengikat pengguna”.
Intinya, menurut Rhenald, adalah “membaca”. Dalam konteks yang lebih luas cakupannya maka di sinilah urgensi dan signifikansi dari “literasi”. Salah satu makna literasi adalah “membaca” termasuk bagaimana menerima, memahami, mengelola, dan menggunakan kembali informasi yang diterima, itu pun adalah literasi, yang bisa disebut sebagai literasi digital sebagai bagian satu dari enam yang dimaknai sebagai literasi dasar. Literasi dalam konteks Islam memiliki basis teologis yang kuat, yaitu perintah pertama dan utama dari ajaran Islam adalah “Iqra”. Bagi saya posisi atau level iqra jauh di atas literasi karena di dalam iqra wajib bismi rabbika.
Sebagaimana yang telah terungkap di atas, terutama terkait dampak teknologi yang bukan hanya positif dan konstruktif, tetapi termasuk pula negatif dan destruktif, bahkan terkait dampak buruk ini telah nyata dalam realitas kehidupan, maka di sinilah pentingnya “literasi digital”. Dan, literasi digital ini pun bukan sekadar pengetahuan yang bersifat informasi, sejatinya harus terbangun sebagai budaya yang mewarnai dinamika kehidupan sehari-hari, terutama dalam pemanfaatan teknologi digital khususnya di dunia virtual, tanpa kecuali dalam bermedia sosial.
Saya sangat menyadari bahwa lingkup pembahasan literasi digital itu sangat luas. Olehnya itu, saya dalam mengulas materi ini baik untuk dalam tulisan ini, hanya memilih beberapa poin saja. Begitu pun, ketika saya diundang menjadi narasumber di kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMK Negeri 1 Bantaeng, saya hanya membahas hal yang sangat relevan dengan dunia pelajar.
Kaitan antara literasi digital di era digital, saya ingin mengungkap satu fenomena bahwa hari ini banyak di antara kita menghabiskan waktunya di dunia virtual, bahkan ada yang telah mengalami kecanduan. Selain itu, ada pula kecenderungan yang tampak bahwa dalam menghabiskan waktu di dunia virtual diiringi pula oleh fenomena di mana kesadaran kritis dikalahkan oleh hamburan opini dan emosi. Merujuk pandangan Bernando J. Sujibto (2018), saya memahami dan terkonfirmasi pun dalam realitas dunia virtual melalui media sosial “Dunia virtual didominasi pengelolaan isu yang memanfaatkan emosi dan opini daripada kesadaran faktual yang berpijak pada ilmu pengetahuan”.
Dalam jangka waktu tertentu terutama dalam jangka waktu panjang, tentu saja kondisi di atas akan sangat berbahaya, menimbulkan dampak negatif-destruktif. Sebab, kita harus memahami bahwa dalam dunia digital pun tanpa kecuali dalam pemanfaatan media sosial, ada dua hukum dan prinsip yang bekerja dan ini memberikan implikasi nyata dan besar terhadap setiap orang yang terlibat di dalamnya: “algoritma” dan “habits”.
Hukum atau mekanisme kerja algoritma yang bekerja dalam dunia digital akan melahirkan kecenderungan, kondisi terparahnya adalah kecanduan terhadap suatu hal. Kecenderungan ini pun akan membentuk pola komunikasi dan informasi yang akan mengitari orang-orang yang berselancar di dunia virtual. Dan, ternyata algoritma ini pun, mekanisme kerjanya bukan hanya terjadi dalam teknologi yang digunakan oleh seseorang, tetapi termasuk beroperasi dalam diri penggunanya.
Algoritma yang juga bekerja dalam diri seseorang yang relevan dengan algoritma dalam teknologi digital yang sering digunakannya akan memengaruhi sikap dan tindakan seseorang. Hal ini pun diperkuat oleh hukum habits (kebiasaan) sebagai salah satu sunnatullah yang Allah ciptakan di muka bumi dan dalam diri manusia, sehingga akan berpotensi terbentuk sebagai kebiasaan, yang cepat atau lambat akan menjadi karakter. Dalam capaian posisi inilah, nalar pun akan ikut dipengaruhi.
Bahasa sederhananya adalah ketika, sebagai contoh saja, kita sering mengakses konten atau reels satu menit atau yang lebih lama 1,5 menit melalui Facebook Pro (baca: Profesional) yang kini membuat banyak orang yang menamai dirinya content creator (kreator konten) mengalami “kecanduan” terhadapnya, secara algoritmik di media sosialnya, konten sejenis itu akan sering muncul. Kemudian secara algoritmik dalam diri dan diperkuat oleh hukum habits yang melekat pula dalam diri, maka kelak—dan ini potensinya sangat besar—karakter kita akan terbentuk untuk hanya menyukai (khususnya di dunia nyata) ceramah-ceramah singkat saja. Kelak, kita akan bosan mengikuti ceramah yang berdurasi panjang atau lama.
Hal di atas kurang disadari karena lemahnya literasi digital, dan kita rabun dalam membaca dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut, karena kesadaran dan pikiran kritis kita sudah lumpuh, yang penyebabnya selain karena literasi yang rendah termasuk pula karena kita sudah tergoda dan larut dalam kenyamanan dan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia digital.
Sama halnya, godaan dahsyat penggunaan atau pemanfaatan ChatGPT sebagai salah satu anak kandung dari artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan (KB), fungsionalitasnya telah melampaui dari batas kewajaran sebagai “asisten”. Kini semakin menggerus, melumpuhkan, dan bahkan mematikan potensi dahsyat manusia yang telah menjadi anugerah terbesar dari Allah sejak awal kelahirannya, salah satunya “akal” atau “pikiran” dan “otak” sebagai hardware-nya.
Banyak sosok pelajar, tanpa kecuali pengajar yang sejatinya menjadi garda terdapat dalam merawat potensi vital manusia (baca: pikiran dan otak) yang menjadi tools strategis dalam membangun peradaban, kini bisa disimpulkan sedang ramai-ramai melumpuhkan dan membunuhnya. Kesimpulan saya ini, tentu saja dengan alasan yang jelas: kini mereka banyak yang memiliki ketergantungan penuh terhadap kecanggihan AI itu dalam menyelesaikan tugas dan beban kerjanya, dan jarang lagi menggunakan otaknya untuk berpikir.
Apa lagi pelajar, yang semestinya segala harapan tanpa kecuali kemajuan peradaban diletakkan dan dilekatkan terhadapnya, sudah semakin tergoda pula dengan kecanggihan AI. Padahal, seumuran mereka sejatinya harus terus menumbuhkan dan merawat kemampuan otaknya dalam berpikir agar dengan otak yang terus terasah akan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran baru demi membangun peradaban yang lebih baik di masa yang akan datang. Guru pun demikian, sejatinya dirinya harus menjadi teladan dalam merawat dan terus mengasah kemampuan otak dan kemampuan berpikirnya.
Kita harus selalu ingat bahwa dalam hidup dan kehidupan kita, tanpa kecuali dalam relasi keberadaan kita dengan perangkat digital atau teknologi digital di dunia digital, itu ada dua hukum dan prinsip yang terus eksis, bekerja, dan memberikan implikasi besar dan nyata: yaitu algoritma dan habits.
Artinya pelajar dan guru pun akan tunduk pada dua hukum dan prinsip di atas (baca: algoritma dan habits) artinya, ketika dirinya sudah menggantungkan atau menyerahkan sepenuhnya segala pekerjaan dan tugasnya pada perangkat digital dan jarang lagi menggunakan potensi dahsyat yang telah built-in dalam dirinya, maka implikasinya pun akan sesuai dengan kebiasaan atau kecenderungannya ini.
Dari berbagai persoalan sebagai fenomena nyata hari ini terkait dampak negatif dan destruktif dari teknologi digital termasuk kecanggihan AI, sehingga dalam suatu kesempatan Prof. Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, menyampaikan “AI bukan hanya membuat manusia semakin cerdas dan bijak, justru semakin culas”.
Sekali lagi, pembahasan tentang teknologi digital memiliki cakupan yang sangat luas, tentu saja apa yang saya uraikan di atas, hanya bagian terkecil, tetapi saya merasa itu penting. Oleh karena itu, sejatinya memang tema-tema “literasi digital” terus dibahas dan didiskusikan bukan hanya pada saat pelaksanaan MPLS yang sasarannya untuk siswa baru dan itu pun hanya satu, dua jam tanpa ada follow-up-nya. Literasi digital memang harus dibangun menjadi “budaya” agar segala dinamika kehidupan kita khususnya di media sosial dan pemanfaatan teknologi digital memberikan banyak manfaat, tetap menjunjung etika, mengedepankan pikiran dan kesadaran kritis, mengedepankan dasar ilmu pengetahuan yang utuh, dan tanpa menggerus potensi dahsyat yang ada dalam diri.
*Pemilik Pustaka “Cahaya Inspirasi”, Wakil Ketua MPI PD. Muhammadiyah Bantaeng, dan Redaktur Opini Khittah.co