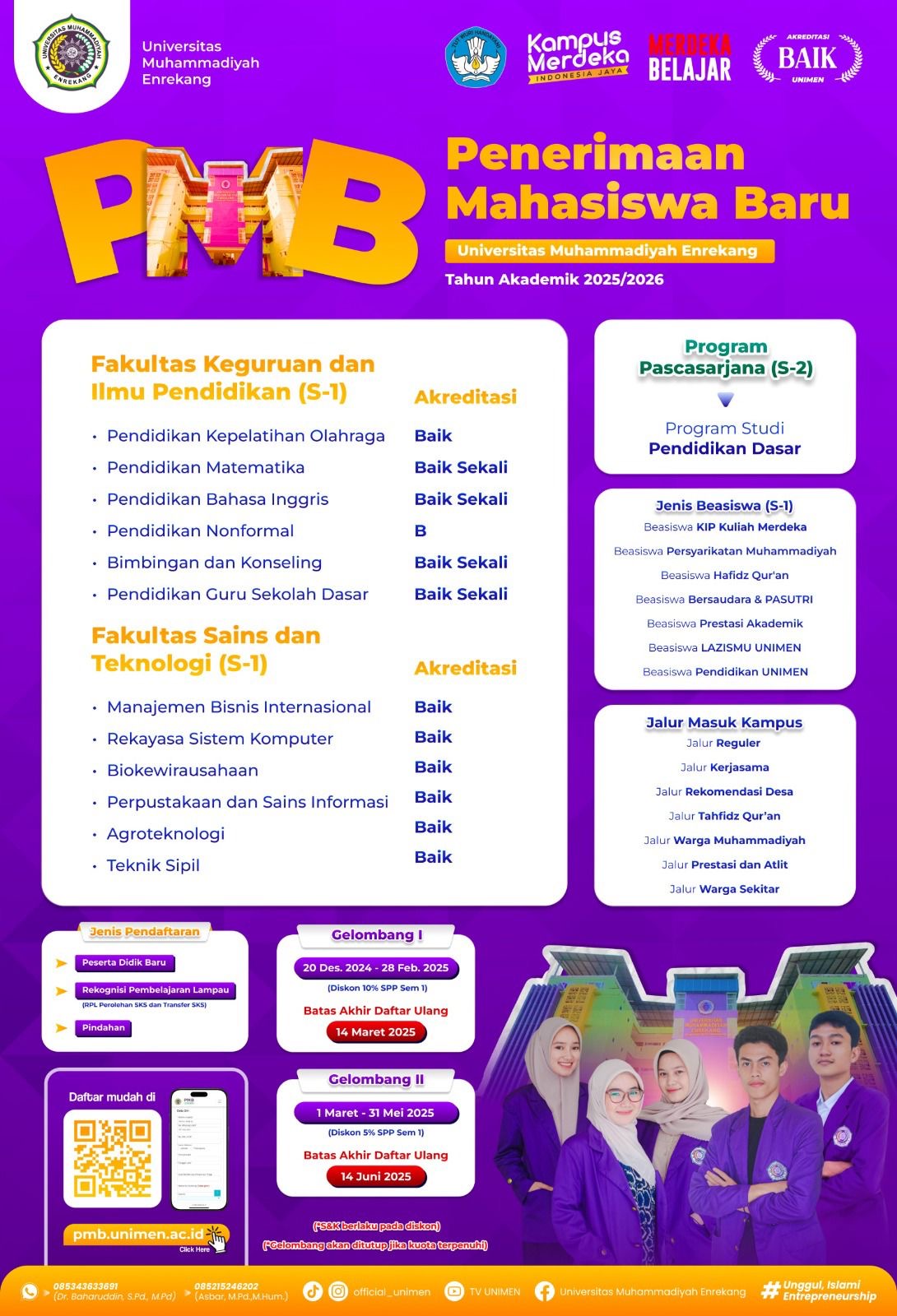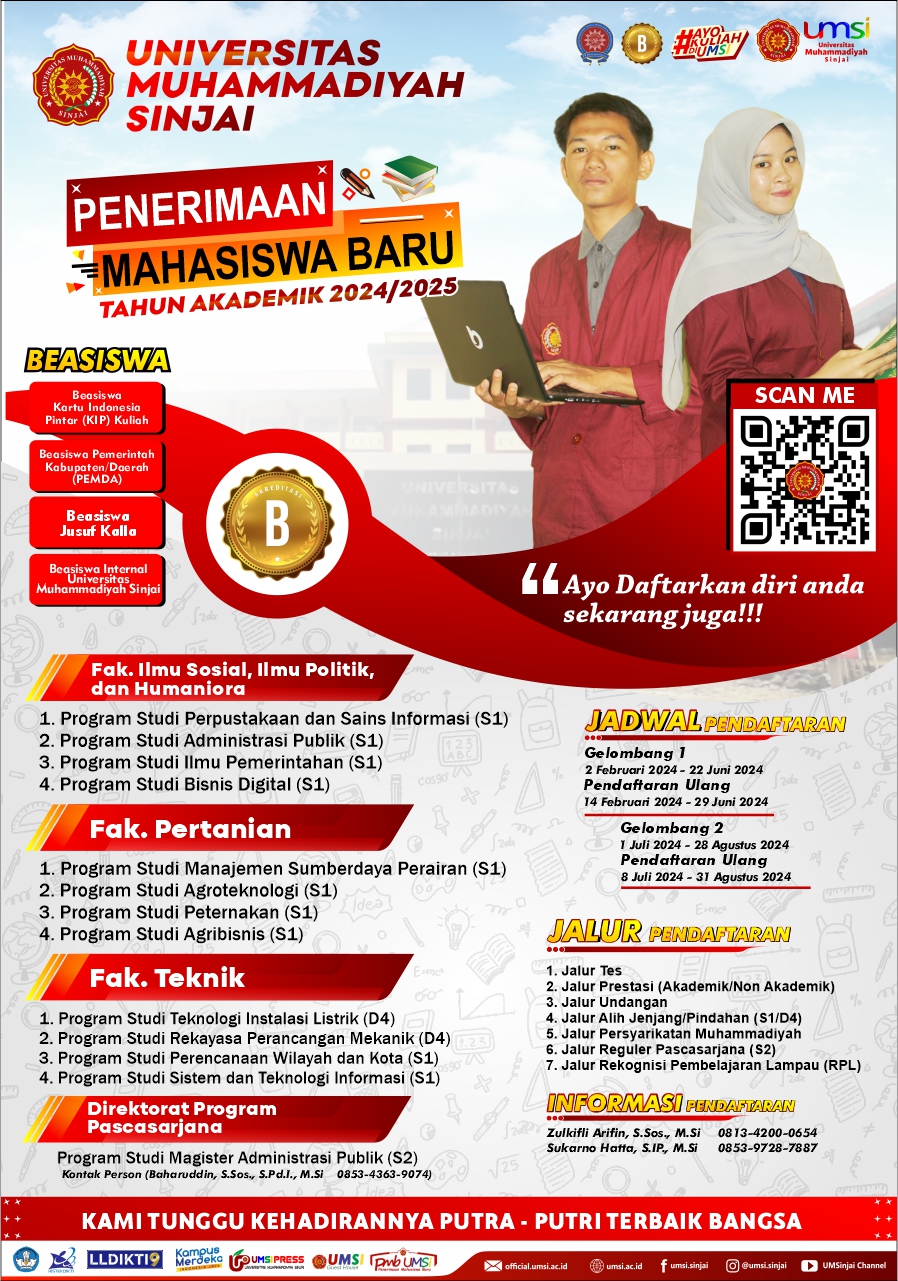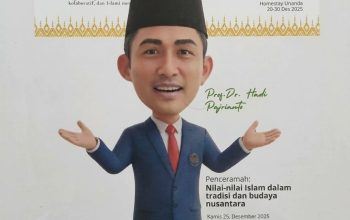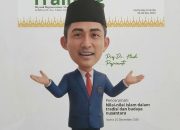Oleh: Agusliadi Massere*
KHITTAH. CO – Memperhatikan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang masih menyisakan banyak PR (baca: Pekerjaan rumah) untuk diselesaikan, meskipun telah banyak langkah preventif dan preemtif yang telah ditempuh, bahkan yang represif pun telah ada yang melakukannya, mungkin waktunya telah tiba, kita kembali ke hati. Merujuk pada lirik lagu Aa Gym—sapaan akrab dari Kiai Kondang H. Abdullah Gymnastiar—Jagalah Hati, hati adalah “Lentera hidup” dan “Cahaya ilahi”.
Jika kita fokus pada cara pandang penyelesaian masalah dari Aa Gym, intinya bisa disimpulkan adalah kembali ke hati. Aa Gym fokus pada manajemen qalbu untuk menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi, termasuk oleh bangsa dan negara ini, Indonesia. Jika saya tidak salah mengingat—meskipun hati tidak persis sama dengan jiwa—Prof. Haedar Nashir di antara buku-buku dan tulisan karyanya, ada satu tulisannya yang menegaskan pentingnya mengaktualisasikan pesan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dalam hal ini “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya”. Artinya membangun jiwa adalah prioritas utama, kemudian barulah badannya. Saya menyebutnya membangun hati, menjaga hati, dan terutama menyucikan hati.
Selain itu, sambil membaca buku karya Emha Ainun Nadjib (yang akrab disapa Cak Nun), Berserahlah Biarkan Allah Mengurus Hidupmu, saya menemukan tiga diksi yang saya ramu menjadi judul tulisan ini: “Sekolah”, “Fakultas hati” (termasuk disebut fakultas perasaan), dan “Stunting spiritual”. Dan, Cak Nun pun memberikan poin utama dan prioritas terhadap pentingnya hati dan perasaan serta digambarkan pula, bahwa kita sedang mengalami stunting spiritual. Hanya disayangkan oleh Cak Nun, tidak ada sekolah yang menyiapkan fakultas hati dan fakultas perasaan.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun ada yang menarik, relevan, strategis, dan penting untuk diberikan porsi perhatian, pemahaman, dan kesadaran yang besar dan tinggi. Yang dimaksud adalah bunyi—termasuk nilai dan makna—dari Pasal 31 ayat (3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.
Dari pasal tersebut di atas, kita bisa mendapatkan pemahaman dan kesadaran mendalam, bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa pun harus berbasis pada hati. Mengapa? Karena pembicaraan dan upaya perwujudan peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak, itu berada dalam “Fakultas hati”. Jika kita membaca utuh konstitusi negara Indonesia, sebenarnya ada banyak poin, yang secara langsung maupun tidak langsung bisa dipahami bahwa substansi penegasannya ada pada “hati” atau berada dalam fakultas hati.
“Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur…” Penggalan alinea ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945 ini pun, menegaskan sesuatu (baca: keinginan luhur) yang berada dalam mekanisme kerja hati. Begitu pun sila dan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila jika ditarik garis derivasi dan dibawa dalam pemaknaan mendalam maka lebih banyak porsinya yang harus dirujuk pada hati.
Sebagai bangsa Indonesia, yang sebagian besar penduduknya adalah umat Islam, tentunya tidak keliru jika merujuk pula pada sejarah kenabian. Di antara catatan sejarah tersebut, Rasulullah Muhammad Saw sepulang dari perang Badar, perang yang sangat besar dan dahsyat, pernah pula menegaskan, bahwa perang terbesar setelah ini adalah “Perang melawan hawa nafsu”. Hawa nafsu ini, bisa mendominasi hati, ketika hati tidak dijaga sesuai fitrah sejatinya, yang telah terikat dengan janji dan komitmen suci dengan Allah Swt.
Dari sekian banyak catatan dan referensi di atas, menegaskan betapa pentingnya hati sebagai—di antaranya—lentera dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Sayangnya, jika kita ingin jujur mengakui, Indonesia dalam praktiknya masih jauh dari posisi untuk memberikan porsi perhatian yang serius dan besar terhadap bagaimana mendirikan fakultas hati untuk menjaga hati sebagai cahaya ilahi yang akan menuntun dan mengendalikan segala sikap, tindakan, dan keputusan-keputusan serta kebijakan yang dilahirkan dalam kehidupan, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan terutama dalam bernegara.
Sehingga, Indonesia sebagai bangsa dan negara yang kaya raya; fondasi tempat bangunan keindonesiaannya didirikan pun, sejatinya itu adalah sesuatu yang sangat kokoh; namun, ada penampakan realitas yang sangat paradoks. Data statistik dan fakta lapangan tentang kemiskinan masih sangat tinggi, tingkat korupsi mencapai taraf “tergila”, berbagai pelanggaran dan penyimpangan mewarnai kehidupan demokrasi. Kepalsuan demi kepalsuan diproduksi demi kepentingan pribadi dan merugikan kehidupan kolektif secara umum. Begitu pun moralitas dan etika menjadi barang langka dan asing bagi orang-orang yang telah mendapatkan amanah mulia, besar, dan strategis dari negara dan rakyat.
Ini semua, sekali lagi karena hati sedang dilupakan. Hati dikotori. Itulah sebabnya baris pertama dari alinea pertama lagu Aa Gym Jagalah Hati, berlirik “Jagalah hati jangan kau kotori”. Ketika hati kotor, maka dipastikan empati dan semangat membangun kemajuan yang berbasis kemanusiaan dan keadilan jadi kering dan layu. Justru, hati yang kotor menjadi lahan subur bagi the love of power (cinta kekuasaan) yang telah menimbulkan banyak kerusakan di muka bumi tanpa kecuali dalam kehidupan demokrasi dan perpolitikan Indonesia.
Kita mungkin kembali bertanya sekali lagi. Mengapa harus dengan hati? Terkait ini, kita pun harus menegaskan jika kita merenungi secara mendalam, maka kita hanya menemukan dua fungsi sejati hati: pertama, mengajak diri kita kepada kebaikan; dan kedua, mencegah diri kita dari keburukan. Intinya semua tentang yang positif, produktif, konstruktif, bermanfaat, dan berorientasi masa depan. Hati sesungguhnya akan menjadi penentu, apakah diri kita baik atau buruk. Tetapi yang menjadi penentu buruk itu, bukanlah hati yang sebenarnya, itu adalah hati yang kotor dan/atau dikotori.
Dalam buku Ary Ginanjar Agustian, buku keduanya, Rahasia Sukses Membangkitkan ESQ Power: Sebuah Inner Journey Melalui Al-Ihsan, terungkap hasil survey yang luar biasa. Hasil survey tersebut terkait Peringkat Karakter CEO Ideal yang berasal dari enam benua: Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Eropa, dan Australia. Survey ini dilakukan selama tiga kali, yaitu pada tahun 1987, 1995, dan tahun 2002 oleh lembaga leadership internasional yang bernama “The Leadership Challenge”. Lembaga ini menghasilkan data hasil survey dengan poin tertinggi selama tiga kali itu, menempatkan karakter honest (jujur) pada peringkat pertama. Jujur itu berada dalam fakultas hati. Jujur adalah hasil mekanisme kerja hati.
Sama halnya ketika bangsa dan negara kita, Indonesia, telah memiliki banyak hal, mulai dari fondasi kebangsaan, sumber daya alam yang kaya raya, penduduk dan sumber daya manusia, dalam hal intelektualitas sangat mumpuni, tetapi masih menyisakan banyak persoalan dan PR, itu karena kita masih bersoal dalam urusan honest (sikap dan tindakan jujur) ketika mendapatkan amanah. Kejujuran masih menjadi barang langka dan asing di negeri kita ini. Padahal, bagi CEO Perusahaan besar dunia, persoalan kejujuran itu adalah karakter utama yang mereka implementasikan dalam menjalankan perusahaannya.
Selain kejujuran, persoalan utama kita adalah hilangnya empati dan/atau kepedulian, bukan hanya dalam makna sempit yang terkesan hanya dibutuhkan pada saat ada bencana dan musibah kemanusiaan, tetapi ketika korupsi semakin menggila maka itu juga bermakna hilangnya empati dalam diri para pelakunya. Ini pun menegaskan bahwa hati itu sedang kotor.
Kita pun memahami bersama, bahwa dalam hidup dan kehidupan ini, bukan hanya ada kecerdasan intelektual, yang kesannya berada dalam otak, tetapi termasuk ada kecerdasan emosional dan spiritualitas yang bersentuhan dengna hati, tentu termasuk dalam kajian tertentu termasuk dengan otak kanan. Ketiga kecerdasan ini harus mampu diseimbangkan dalam hidup dan kehidupan.
Begitu pun, kita mengenal bahwa kerja itu bukan hanya dengan kerja keras yang basisnya pada kekuatan fisik-biologis. Namun, ada pula yang disebut dan itu sangat penting adalah kerja cerdas dan kerja ikhlas. Yang terakhir ini, kerja ikhlas, tentu saja itu berada dalam zona dan/atau fakultas hati. Jika kita merujuk pada buku Kubik Leadership karya Jamil Azzaini, dan kawan-kawan, kita—sebagaimana yang saya temukan—akan menemukan pemahaman dan kesadaran betapa tingginya dan dahsyatnya efek daripada kerja ikhlas ketimbang kerja cerdas dan kerja keras.
Bahkan Ary Ginanjar, di antara uraian-uraiannya dari kedua buku dahsyatnya yang mengulas secara umum tentang kecerdasan emosional dan spiritual, kita bisa menemukan pula bukti-bukti nyata bagaimana kerja ikhlas itu telah memberikan pengaruh besar bagi perusahaan-perusahaan besar dunia. Bahkan ada satu perusahaan yang dilukiskannya, awal perjuangannya, para karyawan dan manajer itu bekerja dengan penuh ikhlas selama berbulan-bulan tidak digaji, padahal di tempat lain, mereka berpotensi digaji dengan gaji yang sangat besar.
Lalu bagaimana dengan sekolah yang peduli dengan fakultas hati dan fakultas perasaan itu. Untuk dipahami atau minimal sebagai tambahan pengetahuan, bahwa perasaan itu adalah software yang berada dalam hati sebagai hardware. Sejatinya negara atau pemerintah dalam hal ini secara serius menerjemahkan secara mendalam dan mewujudkannya secara kelembagaan dengan indikator yang sangat nyata dan jelas implikasinya, terutama ketika output dan terutama outcome dari sekolah itu telah menjadi pejabat negara yang akan mengurusi dan menentukan nasib rakyat.
Pemerintah memiliki kewajiban dalam upaya “Mencerdaskan kehidupan bangsa” dan tidak boleh lupa bahwa dimensi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia adalah indikator wajib yang harus melekat di dalamnya. Karena ini berproses dalam institusi yang salah satunya bernama sekolah, maka idealnya itu menjadi karakter bagi anak negeri, kemudian akan memengaruhi kepemimpinan ketika mereka semua menjadi pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan negara di masa yang akan datang.
Ketika hari ini masih banyak yang korupsi, itu berarti negara dan pemerintah masih gagal mewujudkan Pasal 31 ayat (3). Namun, bagi saya, ini adalah tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah, meskipun tentunya peran yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat masing-masing sesuai kemampuan saja, seperti saya pribadi hanya bisa menyuarakan secara terus menerus melalui tulisan serta melalui forum perkaderan dan LDK.
Ada hal sederhana yang harus diperhatikan pula oleh sekolah dalam makna institusi formal. Bahwa budaya nyontek ketika menghadapi ujian atau ketika diberikan tugas tertentu yang bermaksud mengukur kemampuan siswa, maka hal-hal yang mencerminkan ketidakjujuran dalam proses penyelesaiannya, itu perlu “diperangi” secara serius. Ingat, ketidakjujuran itu berpotensi menjadi karakter dan akan mengotori hati.
Pesantren bisa menjadi ruang untuk memberikan perhatian besar terhadap fakultas hati dan fakultas perasaan tersebut. Sekolah umum dan swasta pun—selain pesantren—tentunya bisa merumuskan bagaimana membangun fakultas hati dan fakultas perasaan yang berimplikasi besar bagi masa depan Indonesia yang lebih berkemajuan, berkemanusiaan, dan berkeadilan.
Ketika berbagai program dan kegiatan dilakukan dengan dukungan anggaran yang maksimal di berbagai daerah untuk menangani stunting terhadap pertumbuhan anak yang mengalami kekurangan gizi, tentunya ini bersentuhan langsung pada fisik-biologis. Maka, sejatinya terhadap stunting spiritual pun perlu lagi dirumuskan secara serius program dan kegiatan yang tepat.
*Pemilik Pustaka “Cahaya Inpsirasi”, Wakil Ketua MPI PD. Muhammadiyah Bantaeng, dan Pegiat Literasi Digital & Kebangsaan.