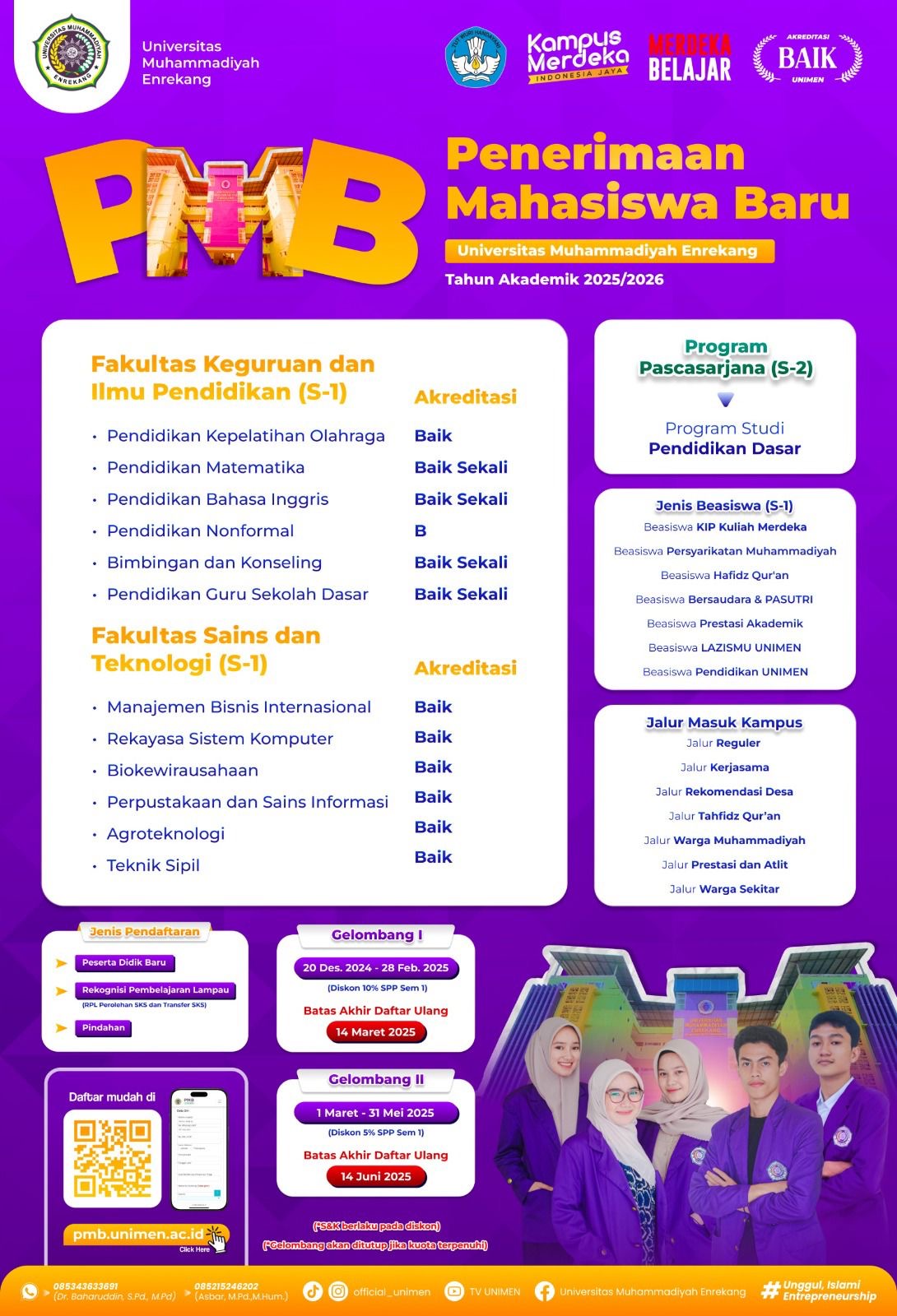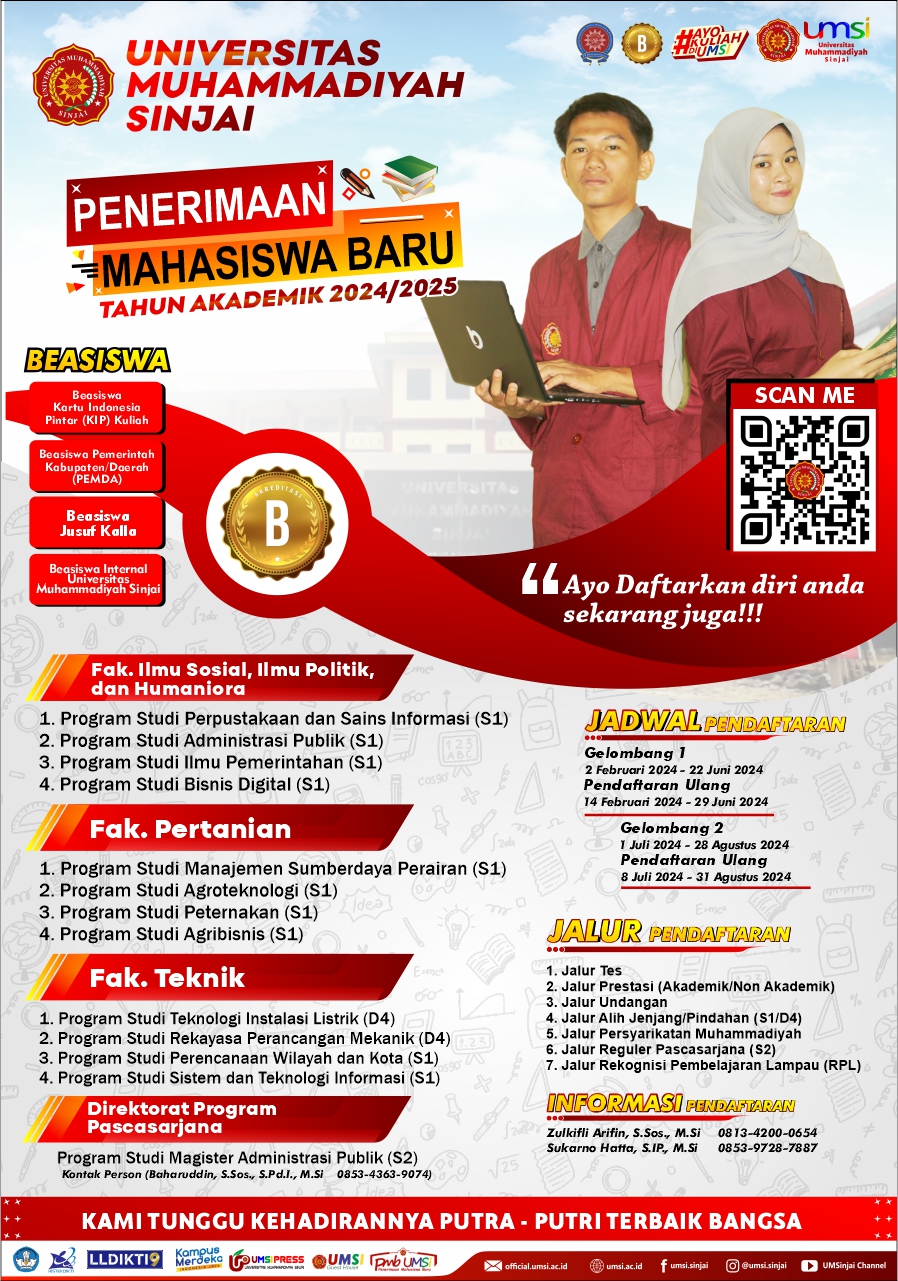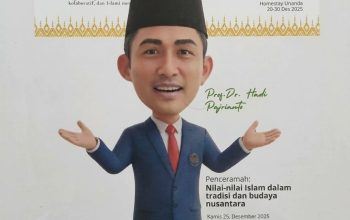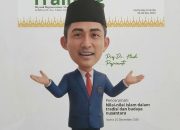Oleh: Agusliadi Massere*
KHITTAH. CO – Dua puluh tahun lagi, Indonesia akan memasuki masa keemasan kemerdekaannya. Tahun 2045 inilah yang dimaknai sebagai Indonesia Emas 2045 karena pada saat itu Indonesia telah mencapai rentang waktu seratus tahun kemerdekaannya. Makna sederhana Indonesia Emas 2045 ini tentu saja benar dan kita semua sepakat. Hanya saja, saya pribadi menaruh harapan dan pandangan utama agar Indonesia Emas 2045 itu tidak dipahami sesederhana itu.
Indonesia Emas 2045 dalam pandangan saya harus dimaknai secara filosofis, ideologis, politik, ekonomi, sosial, dan psikologis yang bermuara pada indikator kemajuan, kegemilangan, kecemerlangan, kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, kebahagiaan, kedaulatan, keadaban, dan kemuliaan dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau, jika saya meminjam pandangan Muhammadiyah, maka Indonesia Emas 2045 yang saya maksud selaras dengan makna Indonesia Berkemajuan yang dikonstruksi oleh Muhammadiyah, yaitu “Negara utama (al-madinal al-fadhillah), negara berkemakmuran dan berkeadaban (umran), dan negara yang sejahtera. Negara yang mendorong terciptanya fungsi kerisalahan dan kerahmatan yang didukung sumber daya manusia yang cerdas, berkepribadian, dan berkeadaban mulia”. Kurang lebih seperti ini, gambaran dan makna Indonesia Emas 2045 yang terbayangkan dalam diri.
Harapan di atas bertumpu pada pandangan agar Indonesia Emas 2045 bukanlah parade kemajuan dan pencapaian semata dalam mengawali lintasan abad kedua kemerdekaannya. Sebagai sekadar parade kemajuan dan pencapaian, bisa saja awal mula melintasi abad kedua kemerdekaannya, Indonesia disambut dengan perayaan luar biasa, penuh pesta kembang api, diteriaki, disoraki dengan gemuruh dan meriah. Namun, yang namanya sekadar parade setelah itu dilupakan dan kembali berjalan seperti biasa tanpa ada pembeda yang menunjukkan makna “keemasan” tersebut.
Kita tentu saja berharap, Indonesia kelak dalam melintasi abad kedua kemerdekaannya bukan hanya meriah dan luar biasa pada awal memasuki pintu gerbang lintasan barunya itu, tetapi kita ingin sebagaimana indikator pencapaian multimakna di atas, itu terus mewarnai sepanjang masa abad keduanya minimal dalam melewati segala dinamika kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, peradaban, kemajuan, dan perubahan yang ada. Tentu saja, untuk mimpi besar dan mulia tersebut, kita berharap lahir generasi emas yang bisa terus mengiringi, menggerakkan, mengarahkan, dan mengendalikan dinamika yang ada agar cahaya “Emas” itu terus bersinar dalam mengarungi setiap langkah dan detik episode kehidupannya.
Siapakah generasi emas itu? Dalam pandangan saya setelah merenungkan secara mendalam, memikirkan berbagai spektrum nilai dan makna yang relevan, saya sampai pada kesimpulan bahwa sejatinya yang layak menjadi generasi emas adalah Generasi Z. Meskipun, kesimpulan ini belum titik sampai di sini, sebentar ada penegasan substansial Generasi Z yang seperti apa yang layak dinilai sebagai generasi emas.
Sebelum membocorkan Generasi Z yang saya maksud bisa menjadi generasi emas, saya akan terlebih dahulu mengungkapkan alasan sehingga pilihan saya jatuh pada generasi ini. Merujuk pada teori generasi Strauss-Howe (Subhan Setowara, dkk, 2018:1) generasi itu dibagi menjadi Generasi baby boom (1943-1960), Generasi X (1961-1981), Generasi Y atau milenial (1982-2004), dan Generasi Z (2005). Terbaru pun ada istilah Generasi alfa.
Berdasarkan kategorisasi Howe di atas, kita memahami bahwa Generasi Z itu lahir di tahun 2005. Berdasarkan ini, berarti Generasi Z untuk hari ini sedang berumur dua puluh tahun, atau kurang lebih dalam rentang usia ini. Usia seumuran ini, tentu saja adalah masa-masa keemasan, masih bisa dipandang sebagai umur keemasan relevansinya dengan peningkatan kapasitas dan kapabilitas generasi. Sebab, pada usia dua puluh tahunan ini, mereka masih bisa dipandang sebagai generasi pembelajar, masih masa-masa belajar atau fokus belajar. Meskipun, tentu saja tidak secara keseluruhan tetapi inilah ciri dan kondisi pada umumnya.
Selain itu, jika merujuk tahun kelahiran Generasi Z berdasarkan pandangan Howe di atas, kelak pada tahun 2045, Generasi Z ini akan berumur kurang lebih empat puluh tahun. Terinspirasi dari pengangkatan Muhammad Saw sebagai rasul Allah pada usia empat puluh tahun, berarti bisa mengandung makna bahwa umur empat puluh tahun sebenarnya adalah masa keemasan untuk diberikan tanggung jawab yang orientasi kemaslahatannya bukan hanya untuk dirinya semata tetapi untuk kehidupan yang lebih luas dan besar seperti untuk urusan bangsa dan negara.
Dari gambaran sekilas di atas, tampak dan terungkaplah dengan nyata dan jelas bahwa penentuan Generasi Z sebagai cikal bakal generasi emas itu telah melewati pertimbangan dan landasan filosofis yang cukup kuat dan mendalam. Meskipun demikian, saya pun tidak serta-merta mengandalkan Generasi Z tanpa ada upaya konstruksi nalar kebangsaan dalam dirinya. Artinya Generasi Z hanya bisa menjadi generasi emas ketika nalar kebangsaan terkonstruksi atau terbangun dalam dirinya.
Tanpa nalar kebangsaan yang terkonstruksi dengan baik dalam diri, Generasi Z pun berpotensi bukan sebagai generasi emas, tetapi justru sebagai generasi cemas atau yang dalam istilah Rhenald Kasali (2017) sebagai strawberry generation (generasi strawberry). Nalar kebangsaan adalah nalar yang terbentuk dan mengakar kuat dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, spirit NKRI dengan peta sosiologisnya yang identik dengan kebinekaan, dan berbagai nilai luhur bangsa tanpa kecuali nilai-nilai dan ajaran agama. Nalar pada dasarnya mampu memengaruhi dan mengendalikan segala sikap (baca: pikiran, perasaan, dan pemaknaan), tindakan, relasi, dan proses menjadi.
Mengapa nalar kebangsaan harus terkonstruksi terlebih dahulu dalam diri Generasi Z barulah bisa dipandang sebagai generasi emas. Ada sejumlah landasan filosofis, pandangan otoritatif, dan pijakan ilmiah yang bisa membenarkan kesimpulan tersebut.
Secara psikologis dipahami oleh semua psikolog bahwa dimensi psikologis secara hierarki posisinya lebih kuat dan pengaruhnya lebih besar ketimbang dimensi fisik-biologis yang ada dalam diri manusia. Dalam konteks kehidupan duniawi pun, pusat perubahan dan kemajuan adalah manusia. Salah satu yang bisa menjadi basis teologis dari posisi manusia dan terutama pada dimensi psikologisnya terungkap dari QS. Ar-Ra’d ayat 11 yang berbunyi “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”.
Berdasarkan ayat di atas dari beberapa kajian dan tafsir termasuk yang pernah saya dengar penjelasannya dari Ustad Adi Hidayat, bisa disimpulkan kembali yang memperkuat pandangan, bahwa perubahan dan kemajuan suatu bangsa dan negara diawali dengan perubahan dalam diri. Perubahan dalam diri di sini, tentu saja adalah perubahan dalam dimensi psikologis-spiritual (seperti pikiran/akal dan perasaan/kalbu). Tetapi tidak berhenti sampai di sini, termasuk input (bisa berupa ilmu pengetahuan, nilai, makna, dan lain-lain) yang akan berada dan beroperasi dalam dimensi psikologis-spiritualitas tersebut.
Dr Taufiq Pasiak pun mengungkapkan satu pandangan dari Rene Descartes yang sejalan dangan pandangan di atas “…Rene Descartes juga melihat adanya segi lain dari diri manusia, yakni jiwa yang kedudukannya lebih tinggi daripada tubuh” (2012:6). Kutipan pandangan Taufiq Pasiak dari Descartes ini, salah satunya bisa dipahami dan diperkuat dari pandangan Erbe Sentanu (2010: 7-12) yang membuat skema bahwa energi vibrasi dan quanta—sebagai bagian terdalam dari suatu benda apa pun—itu berada dalam medan tak tampak (Fisika Kuantum) sedangkan partikel, atom, molekul, dan benda, itu berada dalam medan tampak (Fisika Newton).
Skema Sentanu di atas pun disandingkan dengan apa yang ada dalam diri manusia bahwa perasaan dan pikiran berada dalam medan tak tampak (Fisika Kuantum) sedangkan tindakan, kebiasaan, karakter, dan nasib, itu berada dalam medan tampak (Fisika Newton). Salah satu kesimpulan yang bisa ditemukan dari skema yang dibuat oleh Sentanu ini, bahwa hal fisik bahkan realitas empirik bisa dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan, yang dalam penegasan saya di tulisan ini, adalah sesuatu yang berdimensi psikologis-spiritual.
Kajian yang lebih menarik yang bisa memperkuat pandangan yang diungkap oleh Pasiak dan Sentanu, itu dari Dr. Joe Dispenza (2021), “Pikiran-pikiran Anda memiliki konsekuensi yang sangat besar sehingga bisa menciptakan realitas Anda”. Selain itu ditegaskan pula, “Energi adalah struktur utama dari segala sesuatu yang material dan sangat responsif terhadap pikiran” (Dispenza, 2021: 38).
Dari pandangan Dispenza (2021: 46), kita pun bisa sampai pada kesimpulan bahwa dimensi psikologis-spiritual bukan hanya bisa memengaruhi dimensi fisik-biologis diri kita, termasuk dimensi material yang ada di luar diri manusia: “Pikiran dan materi sangat berkaitan. Kesadaran (pikiran) Anda memiliki efek terhadap energi (materi) karena kesadaran Anda cukup berdaya untuk memengaruhi materi karena di tingkat paling dasar, Anda adalah energi yang memiliki kesadaran.
Dari Dispenza pun, secara umum, saya bisa memahami dan menyadari bahwa dari diri manusia ada gelombang elektromagnetik yang sangat dahsyat yang bisa memengaruhi hal material tanpa kecuali yang berada di luar diri manusia. Gelombang elektromagnetik yang dimaksud adalah keselarasan energi listrik (elektrik) yang bersumber dari pikiran dan daya magnetis yang berasal dari perasaan.
Beberapa pandangan di atas, minimal sudah bisa memperkuat bahwa dimensi psikologis-spiritualitas manusia memiliki pengaruh yang kuat untuk memengaruhi dimensi lain baik fisik-biologis yang melekat pada diri manusia itu sendiri maupun hal material lain yang berada di luar diri manusia. Namun, bukan hanya itu, ada pula dan jumlahnya banyak referensi yang memperkuat bahwa sesuatu seperti pengetahuan, nilai, pandangan, ideologi, ajaran, makna, tanpa kecuali nilai agama, Pancasila, dan UUD NRI 1945 yang akan beroperasi dalam dimensi psikologis-spiritualitas manusia itu bisa memengaruhi manusia dalam hal tindakan, karakter, keputusan, dan kesimpulannya, termasuk yang disebut dengan nalar.
Dr. Asep Zaenal Ausop, M.Ag (2014: 3) menegaskan lima hal yang dapat berpengaruh bagi pembentukan karakter—meskipun konteks yang disebutnya ini adalah dalam lingkup pendidikan. Lima hal atau faktor tersebut adalah: (1) Corak nilai yang ditanamkan. Seseorang bisa dicuci otaknya dan diubah orientasi hidupnya dengan nilai-nilai baru yang didoktrinkan; (2) Keteladanan sang idola; (3) Pembiasaan. Pepatah mengingatkan bahwa “bisa itu karena biasa”; (4) Ganjaran dan hukuman; dan (5) Kebutuhan. Kebutuhan dan perasaan tertekan akan bisa mengubah orientasi hidup seseorang. Dari lima pandangan Asep ini, tiga sampai empat di antaranya, bisa menegaskan bahwa sesuatu yang berada pada dimensi psikologi-spiritual memiliki pengaruh dalam pembentukan karakter, sedangkan karakter dalam bahasa agama itu adalah akhlak dan tentu saja akhlak yang dimaksud di sini adalah akhlak atau karakter yang baik.
Prof. Haedar Nashir (2022) menegaskan “Indonesia dibangun di atas fondasi yang kokoh berupa nilai-nilai ideologis yang bertumpu pada Pancasila dan pandangan hidup yang berlandaskan agama serta berkepribadian berbasis pada kebudayaan nasional yang melekat dengan eksistensi bangsa diperkuat jiwa dan daya perjuangan kebangsaan yang menyejarah dalam lintasan perjalanan bangsa ini”. Dari pandangan Haedar Nashir ini, bisa dipahami bahwa modal yang berada dan beroperasi atau mengalami mekanisme psikis dalam dimensi psikologis-spiritualitas manusia, ternyata menjadi modal utama dan besar bagi kemajuan dan pencapaian material dan infrastruktur bangsa dan negara Indonesia.
Yudi Latif mengutip pandangan John Gardner (2012: 2) “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika tidak sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar”. Yudi Latif mengutip pula pandangan Soekarno ke dalam buku karyanya yang lain “Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita (ideal). Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita ideal itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu dalam bahaya”.
Ahmad Norma Permata (2020: 30) memandang “Bahwa agama dalam sejarah manusia merupakan mekanisme institusionalisasi atau jalan untuk membangun kehidupan, baik memulai sesuatu yang sebelumnya tidak ada seperti sistem Varna dalam Hinduisme, atau meneguhkan sistem yang sebelumnya sudah ada—seperti kesetiaan pada keluarga dalam Konfusianisme, ataupun sekadar menyortir di antara sistem-sistem yang sudah ada seperti Sistem Perkawinan dalam Islam”. Norma permata kembali menegaskan bahwa “Agama sebagai sebuah nilai tidak pernah semata konseptual. Melainkan agama selalu merupakan upaya untuk mengubah kondisi”.
Dari Asep, Haedar, Yudi, dan Norma Permata, kita bisa sampai pada pemahaman dan kesadaran bahwa nilai, ajaran, pandangan, ideologi, dan dalam konteks tulisan ini, termasuk Pancasila, UUD NRI 1945, agama, dan berbagai nilai luhur bangsa sesungguhnya bisa menjadi sesuatu yang berada, beroperasi, dan mengalami mekanisme psikologis-spiritual yang selanjutnya tentu saja memberikan pengaruh terhadap segala sikap (pikiran, perasaan, dan pemaknaan), tindakan, being, dan relating sampai pada pembuatan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam konsep keterpaduan antara dimensi psikologis-spiritual yang berada dalam diri manusia dan segala nilai, ajaran, pandangan, terutama Pancasila, UUD NRI 1945, nilai agama, nilai luhur bangsa yang beroperasi atau mengalami proses mekanisme psikologis-spiritualitas, inilah yang dimaknai dengan “Nalar kebangsaan”.
Lalu bagaimana proses membangun nalar kebangsaan dalam diri Generasi Z itu?
Nilai, ajaran, pandangan, Pancasila, UUD NRI 1945, ajaran agama, dan berbagai nilai luhur bangsa tidak serta-merta bisa berada dan mengalami mekanisme psikologis-spiritualitas dalam diri manusia untuk menjadi nalar kebangsaan. Dibutuhkan minimal peran sunnatullah yang Allah ciptakan di alam semesta tanpa kecuali dalam diri manusia: habits. Membahas habits bisa dilihat dari pandangan Felix Y. Siauw (2015) dan James Clear (2023)
Felix menggambarkan “Bahwa bukan bakat yang lebih berpengaruh dalam keahlian (atau ketidakahlian) seseorang melainkan sesuatu yang lain, yang selanjutnya akan kita sebut sebagai habits (kebiasaan). Dari Felix, kita bisa memahami pula bahwa habits pun memiliki “ayah” yaitu practice (latihan) dan “ibu” yaitu repetition (pengulangan). Yang menarik pula dari Felix yaitu “practice makes right. repetition makes perfect”.
Ada pula ulasan Bagus Takwim dalam Kata Pengantarnya pada buku (Habitus X Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu (Richard Harker, dkk, 2009) bisa menjadi landasan untuk memahami bahwa nilai, ajaran, tanpa kecuali Pancasila, UUD NRI 1945, agama, dan berbagai nilai luhur bangsa bisa sebagai sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konseptual yang terinternalisasi yang selanjutnya hal itu menjadi struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial atau selanjutnya menjadi skema-skema yang memengaruhi bagaimana individu mempersepsi, memahami, menghargai, serta mengevaluasi realitas sosial. Sederhananya, saya pernah terinspirasi dari tulisan seorang aktivis IMM (saya lupa namanya) bahwa habitus itu adalah internalisasi eksterior untuk selanjutnya melakukan eksternalisasi interior.
Konsep habits, habitus ala Bourdieu, dalam pandangan saya meskipun tidak bisa terungkap semua dalam kajian ini, itu relevan dengan—jika merujuk pada pandangan Yudi Latif (dalam Azaki, 2014) —ditegaskan “Setiap ideologi harus mampu memadukan tiga unsur: keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Pertama, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan-tuntunan normatif sebagai pedoman hidup. Kedua, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin, dan teori yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. Ketiga, ideologi mengandung dimensi tindakan yang mengandung level operasional dari keyakinan dan pengetahuan. Saya merasa penting merujuk pandangan Yudi Latif ini, karena bagi saya sejatinya apa yang dimaknai sebagai bagian dari sesuatu yang berada dan berproses atau mengalami mekanisme psikologis-spritualitas dalam diri manusia, akan mampu menjadi nalar kebangsaan, ketika sesuatu itu atau semuanya dipahami dalam perspektif “ideologis”.
Pandangan Yudi Latif di atas terkait yang saya maknai “pandangan ideologis” bisa diperkuat dari pemahaman dan pandangan Gordon Graham (2015: 151-158) tentang nalar. Graham menegaskan bahwa “Para filsuf mengelaborasi perbedaan antara nalar teoritis (theoretical reason) dan nalar praktis (practical reason). Graham melanjutkan “Pembedaan yang dibuat tersebut pada dasarnya menyoal pembedaan antara nalar yang mengarahkan anda padah hal yang harus dipikirkan atau diyakini, dan nalar yang mengarahkan anda pada hal yang harus anda lakukan”.
Cara lain untuk mengonstruksi/membangun nalar kebangsaan dalam diri Generasi Z yang akan menjadi generasi emas, sebenarnya Islam telah mengajarkan tiga metode pembelajaran/pengajaran yang dikenal dengan ta’lim (orientasi intelektualitas), ta’dib (orientasi hati/spiritualitas), dan tarbiyah (orientasi bimbingan fulltime dengan orientasi keseluruhan dimensi dan potensi kecerdasan manusia). Selain itu untuk mengonstruksi nalar kebangsaan dalam diri Generasi Z agar menjadi generasi emas bisa pula dimaksimalkan—meminjam pandangan Dr. Asep—dakwah, uswah (keteladanan), riyadlah (pembiasaan), reward and punishment, tafakur (sering berpikir), tadabbur (sering merenung), zikir, dan muhasabah.
*Pemilik Pustaka “Cahaya Inspirasi”, Wakil Ketua MPI PD. Muhammadiyah Bantaeng, dan Redaktur Opini Khittah.co